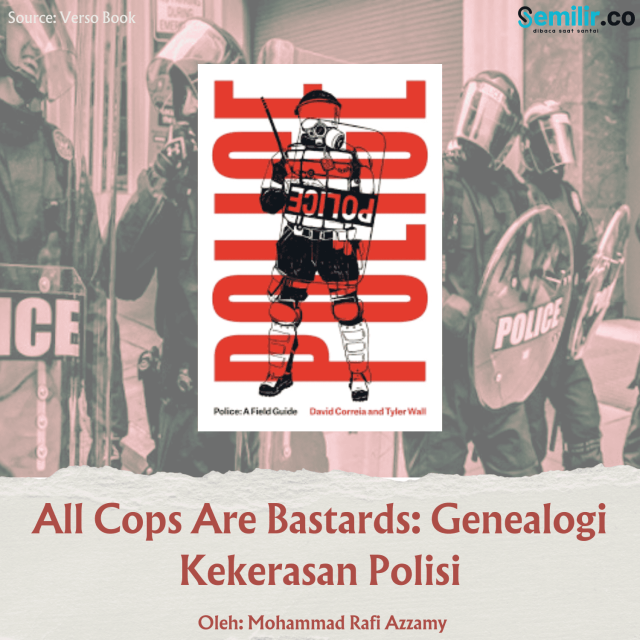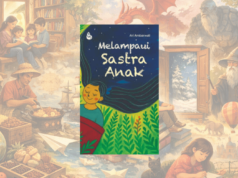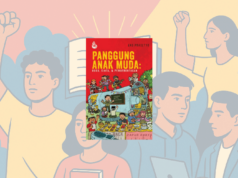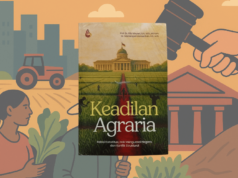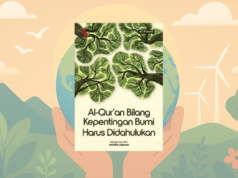Pada halaman pembuka Police: A Field Guide, David Correia dan Tyler Wall membuka dengan kutipan James Baldwin yang mengguncang: bahwa polisi di Amerika Serikat telah “mempolisikan wilayah seperti teritori yang diduduki”. Pernyataan ini bukan metafora, melainkan diagnosis sistemik tentang hakikat kelembagaan kepolisian yang dibangun di atas fondasi kolonial dan bersifat rasial.
Buku yang terbit pada 2018 ini bukan sekadar kritik akademis, melainkan investigasi forensik tentang arsitektur kekerasan polisi. Correia dan Wall membongkar mitos bahwa kepolisian adalah institusi netral penegak hukum, sebaliknya mereka memperlihatkan bahwa polisi adalah mesin kekerasan yang secara sistematis memproduksi dan mempertahankan tatanan rasial kapitalis.
Di Indonesia, genealogi kekerasan polisi memiliki paralelisme yang sama kelamnya dengan analisis mereka. Dari masa kolonial hingga rezim Orde Baru, dan bahkan pasca-reformasi, institusi kepolisian terus memainkan peran sebagai alat represi negara, bukan pelindung masyarakat. Buku ini memberikan kerangka teoritis untuk memahami bagaimana kekerasan bukanlah penyimpangan, melainkan kondisi fundamental kerja polisi.
Akar Kolonial Kekerasan Polisi
Dalam bab Slave Patrol, Correia dan Wall melacak genealogi kepolisian modern yang berakar dari patroli perbudakan di Amerika Serikat. Di Indonesia, genealogi serupa dapat ditemukan dalam pembentukan KNIL (Koninklijk Nederlandsch-Indisch Leger) dan sistem kepolisian kolonial Hindia Belanda. Kedua institusi ini dibentuk bukan untuk melindungi, melainkan untuk mengontrol dan mengeksploitasi penduduk jajahan.
Buku ini menunjukkan bahwa logika kolonial dalam kepolisian dibangun di atas prinsip pemisahan dan kontrol. Dalam konteks Indonesia, hal ini tercermin dalam praktik diskriminatif pada masa kolonial di mana polisi kolonial membedakan perlakuan berdasarkan kategori rasial. Orang-orang Eropa, Tionghoa, dan pribumi memiliki perlakuan hukum yang berbeda, dengan pribumi selalu berada pada posisi paling rentan.
Correia dan Wall berargumen bahwa fungsi utama polisi adalah melindungi kepentingan kelas dominan. Di Indonesia, hal ini terlihat dari sejarah panjang kepolisian yang selalu berpihak pada kekuasaan: dari mendukung sistem tanam paksa di Hindia Belanda, membasmi gerakan antikolonial, hingga menjadi alat represi rezim Orde Baru. Menariknya, buku ini tidak sekadar melihat kepolisian sebagai institusi represif, tetapi juga sebagai produk dari sistem ekonomi-politik tertentu. Setiap tindak kekerasan polisi, menurut mereka, tidak dapat dipisahkan dari logika kapitalisme kolonial yang mengeksploitasi dan mengontrol tubuh-tubuh marjinal.
Copspeak dan Rezim Kebenaran
Salah satu kontribusi teoritis paling orisinil dari Police: A Field Guide adalah konsep “copspeak”—sebuah analisis mendalam tentang bagaimana bahasa digunakan sebagai teknologi kekuasaan untuk menormalisasi kekerasan. Correia dan Wall memperlihatkan bahwa bahasa bukanlah sekadar alat komunikasi netral, melainkan medan pertarungan di mana makna sosial diproduksi dan dikontestasikan.
Mengambil inspirasi dari Georges Bataille dan Michel Foucault, buku ini membongkar bagaimana setiap eufemisme polisional adalah strategi diskursif yang kompleks. Istilah seperti pain compliance tidak sekadar melunakkan terma kekerasan, tetapi aktif mentransformasi tindak represi menjadi tindakan profesional yang rasional. Setiap kata dipilih secara strategis untuk menghapus jejak korban, menghilangkan konteks historis kekerasan, dan mengubah tindakan brutal menjadi prosedur standar operasional.
Copspeak bekerja melalui mekanisme yang jauh lebih canggih daripada sekadar propaganda. Ia menciptakan rezim kebenaran di mana kekerasan tidak hanya dapat dibenarkan, tetapi bahkan dipandang sebagai tindakan profesional dan perlu. George Orwell menjadi sosok kunci dalam pembahasan ini—bagaimana bahasa dapat “membuat kebohongan terdengar benar dan pembunuhan terlihat terhormat”. Setiap eufemisme adalah pertarungan makna di mana kekuasaan berusaha mendefinisikan batas-batas yang dapat dipikirkan dan tidak dapat dipikirkan.
Buku ini mengajak pembaca untuk melakukan dekonstruksi bahasa sebagai langkah awal perlawanan. Copspeak tidak sekadar tentang kata-kata, tetapi tentang bagaimana kekuasaan membentuk imajinasi kolektif tentang kekerasan. Dengan merujuk pada tradisi pemikiran kritis dari filsuf bahasa hingga teoritisi postkolonial, Correia dan Wall memperlihatkan bagaimana setiap pilihan kata adalah pertarungan politik untuk mendefinisikan realitas.
Teknologi dan Metode Kontrol Polisi
Selain mekanisme bahasa. Dalam kerangka analisis Correia dan Wall, teknologi polisi bukanlah sekedar alat pengamanan yang netral, melainkan perpanjangan logika kekuasaan yang kompleks. Buku Police: A Field Guide membongkar bagaimana setiap teknologi—dari senjata api hingga metode interogasi—adalah manifestasi sistemik dari strategi kontrol negara terhadap tubuh-tubuh marginal.
Genealogi teknologi kepolisian tidak dapat dipisahkan dari sejarah kolonial dan kapitalisme. Penulis memperlihatkan bagaimana teknologi kontrol berkembang tidak sebagai respons terhadap kejahatan, melainkan sebagai mekanisme untuk mendisiplinkan kelas pekerja dan kelompok subordinat. Setiap inovasi teknologis polisi adalah upaya untuk mengontrol, memisahkan, dan menundukkan mereka yang dianggap berpotensi mengancam tatanan sosial.
Berbeda dari narasi umum yang melihat teknologi sebagai instrumen netral, buku ini mengajukan proposisi radikal: teknologi polisi adalah teknologi kekuasaan yang aktif membentuk imajinasi sosial tentang keamanan, ancaman, dan ketertiban. Setiap alat, setiap metode, secara fundamental merancang ulang hubungan kekuasaan dalam masyarakat.
Senjata api, misalnya, tidak sekadar alat untuk menangkal kejahatan. Dalam analisis Correia dan Wall, senjata api adalah simbol kekuasaan negara untuk mendefinisikan siapa yang dianggap manusia dan siapa yang tidak. Sejarah penggunaan senjata api oleh polisi adalah sejarah diskriminasi rasial—dari pembantaian penduduk Pribumi hingga pembunuhan massal terhadap aktivis kulit hitam.
Metode interogasi pun tidak sekadar teknik pengumpulan informasi, melainkan teknologi untuk memproduksi kebenaran. Menggunakan kerangka Michel Foucault, buku ini memperlihatkan bagaimana interogasi adalah medan pertarungan di mana kekuasaan berusaha mengekstraksi “kebenaran” melalui serangkaian teknik kekerasan psikologis. Penggunaan ancaman, manipulasi psikologis, hingga penyiksaan adalah cara negara mendefinisikan apa yang dianggap sebagai “kebenaran”.
Teknologi pengawasan digital membuka babak baru dalam genealogi kontrol polisi. Correia dan Wall menunjukkan bagaimana algoritma, data mining, dan teknologi pengenalan wajah tidak sekadar mengumpulkan informasi, tetapi aktif membentuk kategori sosial berbahaya. Setiap data point adalah upaya untuk memetakan, mengklasifikasi, dan berpotensi mengendalikan populasi.
Buku ini mengajak pembaca untuk memahami teknologi polisi sebagai teknologi kekuasaan yang kompleks. Tidak sekadar alat, melainkan cara fundamental di mana negara mendefinisikan batas-batas kebebasan, mengontrol tubuh-tubuh warga, dan memproduksi rezim kebenaran tentang apa yang dianggap aman dan tidak aman.
Dengan merujuk pada tradisi pemikiran kritis dari Marx hingga Foucault, Correia dan Wall memperlihatkan bahwa setiap teknologi polisi adalah pertarungan politik untuk mendefinisikan batas-batas kemanusiaan. Teknologi tidak netral—ia selalu berpihak, selalu mendefinisikan siapa yang dianggap manusia dan siapa yang tidak.