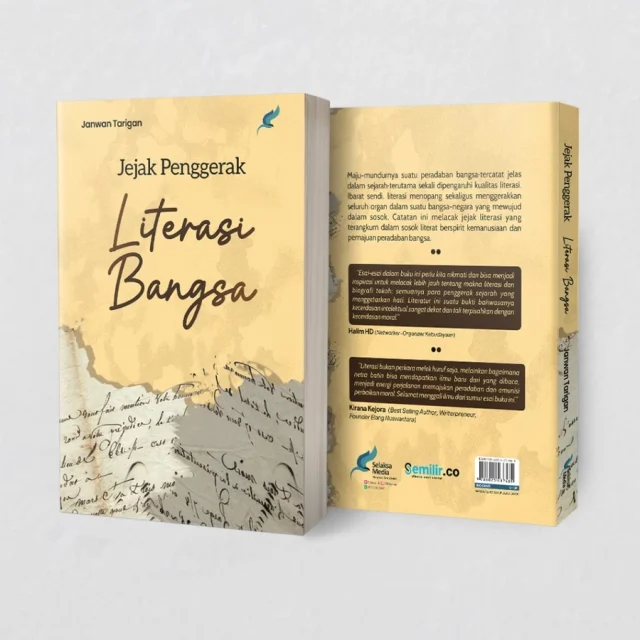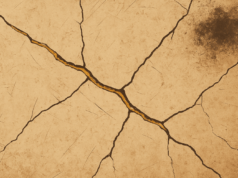Dalam satu dekade terakhir, istilah “literasi” sedang naik daun, menjadi topik pembicaraan di hampir setiap perbincangan. Terasa istilah itu begitu memukau khususnya dalam setiap peristiwa yang ada hubungannya dengan masalah pendidikan dalam berbagai seginya. Tampaknya, tak ada kaum terdidik yang tak menyinggung soal literasi, dan terasa dianggap ketinggalan zaman jika tak menyinggung masalah itu.
Setiap kata atau istilah tentu saja tak muncul seketika. Kata, istilah, dan bahasa menjadi tanda bagi suatu zaman yang sedang terus berubah dan menuntut untuk selalu diikuti perubahan itu oleh siapa saja, jika tidak ingin ketinggalan zaman, atau bahkan digilas oleh waktu perubahan. Persoalannya ialah bagaimana kita memahami sejarah kata itu melalui suatu pendekatan konstekstual, bahwa setiap kata memiliki perkembangan dan perluasan makna berkaitan dengan perubahan dan kebutuhan untuk menggunakannya.
Pada periode pemerintahan Bung Karno pada 1950−1960an, Gerakan Pemberantasan Buta Huruf (PBH) dilaksanakan di kampung-kampung dan di wilayah perdesaan dengan sasaran agar warga dan masyarakat bisa baca dan tulis. Menariknya, saya masih ingat komentar seorang ustaz madrasah, pengajar sekolah agama yang terletak di seberang sungai, yang menyatakan bahwa ada warga yang tidak buta huruf dalam konteks bacaan Al-Qur’an. Saya kurang tahu maksud ungkapan ustaz itu. Namun ada benarnya, bahwa dalam soal kapasitas membaca dan menulis, seseorang ditentukan juga oleh perangkat bahasa yang dikenalnya. Terlepas dari ungkapan yang disampaikan oleh sang ustaz yang selalu berpakaian rapi dan selalu melintasi kampung kami dengan sepeda ontel, konteks PBH yang ingin disampaikan oleh pemerintah adalah bagaimana agar warga dan masyarakat bisa membaca dan menulis dalam bahasa nasional, bahasa Indonesia, dan dengan huruf latin.
Dalam konteks inilah bahasa sebagai perangkat strategis kebudayaan dan peradaban menjadi penting. Walaupun kepentingan itu bisa juga bermakna bagai pedang bermata dua: kapasitas membaca dan menulis melalui bahasa nasional atau bahasa internasional, seperti bahasa Inggris, Perancis, Jerman, Cina, dan Arab menjadi jembatan bagi pergaulan antarbangsa dan menciptakan perkembangan ilmu pengetahuan melalui pemahaman terhadap bahasa yang bersangkutan.
Namun demikian, kita juga harus menyadari bahwa bahasa-bahasa internasional yang disampaikan melalui sastra, agama, dan ilmu pengetahuan menjadi kekuatan yang bisa menguasai suatu bangsa lainnya. Berkaitan dengan hal inilah maka betapa pun juga bahasa nasional bisa sebagai alat propaganda dan indoktrinasi serta alat kontrol pemikiran, menjadi penting dalam menciptakan ikatan kesatuan nasional melalui bahasa. Bahasa Nasional sebagaimana juga bahasa-bahasa lokal yang menjadi modal kultural bagi suatu masyarakat bagai ruang kultural yang terus berkembang dan berubah.
Kita menyaksikan perkembangan bahasa Indonesia yang dibentuk oleh puluhan bahasa yang berasal dari berbagai negeri lain, di samping bahasa-bahasa lokal yang ada di nusantara, seperti juga bahasa lokal yang kita miliki tak sepenuhnya berasal dari dirinya sendiri: interaksi dan relasi antarbudaya yang pernah terjadi di kawasan nusantara ikut membentuk, mengubah, dan mengembangkan bahasa lokal itu sendiri, seperti juga bahasa Indonesia yang terus berkembang. Akan tetapi, kita juga menyaksikan adanya bahasa-bahasa lokal yang kian surut, bahkan menuju kemusnahan penggunanya sebagai dampak dari pengaruh bahasa nasional.
Segi lain yang ingin saya sampaikan berkaitan dengan dunia literasi adalah masalah etik(a). Ketika saya menulis catatan menyambut buku yang ditulis oleh Janwan Tarigan, kondisi sosial politik sedang hangat dan bahkan letupan isu sosial politik terjadi hampir setiap saat, pertempuran isu dan gosip politik melanda dan merasuk ke dalam berbagai ruang sosial dan personal. Poin lain yang ingin saya kaitkan antara literasi dengan etik(a) berkaitan dengan kondisi pendidikan tinggi kita, khususnya yang dalam dua dekade terakhir mengalami sejenis degradasi dalam disiplin dan komitmen keilmuan.
Saya meragukan kaitan kuat antara kesadaran literasi dengan kesadaran politik dalam konteks praktik etik(a). Di dalam struktur kefilsafatan, etik(a) sebagai bunda kandung politik (dan ekonomi) melandasi kajian yang bersifat fundamental. Suatu kerangka politik yang kita hadapi sehari-hari diuji oleh sejauh mana kerangka politik itu memiliki komitmen dan dasar etik(a). Jika suatu kekuasaan politik diraih dengan ambisi yang menghalalkan segala cara, dan dengan kerangka keilmuan yang mendukungnya maka menjadi pertanyaan kita, bukankah pelaku politik itu memiliki kesadaran literasi namun jauh dari kerangka dan dasar etik(a)? Tanpa harus memberikan gambaran tentang para buzzer atau influencer yang dengan sigap dan dengan sejenis kecerdasan analisa kita diperhadapkan pada masalah, bahwa ada suatu makna yang hilang pada saat hasil kajian keilmuan itu disodorkan ke hadapan publik.
Banyak orang menganggap bahwa suatu kajian mestilah diperhadapkan dengan kajian lainnya. Secara keilmuan barangkali benar. Akan tetapi, batas terpenting antara perhadapan suatu kajian dengan kajian lainnya sesungguhnya bukan hanya kerangka teoritik dan data. Di balik itu, ada hal yang lebih fundamental, yakni kaitan antara kepentingan suatu kerangka teoritik dengan tujuan ideal yang didasarkan pada kepentingan masyarakat dan tujuan untuk ikut menciptakan suatu kehidupan berbangsa yang lebih beradab. Namun, kita juga menyaksikan bahwa kerangka keilmuan yang tanpa dasar etik(a) telah menjadi bagian yang secara simultan disorongkan kehadapan masyarakat, dan di balik itu pula jenis keilmuan dengan prinsip pragmatisme diterapkan. Dalam konteks inilah kapasitas literasi seseorang atau suatu lembaga dipertanyakan berkaitan dengan dasar etik(a)nya.
Dunia internet dengan sistem yang makin canggih telah ikut membantu kemajuan dan perkembangan dunia pendidikan. Informasi kian mudah didapat yang membuat seseorang anak didik atau mereka yang sedang menempuh kuliah lanjutan dengan gampang melacak suatu bahan perkuliahan. Ditambah lagi dengan perkembangan teknologi informasi dengan sistem digital maka likuiditas informasi meresap ke dalam berbagai segi kehidupan di dalam kampus dan lembaga pendidikan. Seorang siswa sekolah menengah pertama dengan lancar dan bahkan fasih mengetahui perkembangan informasi. Tentu saja minat terhadap informasi ditentukan dari sejauh mana apresiasi tentang makna informasi yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan sangat menentukan arah anak didik yang bersangkutan. Pada sisi lainnya, dunia internet dengan dukungan teknologi digital membuat segala sesuatu dengan gampang diraih dan dipindahkan. Copy dan paste begitu populer sebagai petunjuk dan perangkat untuk ikut mendukung suatu tulisan atau raihan informasi yang ingin kita sodorkan.
Berkah dunia internet dengan dukungan teknologi digital itu membuat kita bisa ikut memasuki dan memahami dunia global dengan gampang. Akan tetapi, dalam konteks inilah kita menghadapi masalah. Semakin kita memasuki dunia global, sesungguhnya kita ditantang untuk memahami apa yang kita miliki sendiri yang berasal dari lingkungan sosial kita, atau apa yang menjadi dasar pemikiran kita. Perkembangan internet yang kita harapkan ikut mendukung dunia pendidikan dan perkembangan ilmu pengetahuan yang ingin kita raih, ternyata menghadapi masalah. Masalahnya bukan terletak pada kapasitas menggunakan sarana teknologi informasi atau media sosial. Persoalan yang kita hadapi justru terletak pada kondisi sejarah sosial yang jauh sebelum masuknya teknologi informasi dan internet ke dalam masyarakat dan khususnya dunia pendidikan kita, yakni masalah kapasitas menulis yang tak berkembang dampak dari sistem pendidikan yang lebih menekankan hafalan ketimbang pemikiran.
Dunia pendidikan kita terlalu lemah di dalam pengembangan kapasitas menulis sebagai proses pengembangan pemikiran dan imajinasi. Pelajaran mengarang misalnya, menjadi pelajaran yang langka, dan jika pun ada sekadar pelengkap. Dalam konteks itulah terbentuknya kondisi di mana siswa dan bahkan mahasiswa mengalami masalah bisnis ketika mendapatkan tugas menulis makalah, yang berlanjut dalam proses penulisan skripsi. Kegagalan pengembangan kapasitas menulis dan berpikir kritis inilah yang memunculkan dampak lain dan terciptanya suatu keadaan di mana banyak mahasiswa yang melakukan penjiplakan ‘plagiarism’. Dan yang lebih parah lagi, dengan tak ragu mahasiswa yang mengalami kesulitan menulis, memesan skripsi atau tesis dari “pembimbing tersembunyinya”. Bisnis pembuatan makalah, skripsi, tesis berkembang di sekitar kampus. Ironisnya, justru masalah itu tampak dan terasa dianggap hal yang wajar. Padahal, masalahnya bukan sekadar kegagalan pengembangan kapasitas teknis menulis. Lebih jauh dari hal itu, terjadi degradasi etik(a) dalam kehidupan pendidikan dan dunia akademis.
Jika kita ditanya apa makna dari kaum terdidik yang meraih pendidikan tinggi dan berada pada posisi sosial di dalam masyarakat, tentu kita akan menjawab bahwa mereka adalah kaum terpelajar yang telah memahami ilmu pengetahuan dan memahami apa makna ilmu dalam kehidupan masyarakat. Secara teoritik, kita akan menjawab seperti itu, bahkan kita akan menambahkan bahwa mereka adalah kaum yang terpilih dari mayoritas masyarakat yang beruntung menikmati fasilitas pendidikan yang sekaligus identik dengan kelompok dari masyarakat yang secara literasi memahami, minimal wilayah ilmu pengetahuannya.
Namun, seperti gambaran singkat yang saya tuliskan di atas, bahwa posisi pendidikan seseorang tak selalu seiring dengan kapasitas menulis, yang membawa dampak tertuju pada degradasi etik(a) dan hilangnya komitmen moral. Dunia akademis kita penuh ironi. Penulis esai Janwan Tarigan memberikan data yang menarik tentang bagaimana tak produktifnya kaum akademisi kita dalam kaitannya dengan dunia penerbitan atau buku, seperti yang diuraikannya dalam pengantar buku ini.
Membaca esai-esai Janwan Tarigan tentang kaitan literasi dengan lintasan biografi para tokoh membuat saya mendapatkan inspirasi untuk mengaitkan antara literasi dengan etik(a) sehubungan dengan gejala plagiarism, jual-beli makalah-skripsi-tesis yang telah melanda dunia pendidikan tinggi kita. Dalam konteks inilah esai-esai Janwan Tarigan perlu kita nikmati dan bisa menjadi inspirasi untuk melacak lebih jauh tentang makna literasi dan biografi tokoh. Contoh ideal dari para tokoh bukan hanya memahami literasi dalam berbagai disiplin ilmu pengetahuan, dan melalui pelacakan dan pemahamannya pada kandungan literasi yang dipahaminya itu justru menguatkan pandangan dan praktik tentang etik(a). Bung Hatta, Bapak Koperasi Indonesia, merupakan contoh terbaik bagi kita. Sosok yang bagai batu granit moralitas yang dengan teguh perkasa menjadi bukti di dalam kehidupan sosial, politik, ekonomi, dan di dalam kehidupan keseharian yang sederhana, sebagaimana sosok pendiri bangsa Ki Hajar Dewantara, Bung Karno, Mohammad Yamin, Agus Salim, yang dihimpun dalam kumpulan esai Janwan Tarigan, bersama juga dengan sosok Kartini, Multatuli, dan Tirto Adhi Soerjo.
Semuanya para tokoh sejarah yang menggetarkan hati, yang rentang perjalanan kehidupannya sangat inspiratif dalam konteks kehidupan kini bagi kaum muda dari generasi milennial maupun generasi Z. Inspirasi itu bukan hanya dalam soal kapasitas literasi para sosok sejarah yang telah mengisi kehidupan kebangsaan kita. Lebih penting dan sangat mendasar adalah bahwa kapasitas literasinya memiliki kaitan bobot etik(a). Hal inilah juga untuk menunjukkan suatu bukti tentang kecerdasan intelektual sangat dekat dan tak terpisahkan dengan kecerdasan moral, yang pada masa kini kita dihadapkan pada dunia akademis yang amburadul oleh ketiadaan etik(a), sebagaimana juga kehidupan sosial politik di negeri ini.
Suatu pembentukan kehidupan bangsa tentu saja memiliki beragam jalan. Salah satunya melalui dunia sastra. Dalam dunia sastralah sesungguhnya, di samping dunia pendidikan, literasi diawali yang memang dekat dengan masalah kapasitas membaca dan menulis. Melalui dunia sastra, yang juga sangat dekat dengan dunia jurnalisme, literasi berkembang. Perkembangannya bukan hanya pada wilayah kapasitas literasi, melainkan pula terdapat bobot sastra yang ikut membentuk suatu cara berpikir kritis, reflektif, dan eksplorasi daya pemikiran yang memiliki kaitan kuat dengan proses menjadikan warga sebagai anak bangsa yang memiliki kesadaran kesejarahan, keadilan sosial, dan kesadaran diri tentang kaitan antara sastra dengan masalah-masalah kemasyarakatan dan kabangsaan.
Dalam esai esai Janwan Tarigan ini kita disajikan sosok-sosok yang mengarungi dunia sastra dalam jenis karya sastra puisi, novel, dan juga yang berkaitan dengan dokumentasi: Sutan Takdir Alisjahbana, Mochtar Lubis, HB. Jassin, Pramudya Ananta Toer, Y.B. Mangunwijaya, Rendra, dan Sapardi Djoko Damono, yang telah mengisi kehidupan pemikiran dan peradaban masyarakat dan bangsa kita. Jika kini kita bisa memahami sejarah dan kehidupan masyarakat secara mendalam dan dengan imajinasi yang luar biasa, kaum pengarang itu telah mengisi relung-relung terdalam diri kita. Dan, melalui pemahaman karya sastra itulah kita ditumbuhkembangkan sebagai warga suatu bangsa yang terus mencari jati diri.
Di antara penyajian sosok-sosok kesejarahan dalam berbagai bidang, Janwan Tarigan menutup bukunya melalui suatu esai yang sangat menarik, suatu pertemuan dia dengan sosok petani di suatu desa yang berpuluh tahun hanya mengolah tanah. Sang petani tua hanya mengenal lahan yang diolahnya, dan memahami semua lika-liku dari jagat yang setiap hari ditetesi keringatnya. Sang kakek tak menginjakkan kakinya di halaman sekolah, apalagi ruangan kelas. Upayanya untuk membangun dunia impiannya, suatu lahan pertanian yang beragam tanaman dan mengolah lahan secara simultan melalui kesadaran ekonomis, yakni bagaimana menghasilkan produk pertanian yang akan menambah penghasilan hidupnya. Dorongan ekonomis membuatnya mencari kemungkinan jalan lain dalam mengembangkan pengetahuan secara personal melalui belajar membaca dan menulis yang dikuasainya secara belajar mandiri, otodidak, yang ada kaitannya dengan dunia pertanian. Bagi sang kakek, ruang kehidupan merupakan ruang belajar dan di situlah sang kakek tak henti belajar dan menapakkan kakinya langkah demi langkah ke arah penciptaan dan perwujudan impiannya.
Esai penutup ini sangat mengesankan dan ingin menyatakan bahwa proses belajar tak harus dari bangku sekolah dan bangku kuliah. Tantangan kehidupan dan keinginan untuk mewujudkan impian membuat seseorang belajar sebagai jalan menuju impian dambaannya. Dari esai inilah kita kembali menemukan inspirasi etik(a) dan etos kerja yang dibentuk sang kakek bukan hanya dari hari ke hari tapi dari setiap langkah dan setiap helaan napasnya yang menciptakan energi spiritualitas–meminjam ungkapan Romo Mangunwijaya–religiositas: kesadaran mengolah semesta dengan kapasitas kemanusiannya.