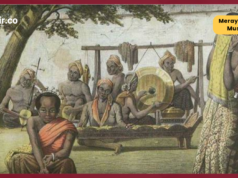Bias cahaya purnama, hawa sejuk sehabis rintik hujan dan irama Gong Waning menghangatkan Malam Bebas Kendaraan Bermotor (Car Free Night), Jalan El Tari, Kota Maumere, 15 Maret 2025. Jika ada yang berbeda dan menarik perhatian, maka itu adalah suara Gong Waning yang mengundang kerumunan orang memenuhi sekeliling panggung.
Tidak ada gitar elektrik, drum, atau piano sebagaimana konser musik modern lainnya. Hanya ada juk, gitarlele, jimbe, keckrek dan bas teren. Ada apa ini? Tentu saja bukan pentas musik rock. Bukan juga semacam reggae party yang sering digelar di Maumere. Ini musik kampung. Ini musik tradisi. Dan Leisplang membuka Jamming Sastra Komunitas KAHE malam itu dengan irama Gong Waning yang penuh semangat. Setelah itu, dari atas panggung, lantunan suara tujuh orang personil Leisplang terdengar begitu magis dan menghipnotis:“Oa Mbele oa nara, nara mbele oa le…oa le.”
Dalam salah satu reportasenya di harian Pos Kupang, jurnalis senior Gerardus Manyela menulis, syair Oa Mbele sering didendangkan pada musim persiapan tanam yang dinyanyikan oleh kelompok kerja berjumlah 20 sampai 40 orang di tengah-tengah ladang. Biasanya hentakan cangkul yang membentur tanah mengiringi nyanyian Oa Mbele. Cangkul diayunkan ke tanah secara serentak sampai sepetak ladang digembur habis dan siap untuk ditanami.
Tradisi menggembur tanah ladang secara gotong royong ini disebut Sakoseng di wilayah Kangae, Sakojung di wilayah Kewapante dan Papapoa di wilayah Lio. Kelompok ini secara bergilir menggembur tanah milik anggota kelompok. Hari ini di kebun A, besok di kebun B, lusa di kebun C dan seterusnya. Pemilik kebun hanya perlu menyiapkan makanan dan minuman seperlunya saja.
Oleh Leisplang, Oa Mbele hadir lagi dengan aransemen yang berbeda, tetapi bukan di tengah ladang di kampung Watublapi. Bukan pula dalam konteks kehidupan kolektif masyarakat pertanian atau tradisi gotong royong Sakoseng. Oa Mbele mengalun di tengah-tengah pasar kuliner di mana selera sangat ditentukan oleh logika kapitalisme, ia hadir saat orang-orang sedang melepas penat lelah bekerja sehabis mengejar cuan sebanyak-banyaknya, ia juga ada di saat semangat individualistik merasuk ke dalam denyut kehidupan modern Kota Maumere.
Leisplang sadar akan kondisi-kondisi ini. Iming-iming modernisme membuat hidup semakin kompleks, semakin jauh orang meninggalkan tradisi yang berakar pada tanah, kampung, rumah dan ingatan-ingatan.
Beberapa lagu original yang belum dirilis dipersembahkan khusus pada malam jamming sastra tersebut. Pencipta lagu, vokalis dan musisi Leisplang Erick Bagoest membuat suasana menjadi lebih ramai dengan tutur cerita berbahasa Krowe-Sikka seperti orang yang sedang mendongeng.
“Moke itu identitas kita,” serunya berulang kali sembari meneguk minuman tradisional yang disadap dari pohon lontar tersebut. Erick bilang moke tidak merusak generasi muda Maumere. Generasi muda yang tidak bisa mengontrol dirilah yang merusak citra moke. Minuman sakral yang sering disajikan saat ritual adat berubah menjadi minuman haram yang memabukkan di tenda tenda pesta dan di pinggir jalan. Leisplang meluruskan salah kaprah semacam ini. Seruan ini sontak disambut tepuk tangan membahana.
Demikianlah, mendengarkan Leisplang seperti menyimak wejangan orang tua di kampung. Kelompok musik tradisi ini laiknya para petani dulu yang gemar berbalas syair di bawah sinar terang purnama pada malam pesta panen. Syair-syairnya punya cita rasa sastrawi yang dalam, penuh makna.
Peristiwa pertunjukan di Jalan El Tari itu pun serupa pesta panen semalam suntuk. Sebagai bentuk syukur atas panen berlimpah, orang-orang makan dari hasil kebun, minum moke dan bergoyang ria dengan penuh sukacita. Lagu seperti Bako Koli (cover), ½ Gila, Bekor, Sora, Pertanian, Yesenia, Buru Boreng, dan Gong Waning membakar semangat para penonton yang ingin meregangkan otot.
Saya ada di tengah kerumunan ‘pesta panen’ ini, dan untuk pertama kalinya ‘mengalami’ Leisplang.
Pada kesan pertama, lagu mereka yang berjudul Batas membuat saya tertegun kagum. Lagu ini sebenarnya merupakan bagian dari inisiatif “Frekuensi Perangkap Tikus: Menenun Suara Timur” oleh Indonesia Corruption Watch (ICW). Inisiatif ini memakai musik sebagai medium untuk menyoroti perjuangan komunitas adat yang menghadapi ancaman atas tanah leluhur mereka.
Batas berbicara tentang tanah leluhur yang hilang, konflik tanah, tanah yang dicaplok seenaknya. Hilang tanah hilang pula identitas. Leisplang menggambarkan situasi nyata hari hari ini di Flores.
Di Maumere, lagu ini seharusnya punya efek kejut lebih. Persis setelah Batas dirilis resmi, konflik perebutan lahan di Nangahale, kawasan pertanian sebelah timur kota Maumere, pecah. Sebuah perusahaan korporasi milik Keuskupan Maumere menggusur rumah-rumah warga dengan moncong ekskavator di atas tanah eks HGU (Hak Guna Usaha) Nangahale.
Perusahaan mengklaim kepemilikan ratusan hektar tanah perkebunan tersebut dengan bukti sertifikat HGU. Sementara masyarakat adat mengklaim balik dengan cerita turun temurun bahwa tanah itu dicaplok oleh perusahaan pemerintah kolonial Belanda hampir seabad lalu. Tanah milik masyarakat adat itu kemudian diperjualbelikan kepada perusahaan milik gereja katolik.
Bagi masyarakat adat, perjuangan mempertahankan tanah adalah perlawanan kepada korporasi yang ingin merusak harga diri mereka. Semangat perlawanan ini tercermin dari ungkapan dalam bahasa Krowe Sikka, Tana Amin Moret Amin, yang berarti ‘Tanah Kami Hidup Kami’.
Leisplang menegaskan ungkapan ini dalam syair yang mereka adaptasi dari Kitab Amsal dalam Perjanjian Lama,“Jangan kau pindahkan batas tanah yang lama/tanah pertiwi warisan leluhur/Jangan kau pindahkan batas tanah yang lama/ini tanahku ini hidupku.” (Amsal 22: 28 dan 23:10)
Bas teren yang dibetot dengan sentuhan irama Melayu, genjrengan juk yang cepat, nada biola yang lembut berpadu dengan lentingan sopran, alto dan tenor dari masing-masing vokalis sudah cukup elegan memberi energi kepada syair-syairnya yang kritis membaca tanda-tanda zaman.
Musik Leisplang memang tidak pernah gagal membuat tubuh bergoyang. Ini alasan lagu-lagu mereka laris manis diputar di tenda-tenda pesta. Namun, lagu Batas sejenak menunda hasrat orang untuk bergoyang dan bersenang-senang, seperti dalam refleksi Erick tentang Batas. Lagu ini, kata Erick, tidak hanya bicara soal tanah. Batas bisa dipahami lebih jauh, bahwa orang hidup harus tahu batas.
Hidup itu ada batasnya. Keserakahan, keangkuhan dan kemunafikan bermula dari sikap manusia yang tak tahu batas. Gaya hidup yang modern/kolonial menuntut individu mengumpulkan kapital sebanyak-banyaknya dan menimbun harta setinggi-tingginya. Tak ada batas untuk indikator ‘sebanyak-banyaknya’ dan ‘setinggi-tingginya’ dalam dunia yang terkungkung kapitalisme.
Ibarat perjalanan menyusuri hutan belantara, Leisplang serupa suar di tengah kegelapan yang mengingatkan bahwa di pundak kita ada beban berat kolonialisme. Laku hidup masyarakat bertani ladang yang kaya akan nilai nilai spiritual tercabik-cabik dalam sekejap mata. Religiositas masyarakat adat yang seyogyanya terkoneksi dengan alam terputus seketika akibat pemahaman tentang sejarah, ingatan-ingatan dan tradisi mereka diubah oleh agen-agen kolonialisme.
Tanah/alam yang punya jiwa, roh, dan kekuatan berubah profan dan dipandang sebagai material-material teknis belaka yang bisa dieksploitasi seenaknya. Modernisme dengan janji-janji pembangunannya adalah gestur yang sengaja ditampakkan secara kasat mata. Akan tetapi, apa yang sengaja tidak diperlihatkan ternyata penuh luka menyakitkan; penggusuran, kekerasan, pemusnahan terhadap tradisi dan sejarah panjang peradaban masyarakat adat.
Pablo Neruda sering berkata bahwa setiap penulis Amerika Latin berjalan sambil menyeret raganya yang berat; raga masyarakatnya, raga masa lalunya. Atau mungkin juga dengan penegasan yang lebih tajam seperti yang diutarakan Carlos Fuentes: “Kita harus mengasimilasi beban berat masa lalu kita agar tidak lupa apa yang memberi kita hidup. Bila kau lupakan masa lalumu. Matilah kau!”
Di Maumere, Leisplang turut menyeret beban berat masa lalu persis seperti yang diungkapkan Pablo Neruda atau Carlos Fuentes. Bisa jadi karena beban berat yang dipikul itu suara mereka malah makin kencang:
“Tota itan tora mitan, paga itan tora bura/ Tena wu’un naha bitak, tena larun, naha bewar/ Ami depo inan duru mole ami rena naruk aman donen/ Depo inan ata dulak bua, diri aman ata l’oran ga’e…”(Kami memperjuangkan hal yang sebenarnya yang sudah menjadi warisan leluhur/ Harus ada solusi yang dihasilkan/ Dan kami akan selalu mengikuti nasihat dan menjawa warisan ibu pertiwi serta leluhur kami demi kelestarian dan peradaban kehidupan)
Sebelum Leisplang menutup pertunjukan, Eka Putra Nggalu, Direktur Komunitas KAHE Maumere, setengah berteriak di telinga saya, “Seluruh pertunjukan ini adalah resistensi!”
“Dan juga pemberontakan,” saya hanya membatin.
Catatan:
Gong Waning: Alat musik tradisional masyarakat Kabupaten Sikka.
Moke: Minuman tradisional beralkohol masyarakat Flores yang disadap dari tanaman lontar atau enau.
Jamming sastra: Salah satu platform seni Komunitas KAHE Maumere yang menyediakan panggung kepada musisi Maumere/Flores untuk mempresentasikan gagasan atau ide di balik karya-karya originalnya di hadapan publik.
Ulasan lengkap tentang konflik tanah Nangahale di Kabupaten Sikka bisa diakses di banyak media massa seperti Kompas, Tempo, BBC Indonesia, Narasi, Floresa.co, Pos Kupang, Tribun Flores dan media regional lainnya.
Referensi:
Agustinus, Ronny. Macondo, Para Raksasa, dan Lain-Lain Hal. Yogyakarta: Penerbit Tanda Baca, 2021.
Pos Kupang edisi Minggu, 12 Oktober 2008