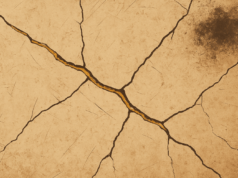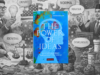Saya masih mengingat satu momen kecil yang terus melekat dalam ingatan. Seusai kuliah, saya berbincang santai dengan seorang dosen perempuan. Dalam obrolan ringan itu, ia berkata sambil tersenyum, “Perempuan biasanya nggak tahan lama di dunia akademik, apalagi kalau sudah menikah. Paling-paling jadi dosen biasa, lalu sibuk urus anak.” Ucapan itu disampaikan seolah sebagai gurauan, mungkin tanpa niat merendahkan. Namun, bagi saya, kalimat itu jatuh seperti palu.
Saya tiba-tiba sadar, itulah cara halus sistem mengingatkan tentang siapa yang dianggap layak bermimpi lebih tinggi, dan siapa yang sebaiknya cukup puas di tempatnya.
Kalimat yang terbungkus tawa itu adalah gambaran nyata bagaimana seksisme bekerja dalam dunia akademik. Ia tidak selalu hadir dalam bentuk kasar atau terang-terangan. Ia menyusup dalam komentar santai, dalam pembagian tugas yang tidak setara, dalam undangan rapat yang tak kunjung datang, atau dalam pujian semu yang menutupi ketidakpercayaan. Seksisme akademik beroperasi dalam bentuk-bentuk halus yang kerap dianggap wajar. Dan karena itulah, ia begitu sulit dilawan, dan begitu berbahaya.
Benteng Ilmu yang Sarat Bias
Kita sering mengidealkan kampus sebagai benteng terakhir rasionalitas dan keadilan. Namun realitasnya tak selalu seindah itu. Di balik dinding-dinding perpustakaan dan aula akademik, masih tersembunyi warisan panjang ketimpangan gender yang dibungkus jargon elitis: meritokrasi, netralitas, dan profesionalisme.
Struktur akademik di banyak institusi masih dibentuk dengan wajah dan semangat maskulin. Posisi strategis seperti dekan, rektor, atau kepala lembaga penelitian kerap diisi oleh laki-laki. Sementara perempuan akademisi, meskipun kompeten, lebih sering dibebani tugas administratif, pengajaran dasar, dan kegiatan pendukung yang kurang dianggap prestisius. Ini bukan kebetulan. Ini adalah hasil dari desain organisasi yang sejak awal memberi ruang lebih luas bagi tubuh laki-laki, yang dianggap tidak terbebani urusan domestik dan lebih “bebas” secara sosial.
Ironisnya, kampus yang katanya tempat membongkar ketidakadilan masyarakat malah justru kerap membiarkan ketimpangan di depan matanya sendiri.
Meritokrasi: Ilusi yang Dipelihara
Salah satu narasi yang paling sering digunakan untuk menampik kritik terhadap ketimpangan gender adalah konsep meritokrasi. Dunia akademik kerap menyatakan bahwa siapa pun, tanpa memandang jenis kelamin atau latar belakang, memiliki peluang yang sama untuk sukses selama ia bekerja keras. Narasi ini terdengar luhur, tetapi seringkali tak sesuai dengan kenyataan.
Perempuan dalam dunia akademik tidak memulai dari garis yang sama. Mereka harus menghadapi tantangan ganda: beban sosial sebagai pengasuh utama, bias dalam penilaian kinerja, minimnya figur panutan perempuan, hingga standar ganda dalam kepemimpinan. Perempuan yang tegas kerap dilabeli agresif, sementara yang lembut dianggap lemah.
Meritokrasi kehilangan maknanya jika sistem tidak mengakui bahwa jalur menuju prestasi dibangun di atas tanah yang tidak rata. Kalimat “kalau memang pantas, pasti sudah naik” hanya menjadi bentuk lain dari pembenaran struktural yang menyamarkan keberpihakan sistemik terhadap laki-laki.
Keheningan yang Sistematis
Seksisme dalam dunia akademik tak hanya berlangsung lewat tindakan, tetapi juga lewat keheningan yang sistematis. Perempuan yang menyuarakan ketidakadilan sering kali dicap “sulit,” “bikin repot,” bahkan “tidak loyal terhadap institusi.” Mereka menghadapi risiko reputasi yang rusak, hubungan profesional yang terganggu, hingga peluang promosi yang tertutup.
Tak sedikit yang akhirnya memilih diam. Mereka paham, menyuarakan ketimpangan bisa berarti membakar jembatan. Dalam dunia akademik yang sangat mengandalkan relasi profesional, menjadi “troublemaker” adalah risiko yang tak semua orang sanggup menanggung.
Siklus ini terus berlangsung. Semakin banyak yang diam, semakin kuat kesan bahwa tidak ada masalah. Dan saat masalah tak terlihat, upaya perubahan menjadi semakin berat. Dalam konteks ini, keheningan bukan hanya gejala dari ketidakadilan, tetapi bagian dari mekanismenya.
Jangan Terkecoh oleh Pencapaian Individu
Memang benar, tidak semua perempuan mengalami hambatan yang sama. Beberapa berhasil menembus batas sistem dan mencapai posisi puncak. Namun pencapaian individual tak bisa dijadikan bukti kesetaraan. Justru sering kali, keberhasilan segelintir perempuan dijadikan alasan institusi untuk menghindar dari kritik. “Buktinya, ada kok perempuan yang jadi profesor.”
Yang tidak dibicarakan adalah harga yang harus mereka bayar: kerja berkali lipat, pengorbanan waktu personal, bahkan menutupi bagian dari identitasnya agar bisa “diterima” dalam sistem yang tak dirancang untuk mereka. Tak jarang, mereka akhirnya turut menjaga status quo, bukan karena setuju, tapi karena merasa tak punya pilihan.
Kita tidak sedang membicarakan siapa yang menang atau kalah, tetapi tentang sistem yang begitu rumit dan penuh jebakan sosial maupun emosional, hingga upaya perubahan pun terasa melelahkan secara eksistensial.
Kini, Saatnya Bersikap
Seksisme dalam dunia akademik bukan sekadar urusan individu. Ini adalah masalah struktural yang membentuk siapa yang layak bersuara, siapa yang layak didengar, dan siapa yang sebaiknya tetap di pinggir. Jika universitas, sebagai institusi yang mengklaim membawa pencerahan, tak mampu menciptakan ruang yang adil, maka ia telah gagal menjalankan misinya.
Kini kita dihadapkan pada pilihan penting: terus menjaga keheningan demi kenyamanan semu, atau membuka luka dan mulai membangun budaya akademik yang setara dan inklusif. Saya percaya, perubahan dimulai dari keberanian untuk bersuara. Mungkin tak langsung berdampak besar, tetapi setiap suara adalah pijakan awal menuju dunia akademis yang lebih adil.
Sudah waktunya kita berhenti menulis lagu yang tak pernah dinyanyikan. Sudah saatnya kita bersuara.