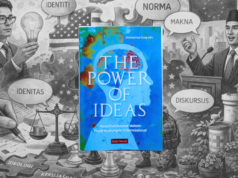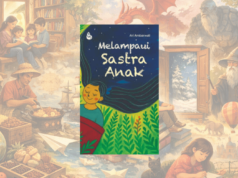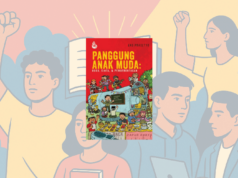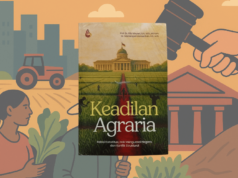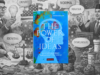Kepada mereka yang percaya bercerita adalah bagian dari perawatan jiwa.
Leila S. Chudori membuka Namaku Alam dengan ‘ledakan’ tersebut. Lebih dari sekadar menyampaikan pengalaman hidup, ‘bercerita’ di sini adalah bekerja untuk merajut sejarah yang tercecer menjadi satu kesatuan narasi yang bulat dan utuh. Dengan mengangkat kisah tentang Alam, Leila mengelaborasi pengalaman pahit seorang anak tahanan politik di era Orde Baru. Diskriminasi secara struktural dan stereotip dari orang-orang terdekatnya sendiri adalah makanan sehari-hari yang didapat oleh Alam. “Anak pengkhianat negara,” begitulah Alam disebut.
Berangkat dari pengalaman itu, ditambah dorongan dari guru sejarahnya dan photographic memory yang dimilikinya, Alam berusaha menulis ulang sejarah keluarganya dan sejarah Indonesia yang tenggelam. Dan itulah yang membawanya ke sebuah jalan yang saat itu hanya sedikit sekali orang yang berani melewatinya: melawan penindasan epistemik yang dilakukan oleh pemerintahan Orde Baru.
Narasi Tunggal Orde Baru: Upaya Epistemisida
Menurut sosiolog Boaventura de Sousa Santos, epistemisida adalah upaya untuk membunuh sistem pengetahuan di dalam masyarakat. Berangkat dari praktik kolonialisme yang memaksa negara-negara non-barat untuk mengadopsi model pengetahuan sistem barat yang dianggap lebih maju, epistemisida dalam perkembangannya bergerak ke arah yang lebih ironis: pencatatan narasi tunggal oleh penguasa dan penumpasan terhadap narasi-narasi alternatif. Dan, itulah yang Alam rasakan ketika hidup di zaman Orde Baru.
Dalam sejarahnya, Orde Baru membuat narasi tunggal bahwa dalang di balik peristiwa G30S yang menewaskan tujuh jenderal di Lubang Buaya adalah Partai Komunis Indonesia (PKI). Alhasil, para tertuduh PKI diburu kemana-mana. Mereka yang ada di dalam negeri dipenjara atau dibunuh. Mereka yang berada di luar negeri, seperti diceritakan dalam novel Leila yang lain, Pulang, tidak bisa kembali ke Indonesia karena dicabut kewarganegaraannya.
Keluarga para tertuduh PKI hidup merunduk di bawah bayang-bayang senapan dan sepatu lars aparat, dan itulah yang Alam rasakan sejak umur tiga tahun. Sejak Hananto Prawiro, ayah Alam, menjadi buronan aparat, rumah Alam selalu disatroni aparat yang bertubuh besar, berambut pendek, dan bersuara menggelegar (hal 20).
Mereka juga dibawa ke markas Kodim di Jalan Budi Kemuliaan. Di sana, Ibu Alam diinterogasi selama berjam-jam setiap harinya oleh aparat dan Bunga Kenanga, kakak tertua Alam, disuruh membersihkan ruang bekas penyiksaan.
Di sekolah, pelajaran sejarah juga dicatat dari kacamata penguasa. We… we have been deprived by our own history (hal 245). Murid sekolah di seluruh Indonesia sangat jauh dari memahami sejarah bangsanya sendiri secara utuh. Orde Baru sebagai pencatat sejarah telah memilah dan memilih peristiwa yang dicatat agar dapat melanggengkan kekuasaan mereka. Padahal, seperti yang disebut oleh filsuf Jerman Walter Benjamin, tidak ada peristiwa yang sudah terjadi yang boleh dianggap hilang dari sejarah.
Tim Pencatat Sejarah: Demokrasi Pengetahuan
Pengekangan terhadap narasi alternatif tidak melulu diikuti oleh sikap merunduk yang terus-menerus. Justru, karena penindasan itu, muncullah kelompok-kelompok yang merasa “ada yang salah dengan narasi yang kita terima”. Dari sana, narasi anti epistemsida kemudian muncul, yang oleh Rajesh Tandon dan Budd L. Hall disebut sebagai demokrasi pengetahuan. Secara sederhana, demokrasi pengetahuan adalah pengakuan terhadap keberagaman epistemik, termasuk pengetahuan dari kelompok yang termarjinalkan.
Tim Pencatat Sejarah (TPS) adalah representasi dari gerakan anti epistemisida itu. Saat SMA, Alam dan teman-teman ‘ideologisnya’ membangun kembali ekstrakulikuler itu setelah hampir dibubarkan karena kekuarangan peminat. Dengan visi untuk ‘mengisi kekosongan sejarah’, TPS melakukan diskusi dan analisis terhadap sejarah underground Indonesia.
Jangankan dibahas di pelajaran sekolah, sejarah yang menjadi objek kajian TPS adalah sejarah yang sangat minim ditulis oleh para ahli saat itu. Dan, ya, salah satu yang dibahas adalah Peristiwa ‘65, termasuk karya-karya dari para eks tahanan politik.
Ada cerita menarik dalam novel ini ketika Alam dan teman-teman TPS-nya berjuang untuk mendapatkan Bumi Manusia karya Pramoedya Ananta Toer. Sejak 1981, pemerintah mengumumkan berbagai buku yang dilarang peredarannya, salah satunya Bumi Manusia yang dianggap menyebarkan paham komunis. Alhasil, seperti adegan detektif atau transaksi gelap di film-film, Alam dan teman-temannya harus sembunyi-sembunyi dan menerapkan berbagai intrik untuk mengelabui intel saat membeli novel itu.
Bayangkan, betapa epistemisidanya rezim saat itu hingga membeli sebuah buku saja tdak lepas dari pantauan aparat keamanan. Sebuah zaman yang semoga tidak akan pernah terulang lagi di Indonesia.
Selain dari cerita yang diangkat, Leila dan Namaku Alam sebenarnya juga manifestasi dari anti epistemisida atau demokrasi pengetahuan itu sendiri. Tentang perjuangan Leila untuk menulis sejarah yang ‘tersembunyi’ adalah caranya untuk mengangkat suara mereka yang tenggelam dan mencatat sejarah yang tidak pernah dicatat di buku-buku sejarah ‘resmi’.
Di tengah proses penulisan ulang sejarah ‘resmi’ dan pernyataan salah satu pejabat pemerintahan yang menghapus pengalaman korban tragedi ‘98 beberapa waktu lalu, Namaku Alam dan novel-novel sejenisnya adalah narasi alternatif yang patut dipertahankan, dan jika perlu dikembangbiakkan, keberadaannya.
Identitas Buku

Judul Buku: Namaku Alam
Penulis: Leila S. Chudori
Penerbit: Kepustakaan Populer Gramedia
Tahun Terbit: Cetakan IV, 2023
Tebal Halaman: ix + 438 halaman
ISBN: 978-623-134-082-5