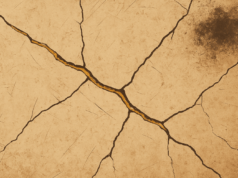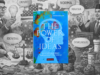Kesadaran Kritis sebagai Ancaman bagi Rezim
Belakangan di media sosial ber-sliweran video para anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia berjoget-joget, para menteri dan presiden pun tak kalah banyak video yang menampilkan mereka berjoget sambil berpesta. Belum lagi beberapa bulan terakhir juga beredar postingan di media sosial mengenai pernyataan “jika gaji Anda 5 juta, bekerjalah seperti orang yang bergaji 10 juta karena kelebihan tersebut akan “dibayar” dalam bentuk lain di masa depan, seperti rezeki yang tak terduga, kesehatan yang baik, atau peluang karir yang lebih baik“.
Sangat ironis ketika para pejabat dan elite borjuis dengan asiknya berpesta dan berjoget di hadapan publik, masyarakat justru terus dibombardir dengan narasi “kerja lebih keras” dan “bersyukur”. Pernyataan seperti “jika gaji 5 juta, bekerjalah seperti bergaji 10 juta” bukan sekadar motivasi kosong, tetapi bagian dari ideologi yang menormalisasi eksploitasi. Ia mendorong pekerja untuk menerima upah rendah sebagai sesuatu yang wajar, bahkan memuji kerelaan mereka untuk bekerja lebih tanpa kompensasi.
Narasi semacam ini membuat masyarakat lupa bahwa masalahnya bukan kurang kerja keras, melainkan distribusi kekayaan yang begitu timpang. Di saat satu kelas bisa menikmati kemewahan tanpa bekerja secara produktif, sementara kelas lainnya dipaksa meyakini bahwa satu-satunya jalan keluar adalah lebih patuh dan lebih rajin. Inilah salah satu bentuk politik pembodohan yang secara halus membungkam kesadaran kritis: menggantikan pertanyaan “mengapa upahku rendah?” dengan “apakah aku sudah cukup bersyukur dan bekerja keras?”.
Pendidikan yang semestinya membangun nalar kritis justru dibentuk untuk semakin meneguhkan pola pikir yang tidak kritis bahkan anti kritis. Tak jarang sesama masyarakat saling bergesekan ketika ada yang mengkritisi bahkan menuntut upah serta hidup yang layak, mereka yang kritis bukan hanya oleh penguasa dan borjuis namun juga oleh sesama masyarakat dianggap sebagai pengganggu. Ruang pendidikan pun semakin menjauh dari upaya membangun nalar kritis; ia berubah menjadi sekadar pabrik keterampilan pragmatis yang menyiapkan tenaga kerja patuh. Lembaga pendidikan dianggap sukses jika menghasilkan lulusan-lulusannya bekerja di perusahaan ternama, lembaga pendidikan menghindari menghasilkan lulusan-lulusan yang membangun kegelisahan dalam masyarakat agar terciptanya masyarakat kritis. Tulisan ini berangkat dari keyakinan bahwa kondisi tersebut bukanlah hasil dari ketidaksengajaan, melainkan bagian dari strategi rezim dan kelas borjuis untuk memastikan rakyat tetap tidak kritis dan mudah dikendalikan.
Rezim dan Kelas Borjuis: Siapa Mereka dan Apa Kepentingannya
Rezim dan kelas borjuis tidak hadir secara alamiah, juga bukan sekadar sekelompok individu yang menempati posisi strategis. Mereka dibentuk oleh struktur sosial dengan kepentingan yang sangat jelas, baik ekonomi maupun politik. Tujuan utamanya adalah mempertahankan dominasi atas masyarakat. Mereka berada di pucuk lembaga negara, menguasai jalur distribusi kekayaan, serta mengendalikan sumber-sumber informasi. Dalam kerangka ini, negara tidak bisa dianggap netral; keberpihakannya selalu ditentukan oleh kelas mana yang berkuasa. Jika kelas borjuis memegang kendali, maka negara berfungsi sebagai alat untuk menjamin keamanan kepentingan mereka. Karena itu, setiap kebijakan, regulasi, hingga narasi publik yang muncul, tidak lepas dari upaya menjaga keberlangsungan kekuasaan.
Keberlangsungan hidup kelas borjuis sepenuhnya ditopang oleh akumulasi kapital. Tanpa akumulasi itu, mereka akan kehilangan sumber kehidupannya. Namun, kapital tidak berputar dengan sendirinya—ia digerakkan oleh kerja kelas pekerja. Dengan demikian, kelas pekerja adalah “mesin” yang membuat kapital borjuis tetap hidup. Di Indonesia, dinamika ini terhubung erat dengan oligarki, di mana politik dan bisnis saling menopang. Kekuasaan digunakan untuk memperluas kepentingan ekonomi kelompok penguasa, sementara instrumen negara digerakkan untuk menjaga dominasi. Tidak mengherankan bila sebagian besar politisi di Indonesia sekaligus adalah pengusaha, agar mereka bisa terus mengamankan kepentingannya.
Aparat negara, seperti militer dan polisi, sejatinya bertugas melindungi rakyat. Namun karena intervensi kepentingan politik dan ekonomi, mereka justru berubah menjadi alat untuk menindas rakyat. Tidak jarang, penggusuran lahan oleh perusahaan besar berlangsung dengan perlindungan aparat, sehingga terjadi bentrokan dengan masyarakat. Perlawanan rakyat direpresi dengan pentungan, gas air mata, bahkan peluru. Media massa kemudian menggiring opini bahwa masyarakatlah yang bersalah. Jika perlawanan dianggap terlalu mengancam kekuasaan, berita tentangnya bahkan tidak disiarkan sama sekali agar semangat perlawanan tidak menyebar.
Lebih jauh lagi, sistem pendidikan pun berfungsi sebagai alat mempertahankan kekuasaan. Pendidikan diarahkan untuk membentuk manusia yang patuh, bukan kritis. Tujuannya jelas: menjaga status quo—upah murah, pasar bebas bagi modal, dan stabilitas politik yang menguntungkan mereka. Kekuasaan kelas borjuis tampak kokoh, tetapi sesungguhnya rapuh karena bergantung pada eksploitasi kelas lain. Inilah celah yang selalu dapat dipertanyakan dan digugat oleh kesadaran kritis. Dominasi tidak hanya dijaga dengan senjata atau regulasi, melainkan juga dengan strategi yang lebih halus: politik pembodohan.
Strategi “Pembodohan” sebagai Instrumen Politik Kekuasaan
Dominasi kelas penguasa tidak hanya serta merta menggunakan kekerasan fisik melalui aparatus yang represif. Represi memang merupakan cara ampuh untuk menakut-nakuti perlawanan rakyat, namun tidak mampu membungkam secara permanen. Oleh sebab itu kekuasaan memerlukan cara yang memiliki dampak jangka panjang dan lebih halus agar rakyat tidak sadar sedang di represif, yaitu dengan strategi pembodohan. Pembodohan di sini tidak boleh dipahami sekadar sebagai ketidaktahuan rakyat, melainkan suatu kondisi yang sengaja diproduksi secara sistematis oleh kelas berkuasa agar rakyat tetap tunduk dan kehilangan daya kritis. Dengan strategi ini, ketidakadilan diterima sebagai sesuatu yang wajar, perlawanan dianggap sia-sia, bahkan rakyat diarahkan untuk merasa bersalah ketika berusaha melawan.
Strategi pembodohan ini paling ampuh melalui jalur pendidikan. Pendidikan bukan diarahkan untuk membebaskan, melainkan mendisiplinkan dan mencetak tenaga kerja patuh. Maka kurikulum pendidikan dibuat bukan untuk memancing peserta didik berpikir melainkan hanya untuk disuapi. Dalam konteks ini, pemikiran Paulo Freire menjadi sangat relevan. Freire menyebut bahwa pendidikan yang dijalankan oleh kelas penindas cenderung menggunakan “konsep pendidikan gaya bank“, di mana peserta didik diperlakukan seperti wadah kosong yang harus diisi dengan informasi secara satu arah. Pendidikan semacam ini tidak dimaksudkan untuk mendorong nalar kritis, melainkan untuk mereproduksi pola pikir yang patuh terhadap tatanan yang ada. Dengan kata lain, pendidikan dijalankan bukan sebagai proses pembebasan, tetapi sebagai mekanisme yang mempertahankan kekuasaan. Inilah yang hari ini kita saksikan dalam sistem pendidikan nasional: kurikulum yang menekankan hafalan, menghindari pertanyaan-pertanyaan kritis, dan menjauhkan peserta didik dari kesadaran akan realitas sosial yang menindas.
Mengapa Kesadaran Kritis Membahayakan Rezim
Masyarakat yang kritis cenderung tidak bisa dikontrol atau ditundukan karena mereka akan terus mempertanyakan segala sesuatu termasuk sebuah kebijakan yang dibuat oleh penguasa. Pendidikan kritis yang disebut oleh Freire sebagai “pendidikan hadap-masalah” tidak dapat melayani kepentingan penindas karena tidak ada tatanan yang menindas mengizinkan kaum tertindas mengajukan pertanyaan: Mengapa? Sehingga masyarakat bukan lagi sebagai objek yang hanya menerima melainkan menjadi subjek yang dapat mengubah dunia.
Hal ini jelas membahayakan penguasa karena mereka bukan lagi satu-satunya subjek yang membentuk dunia, sehingga kesadaran kritis inilah yang paing ditakuti oleh penguasa. Maka berbagai cara dilakukan untuk meredam potensi tersebut. Alih-alih membangun sistem pendidikan yang mendorong masyarakat berpikir kritis, mereka diarahkan agar tenggelam dalam kepatuhan, distraksi, dan rutinitas tanpa refleksi.
Dalam konteks inilah, “pembodohan” dijadikan instrumen politik kekuasaan. Melalui kontrol terhadap informasi, manipulasi kurikulum pendidikan, dominasi media, hingga pengalihan perhatian lewat budaya populer, rezim berusaha menciptakan masyarakat yang pasif, konsumtif, dan sulit membedakan kepentingan rakyat dengan kepentingan oligarki. Dengan kata lain, menjaga masyarakat tetap tidak kritis adalah syarat utama bagi keberlangsungan kekuasaan yang eksploitatif.
Konsekuensi Jika Rakyat Tidak Kritis
Masyarakat yang tidak kritis akan menerima segala sesuatu sebagai hal yang alamiah karena tidak akan pernah mempertanyakan “Apa dan Mengapa” sehingga tidak bisa membedakan mana yang alamiah dan mana hasil konstruksi sosial. Hal ini terlihat dalam masyarakat yang bekerja pagi hingga malam namun tidak mempertanyakan “Mengapa saya bekerja sepanjang hari? Apa hidup ini hanya dihabiskan dalam sebuah dunia yang bernama kantor?” sehingga apa yang dilakukan menjadi suatu hal yang wajar dan semestinya. Sudah semestinya mereka berada dalam kantor seharian dan jauh dari keluarga.
Namun, karena tidak terbiasa mempertanyakan, semua itu diterima sebagai hal “wajar”. Ketidakadilan yang jelas di depan mata dianggap sekadar nasib. Mereka diam, pasif, dan terus bergerak dalam arus yang diarahkan oleh penguasa. Dalam kondisi semacam itu, rakyat tidak lagi menjadi subjek sejarah, melainkan hanya korban dari sistem yang menindas.
Oleh sebab itu membangun kesadaran kritis bukanlah sesuatu yang elitis atau hanya urusan akademisi. Ia adalah syarat dasar untuk membongkar rantai penindasan yang membelenggu. Kesadaran kritis adalah alat agar kita tidak sekadar menerima, tetapi berani mempertanyakan, mendiskusikan, dan pada akhirnya mengubah keadaan. Pertanyaannya sederhana: apakah kita ingin terus menjadi penonton dalam dunia yang dibentuk oleh segelintir orang, atau mulai mengambil peran sebagai subjek yang menentukan arah masa depan kita sendiri?