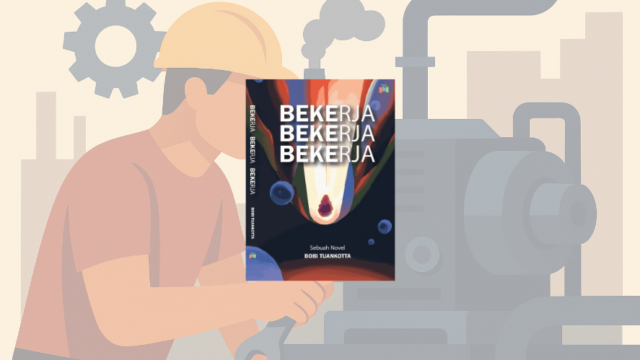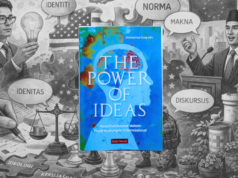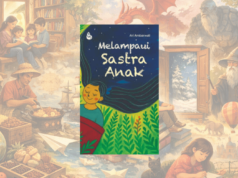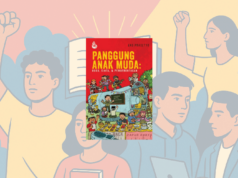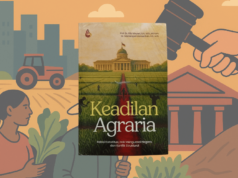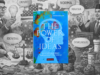Sebuah Catatan atas Novel Bekerja, Bekerja, Bekerja, Bobi Tuankotta
Buku ini perlu dibaca oleh penggemar cerita apa pun untuk bisa tahu bahwa cerita hadir dalam situasi dan peristiwa semonoton apa pun.
– dalam unggahan Instagram Penerbit JBS (@jualbukusastra_jbs)
Mendapati pengakuan dari penerbit di atas, saya jadi teringat satu tulisan Eka Kurniawan. “Apa yang ditawarkan oleh sebuah cerita,” tulis Eka, “selain kabar dari tempat-tempat yang berbeda dan waktu-waktu yang berlainan? Bagi saya sudah sangat pasti: sebuah percakapan.”
Eka lantas menerangkan bahwa dalam masyarakat urban dan modern, manusia tanpa sadar terus membutuhkan dan melakukan percakapan. Ia memberi gambaran bagaimana orang di masa lampau mempunyai peran pendongeng dalam struktur sosial, yang duduk-bercerita di suatu teras; kemudian, oleh zaman, peran tersebut diambil alih oleh buku-buku atau koran-koran; hingga, sekarang ini, didominasi oleh lini-masa media sosial. Eka menulis, “Percakapan tak hanya merujuk kepada orang-orang yang melakukan percakapan, tetapi juga apa dan siapa yang mereka percakapkan.” Dalam itu, Eka lalu mendudukkan Umar Kayam sebagai ‘teman ngobrol’ yang dibutuhkan masyarakat.
Dan dari sana, muncul satu pertanyaan. Kira-kira begini: setelah apa dan siapa, bagaimana sih percakapan itu?
Sebelum ke sana, ada satu info: lima tahun lagi, Indonesia diperkirakan akan mengalami situasi Bonus Demografi. Tenang, kita tidak akan membicarakannya. Hanya saja, perkiraan tersebut membawa satu kemungkinan bahwa, dekat-dekat ini, kita akan hidup di satu negara di mana banyak anak mudanya tidak mengalami secara langsung pengalaman didongengi—jangankan cerita para Nabi atau hikayat leluhur, cerita soal negara saja kebanyakan disensor.
Orang tua mereka, anak-anak muda itu, kebanyakan adalah milenial atau boomer yang, karena kondisi zaman, dipaksa untuk sibuk mencari uang. Sedangkan kakek-nenek mereka, kalau belum meninggal, pastilah telah bermasalah di ingatannya. Maka, mau-tidak mau, mereka akan tumbuh dan memperoleh pengetahuan jauh dari tutur lisan seorang simbah atau teks di suatu buku. Sebab mereka cenderung lebih mengalami-dekat produk-produk audio-visual entah itu melalui media sosial, atau film dan iklan-iklan. Dalam ungkapan lain, percakapan dan teman ngobrol mereka adalah sebuah mesin yang dingin.
Dalam konteks dunia yang seperti itu, manusia butuh bukan sekadar cerita. Percakapan, peristiwa, konflik, narasi, dan lain sebagainya yang mengisi sebuah cerita mesti diikat dengan rapat menggunakan satu tali: intensitas.
Kita sama paham dampak dari pesatnya laju perkembangan. Jika suatu distrik di Eskimo, misalnya, mengalami penurunan suhu, kita dapat mengakses beritanya di internet secara real-time, sambil misalnya berendam di kolam wisata air hangat Pacet. Dengan kecepatan dan kemudahan itu, sulit sekali rasanya memancing rasa ingin-tahu, lebih-lebih kenyamanan dan ketetapan seseorang. Maka intensitas, saya kira, masuk ke dalam bagaimana percakapan, bahkan cerita, disampaikan.
Dan di sanalah karya terbaru Bobi Tuankotta berdiri. Berbeda dengan kecenderungan anti-klimaks Umar Kayam, novel yang berjudul Bekerja, Bekerja, Bekerja ini membawa tawaran soal betapa bising, deru, dan dinginnya mesin-mesin dan manusia. Bobi tidak hanya memberi kabar soal suatu PLTD di Tahanusa yang dibakar oleh massa. Ia mengajak kita mengalami; sekitar dua hari menjelang PLTD dibakar, bagaimana rasanya menjadi karyawan PLN, pegawai outsourcing, Bapa Raja (kepala desa), dan masyarakat di sana? Bagaimana berurusan, mengalami percakapan, dengan mesin-mesin yang bising, emosi yang menderu, juga perintah atasan yang dingin? Hanya dua hari itu saja, tidak kurang, tidak lebih.
Bobi tidak mengajak kita menjadi Bobi si pengarang. Sebab ia sendiri pun tidak berada di sana. Semua suara (tokoh yang menyampaikan narasi dan atau peristiwa) konsisten sebuah fiksi, karangan. Dan di sana, pengarang benar-benar mati. Tidak gentayangan lagi.
Bagai mengetahui kebutuhan hari ini, Bekerja, Bekerja, Bekerja hadir melalui pendekatan seperti sebuah film. Eksplorasi pada objek-objek audio-visual yang menonjol dihadirkan dalam peristiwa langsung (bukan kilas balik) yang intens. Sungguh klinis mengingat konflik cerita berkaitan dengan operasional mesin listrik yang menjadi sumber energi lima desa di sebuah pulau. Perhatikan adegan yang rasanya begitu filmis berikut.
Begitu Faisal mengembalikan matanya ke layar laptop, Amat mengeluarkan paku dan palu dari saku belakang lalu mulai bekerja. Berlatarbelakangkan deru mesin-mesin dari sentral, suara ketikan jemari Faisal di kibor menyusup di antara suara ketukan palu Amat di jendela. Pung, tik, tik, pang, tik, tik, pung, tik, tik, pang. Pasangan senior-junior itu fokus dalam tugasnya masing-masing. Begitu Faisal selesai dengan SFC di laporan, tersisalah suara ketukan palu Amat di atmosfer. Pang, pung, pang …
Juga dalam pergantian adegan. Demi meraih humor situasional ala-ala drama komedi, Bobi menggambar demikian.
“Bagaimanapun, Bos, aku ragu bahwa warga Pacis bakal datang dan berdemo pada jam segini,” lanjut Bento kepada Faisal, “sebab mereka semua pasti sudah tidur. Selain itu, orang gila macam mana yang mau datang ke PLTD pada saat hujan deras begini?”
Dua menit kemudian, hujan berhenti.
Sekilas memang akan mengingatkan kita pada Minor Detail, Adania Shibli. Banyak kritikus menganggap pengarang Palestina tersebut memanfaatkan teknik ungkap-peristiwa layaknya sebuah film, guna mempertebal pengalaman traumatik yang disebabkan oleh serbuan tentara Israel di Nakba. Tapi Bekerja, Bekerja, Bekerja memanglah berbeda.
Jika hanya membaca sinopsis, kita akan berpendapat bahwa cerita soal PLN dan Indonesia Timur adalah cerita soal ketimpangan. Tapi alih-alih demikian, Bekerja, Bekerja, Bekerja rupanya bukanlah suatu kritik sosial yang frontal dan terjebak pada protes-marah atau khotbah-perintah. Bahwa memang ketimpangan itu ada, dengan atau tanpa tendensi membanding-bandingkan dengan wilayah seperti Jawa, misalnya. Apa yang dilakukan Bobi hanyalah menjernihkan masalah tersebut. Ia, seolah sebuah mesin, sebuah komposisi, hanya berkata, “Suatu PLTD dibakar oleh massa di Tahanusa. Inilah ceritanya … ” dan kita, tersebab bagaimana cerita disampaikan, tidak bisa tidak menyimaknya sampai tuntas, kemudian merenungkannya nanti dalam kesendirian. Sambil itu, kita akan mengingat sepetik esai Toni Morrison:
“… Nothing would be more hateful to me than a monolithic prescription for what Black literature is or ought to be. I simply wanted to write literature that was irrevocably, indisputably Black, not because its characters were, or because I was, but because it took asits creative task and sought asits credentials those recognized and verifiable principles of Black art.”
Meski, upaya Bobi untuk tak terlalu tenggelam dalam kelokalan malah membuat cerita terasa dingin di beberapa titik. Misal dalam dialog. Jelas saja, sebagai pembaca, kita berharap ada semacam dialek yang terikat dengan suatu tokoh, mengingat latar berada di Indonesia Timur.
Memang, pada mulanya hal tersebut dapat dibaca sebagai konsistensi pengarang dalam rangka memesinkan cerita. Dalam jarak tertentu, hal tersebut membuat bentuk dan isi menjadi integral, menjadi utuh. Sayangnya hal tersebut sedikit lemah ketika di satu-dua kesempatan, kita malah akan mendapati tokoh outsourcing yang bercakap-cakap menggunakan frasa-frasa bahasa Inggris. Di sanalah muncul satu pertanyaan: mengapa menghindari dialek lokal tetapi mempertahankan frasa Inggris? Apakah, layaknya sebuah mesin, itu adalah satu error system?
Tetapi demikianlah. Terlepas dari apa yang telah saya tulis, tentu saja novel Bekerja, Bekerja, Bekerja berbeda dengan mesin (dalam bayangan hari ini). Sebab buku itu bukannya memerlukan listrik. Ia hanya perlu setoran sedikit uangmu di suatu toko buku. Tidak kurang, tidak lebih. Demikianlah.
Identitas Buku
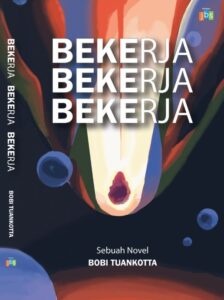
Judul: Bekerja, Bekerja, Bekerja
Penulis: Bobi Tuankotta
Penerbit: Jual Buku Sastra, Yogyakarta
Cetakan: Pertama, 2025
Tebal: 258 Halaman
ISBN: 978-623-8755-16-5