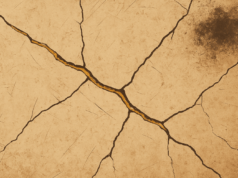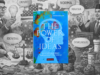Di antara daun kol yang gemetar disiram angin gunung dan bibit tomat yang masih gemetar dalam plastik kecil, seorang pemuda bernama Kamarudin menyiram masa depannya sendiri. Air yang menetes dari selang bukan sekadar cairan penyubur tanaman, tapi adalah pengantar doa, harapan, dan ketekunan yang barangkali tak tercatat dalam indikator keberhasilan program pemerintah.
Saya menemuinya pada akhir April 2025 di Desa Sapit, Kecamatan Suela, Lombok Timur—salah satu dari desa-desa yang menyatakan diri sudah bersiap menyambut gelombang program ketahanan pangan yang dicanangkan oleh negara lewat Permendes dan PDT Nomor 2 Tahun 2024.
Program ini mewajibkan 20 persen Dana Desa dialokasikan untuk swasembada pangan. Namun pertanyaannya: cukupkah angka itu menjawab kompleksitas yang mengakar dalam tubuh pertanian desa?
Di sawah seluas satu hektare yang digarap Kamarudin, hanya satu ton lebih gabah yang bisa dipanen dalam setahun. Jumlah itu pun tak dijual, tapi ditimbun untuk kebutuhan makan keluarga. Di tengah inflasi, krisis iklim, dan anomali cuaca, strategi bertahan hidup ini menjadi pilihan paling rasional. Pangan tak lagi sekadar produk agraria, tetapi soal eksistensi.
Musim tanam di Sapit bersandar pada langit. Sekali padi, sekali hortikultura. Itu pun dengan catatan: hama tak menyerang dan hujan tak mangkir. Tak ada jaminan. Tak ada prediksi. Seperti yang diungkapkan Arini, petani perempuan di desa itu, hasil panen tiap tahun seperti nasib: tak bisa ditebak dan hanya bisa diterima dengan pasrah.
Tapi pasrah bukan berarti menyerah. Warga desa mencoba berdamai dengan keterbatasan. Sayangnya, pupuk organik dari BUMDes yang sebenarnya bisa menjadi jalan keluar justru sepi peminat.
Racikan kimia tetap jadi pilihan utama yang praktis, instan, dan dianggap lebih manjur. Ini adalah cermin dari bagaimana ketergantungan pada pasar dan industri kimia telah mencengkeram desa dengan lembut tapi kuat.
Di Desa Sepit, Kecamatan Keruak—sekitar satu jam perjalanan ke selatan dari Sapit—cerita lain tumbuh dengan akar yang hampir serupa. Desa ini mulai menatap masa depan pertaniannya dengan merancang revitalisasi embung, jalan usaha tani, dan bahkan pengelolaan agrowisata berbasis tanah kas desa. Ada cita-cita yang mengalir, bahwa ketahanan pangan tak melulu tentang padi atau jagung, tapi juga diversifikasi ekonomi pedesaan.
Namun seperti nasib kambing-kambing induk dalam program bagi hasil yang kini sedang dievaluasi—karena dari 44 ekor hanya tersisa 38 dalam dua tahun terakhir—ikhtiar itu juga butuh waktu, evaluasi, dan keberlanjutan. Di desa, pembangunan tidak tumbuh seperti jamur di musim hujan, tapi lebih seperti cengkeh di pekarangan: menunggu musim, menahan sabar, menepis keraguan.
Keluhan para petani Desa Sepit masih klasik: mahalnya buruh, melambungnya harga pupuk, dan kurangnya teknologi. Mesin pencacah tanah dan pengering hasil panen menjadi mimpi yang sederhana tapi belum tentu bisa diwujudkan dari alokasi 20 persen Dana Desa. Di sinilah kita menemukan paradoks: negara ingin desa kuat, tapi jalan menuju kekuatan itu tetap terjal dan berlubang.
Ketahanan yang Inklusif atau Sekadar Administratif?
Ketahanan pangan versi negara, sejauh ini, sering diterjemahkan dalam bentuk program dan proyek: anggaran, pembukaan jalan tani, distribusi bibit, atau pengadaan ternak. Tapi ketahanan yang sejati adalah ketika desa bisa berdikari dalam hal makanannya sendiri. Ini bukan hanya tentang panen yang berlimpah, tapi juga tentang keberlanjutan, kemandirian, dan relasi sosial yang tumbuh dari tanah yang sama.
Program ketahanan pangan mestinya tidak hanya memikirkan sisi teknis, tetapi juga nilai-nilai kultural dan ekologis yang menyatu dalam pola hidup petani. Apakah program ini mampu membalikkan ketergantungan pada pupuk kimia menjadi gerakan agroekologi berbasis lokal? Apakah program ini bisa menjadikan perempuan seperti Arini sebagai subjek aktif, bukan sekadar objek data? Dan yang terpenting, apakah desa bisa memutus ketergantungan dari pasar yang tak kenal ampun?
Kita patut waspada agar program ini tidak menjadi sekadar pelengkap laporan tahunan atau angka-angka evaluasi birokrasi. Musyawarah desa yang digadang sebagai forum tertinggi pengambilan keputusan kerap hanya menjadi ruang formalitas, bukan forum strategis yang benar-benar memberi suara pada petani, perempuan, dan kelompok rentan lainnya.
Melihat Desa dari Dalam
Saya percaya bahwa desa menyimpan kebijaksanaan yang sering luput dari radar kebijakan pusat. Di desa, pangan bukan sekadar komoditas, tapi bagian dari jati diri. Di ladang, di lumbung, di kebun dan dapur, ada cerita tentang bagaimana manusia dan alam saling menopang.
Maka, ketika negara mendorong desa untuk mandiri pangan, maka negara juga harus bersedia mendengarkan logika desa, bukan hanya memaksakan logika anggaran dan indikator keberhasilan.
Ketahanan pangan bukan proyek lima tahun, tapi proses lintas generasi. Ia menuntut ketekunan seperti yang dilakukan Kamarudin saat menyiram bibit, hari demi hari.
Desa tidak menolak bantuan, tapi ia berhak memilih cara bertahan hidupnya sendiri. Kita hanya perlu percaya bahwa petani tahu cara menumbuhkan harapan, sepanjang mereka diberi ruang, dihargai pengetahuannya, dan dibebaskan dari cengkeraman pasar dan proyek sesaat.
Dalam suasana desa yang tenang, di antara bunyi semprot air dan desir angin di kaki Gunung Rinjani, saya menyadari satu hal: bahwa pangan adalah persoalan martabat. Ia bukan sekadar urusan perut, tapi tentang hak untuk hidup dengan bermartabat di tanah sendiri.
Ketika Kamarudin menanam tomat dan menyiram kol, ia sedang menanam martabatnya sebagai petani. Ketika Arini menyimpan gabah di lumbungnya, ia sedang mempertahankan otonomi keluarganya dari gejolak pasar. Ketika desa merancang jalan tani, embung, atau agrowisata, mereka sedang mengukir jalan mereka sendiri menuju masa depan.
Ketahanan pangan sejati hanya bisa lahir ketika kita menempatkan petani bukan sebagai obyek pembangunan, tetapi sebagai aktor utama dalam cerita desa. Sebab dari tangan merekalah, nasi yang kita makan setiap hari berasal. Dan dari tanah yang mereka garap dengan peluh dan harapan itulah, kita bisa memahami makna paling dalam dari kata kedaulatan.***