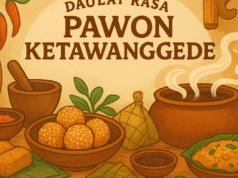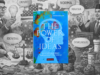Ragam Arti Istilah “Dapur”
Istilah “dapur” merupakan salah sebuah kosa kata di dalam bahasa Indonesia yang secara harfiah memiliki beberapa alternasi arti: (1) ruang tempat memasak; atau (2) tempat membakar batu bata, batu kapur, dsb.; (3) tungku; perapian (KBBI, 2002). Pada alternasi arti yang pertama, dapur berupa: suatu ruang yang integral dalam lingkungan rumah tinggal. Adapun, secara spesifik, fungsi dari dapur adalah sebagai tempat untuk memasak. Pada umumnya, dapur berada di bagian belakang pada tata letak (layout) rumah tinggal, walaupun ada pula yang posisinya di samping-belakang rumah ataupun dapat juga berupa bangunan tersendiri yang terhubung dengan rumah induk.
Dapur sebagai suatu tempat buat memasak, ada yang: (a) bersifat “privat”, yaitu pribadi bagi suatu keluarga, namun ada juga (b) “dapur kolektif” seperti pada sebutan “dapur umum,” yakni tempat menyediakan makanan untuk cuma-cuma orang banyak ketika dalam keadaan darurat, bencana, hajatan besar, dsb. Pada momentum tertentu dapur keluarga yang pada kesehariannya adalah “dapur privat” berubah sesaat menjadi “dapur kolektif”, misal tatkala keluarga sedang mempunyai hajat. Oleh karena itu, konon ukuran dapur dibuat cukup besar untuk dapat menampung cukup banyak orang yang “rewang (buodo)”, yakni membantu tenaga dalam memasak kepada pihak si empunya hajat.
Kata “dapur” tidak hanya ada di dalam bahasa Indonesia. Istilah ini pernah juga kedapatan pada bahasa Jawa Kuna dan Jawa Tengahan dengan beberapa alternasi arti: (1) berjongkok, mendekam, membungkukkan badan, bertekuk lutut; (2) rumpun (pohon, bambu), tumbuhan? Atau bisa juga menunjuk pada kesatuan sosial pedesaan, (3) sejenis bahan kain? (Zoetmulder, 1995: 196). Dalam arti rumpun bambu, terdapat perkataan “pring sedapur” buat rerimbunan bambu. Perkiraan ini bisa juga menunjuk pada sebuah keluarga besar, yang diibaratkan dengan rerimbunan bambu. Ketiga arti di atas berlainan dengan arti kata “dapur” di dalam bahasa Indonesia yang diartikan sebagai ruangan tempat memasak.
Ada pula istilah “dapur” yang digunakan dalam kaitannya dengan keris atau tombak, yaitu bentuk atau tipe bilah keris. Secara garis besar terdapat dua jenis dapur keris, yaitu: (a) keris lurus dan (b) keris berkelok (luk). Masing-masing jenis itu memiliki varian-varian bentuk dengan nama-nama sendiri, seperti tilam upih untuk keris lurus, sengkelat dan brojol untuk keris melengkung, ataupun keris dengan luk 3 hingga 29 Luk. Kata “dapur” dalam artian ini berbeda pula dengan arti kata “dapur” di dalam bahasa Indonesia.
Terdapat juga sebutan “dapur” dalam artian berikut: wajah, rupa atau muka, yang apabila ditambah dengan kata ganti kepunyaan “mu” dan menjadi “dapurmu”, dalam konteks umpatan bisa bermakna negatif, seperti perkataan “raimu”. Misalnya, umpatan “o … dapurmu rusak” atau “raimu amoh“. Oleh karena itu, hati-hati dalam pemakaian. Maunya menyatakan dapur milik Anda (kamu), namun bila diucap dengan nada agak keras “dapurmu!!!!!”, jangan-jangan disangka mengumpat.
Ragam Sebutan Bersinonim.Arti Dengan “Dapur”
Dalam bahasa Jawa Baru, sebutan untuk “dapur” sebagai tempat untuk memasak adalah “pawon”. Sebutan ini adalah suatu kata jadian dengan kata dasar “awu (varian kuno “hawu”), dengan mendapatkan awalan “pa” dan akhiran “an” (pa+awu+an) “. Istilah “awu (hawu)” pada bahasa Jawa Kuna dan Tengahan menunjuk pada: abu, atau bisa juga menunjuk pada bedak, pupur, bubuk (Zoetmulder, 1995: 87, 346). Kata jadian “anghawu” berati menjadi abu, dan kata ulang “pahawwan-hawwan” dan “pawwan- awwan” berarti “kotak”, yang bisa jadi mengarah pada tempat abu, seperti pada kata “paon” dalam bahasa Bali.
Dalam hal demikian, belum tegas arti “pawwan (kini “pawon“)” dalam bahasa Jawa Kuna atau “paon” dalam bahasa Bali sebagai tempat buat memasak. Arti katanya sebagai dapur, yakni tempat untuk memasak, adalah “arti asosiatif, lantaran di tempat pembakaran itu tersisa awu atau abu—terjadilah pertukaran konsonan “w” dengan “b”. Pembakaran dalam konteks ini dilakukan untuk kepentingan memasak. Karena itu, di dalam bahasa Jawa Baru, kata “pawon” memiliki arti sebagai dapur, yang secara lebih spesifik merujuk pada suatu tempat memasak tradisional dengan kayu atau arang sebagai bahan bakarnya.
Sebutan “pawon” lantas diartikan lebih luas lagi untuk menyebut tempat atau ruang memasak, yang sama artinya dengan kata “dapur” di dalam bahasa Indonesia. Sedangkan peralatan pembakarannya disebut “pawonan“, yakni semacam sejuta “tungku” dalam bahasa Indonesia, yang menunjuk kepada alat atau instalasi yang digunakan buat pembakaran guna memanaskan sesuatu, yang bisa berupa alat masak sederhana hingga sistem pemanas besar pada industri atau bangunan. Tungku bisa terbuat dari tanah liat, batu, atau bahan-bahan lainnya, yang bisa menggunakan bahan bakar seperti kayu, arang, gas, atau listrik. Kalaupun ada istilah “tungku” (varian sebutan “katutungku“)” dalam bahasa Jawa Kuna, namun lebih menunjuk pada jenis bunga yang khas (Zoetmulder, 1995 : 474.dan 1299).
Kata tungku juga dipergunakan secara teknis dalam dunia industri, seperti pada perkataan “tungku lokomotif uap”, yang menunjuk pada bagian pada loko yang berfungsi untuk menghasilkan panas yang sangat tinggi yang didapat dari pembakaran bahan bakar (biasanya batu bara, minyak, atau kayu). Panas yang diproduksi itu digunakan untuk memanaskan air dalam ketel hingga menghasilkan uap bertekanan tinggi, yang kemudian digunakan lebih lanjut untuk menghasilkan kinetik, yakni untuk menggerakkan piston dan roda lokomotif. Serupa itu ada sebutan “dapur (tanur)” ditambah dengan kata “tinggi” sehingga menjadi “dapur tinggi”, yang menunjuk pada tanur (tungku) metalurgi silinder besar yang digunakan untuk meleburkan bijih besi menjadi besi kasar (pig iron). Prosesnya melibatkan pemanasan suhu tinggi dengan kokas sebagai bahan bakar dan reduksi bijih besi menggunakan karbon monoksida yang menghasilkan besi kasar dan terak.
Bentuk Tungku dan Perangkat Penggantinya
Tungku (pawonan) bisa ersusun dari batu atau bata yang diatur, sehingga bahan bakar kayu terlindungi, dan panas hasil pembakaran dapat diarahkan guna memanaskan sesuatu. Tungku arkais ada yang bahkan hanya dibuat dari tanah liat (lepung), yang lama kelamaan bisa mengeras lantaran terkena panas tinggi terus-menerus. Kebanyakan tungku dibuat sedemikian rupa sehingga api (panas) yang terbentuk tak terlampau membahayakan si pengguna. Pada umumnya tungku berbentuk persegi, dengan tinggi dindingnya sekitar 40-50 cm, dilengkapi dengan mulut di sisi depan buat memasukkan kayu bakar, serta satu, dua atau bahkan lebih lobang pada permukaan atas sebagai tempat untuk perangkat masak di dalam aktifitas merebus, menggoreng, atau membakar. Lubang atas tunggu ada yang berjajar ke belakang, ada yang menyambung, atau padyan di antaranya.
Tungku (pawonan) adalah perangkat pembakaran yang bersifat *permanen”, yakni berada menetap di satu tempat tanpa dapat dipindah-pindahkan. Pada rumah tunggal tradisional, tungku (pawonan)—sesuai unsur sebutannya “pawon+an”—ditempatkanlah di dapur (pawon), yang menjadi “inti” dari dapur. Lantaran tidak dapat dipindah-pindahkan (unmovable), maka berkembang kemudian tungku “portable“, yang bisa dipindah-pindahkan, tidak terlampau besar ukurannya, dan lebih simpel dalam pengoperasionalnya, yaitu angko. Sebutan “anglo” menunjuk pada alat memasak tradisional yang dipergunakan untuk membakar arang guna memasak atau memanaskan, berupa wadah berkaki yang memungkinkan udara masuk dan menyalakan api.
Terkait dengan kata “anglo”, jangan salah sebut dan salah arti dengan “anglo” dh dalam bahasa Inggris, yang menunjuk pada “prefiks”. Pada sebutan Eropa dan Amerika, terdapat perkataan “Anglo Saxon”, yang menunjuk pada: suatu kelompok suku-suku Jermanik (terutama suku Angles, Saxon, dan Jute) yang bermigrasi dari benua Eropa ke Britania Raya sekitar abad ke-5 M (sekitar tahun 450 hingga 1066 M, dan karenanya dikenal sebagai “Periode Anglo-Saxon”). Warisan budayanya membentuk dasar negara Inggris, bahasa, hukum, akuntansi, dan institusi yang bertahan hingga saat ini. Ada pula sebutan “Anglo Amerika”, yang menunjuk pada kelompok demografi di Amerika yang berbahasa Inggris dan memiliki hubungan budaya dengan Inggris.
Perangkat pembakaran anglo dibuat dari tanah liat, senen-pasir cetak, batu vulkanik ataupun batu padas keras (curing), bahkan ada yang berbahan logam (besi). Bahan bakarnya bisa kayu—untuk anglo besar, atau arang. Dengan adanya penggunaan bahan bakar yang berupa arang kayu memicu produksi arang (bahasa Jawa Baru “areng” atau “hareng” pada bahasa Jawa Kuna dan Tengahan). Ditilik dari ukurannya, ada anglo kecil, biasanya untuk tempat pembakar kemenyan, ada juga anglo sedang dan besar. Bandingkan dengan pawonan, yang bisa mempunyai beberapa buah lubang atas untuk memasak. Kehadiran anglo mampu menggeser penggunaan pawonan. Warung, pedagang keliling, rumah tunggal kecil serta keluarga lebih modern cenderung menggunakan anglo daripada pawonan. Bahkan warga etnik Tengger yang menjadi pendukung kuat “tradisi pawon”, kini banyak yang beralih kepada anglo. Pawonan hanya digunakan di waktu-waktu tertentu, yang pada kesehariannya mulai tergantikan oleh anglo dan kompor gas.
Dalam perkembangannya, penggunaan anglo pun akhirnya tergusur oleh kompor minyak tanah, yang lebih praktis dalam operasionalnya. Namun seiring dengan hadirnya kompor gas, utamanya sejak digelontorkannya gas tabung kecil (neto 3 kg, yang acap disebut “tabung gas melon”—lantaran bercat warna hijau muda) dan bersubsidi hingga ke desa-desa, tak ayal pawonan (tungku,) dan anglo pun turut terkena gusur. Penggunaan kompor gas dinilai sebagai lebih praktis dan tidak berdampak menghitamkan dinding dan langit-langit dapur karena jelaga pembakaran, serta tak berasap seperti asap yang keluar dari pembakaran kayu. Tak sedikit warga, tidak terkecuali warga Tengger, yang kini “ogah (tak mau)” dapurnya menghitam dan dipenuhi asap. Sulitnya mendapat kayu bakar dan arang serta makin langkanya minyak tanah ikut membuat banyak keluarga beralih dari pawonan (tungku), anglon, dan kompor minyak ke kompor gas. Sebenarnya masih ada lagi jenis kompor yang lain, yaitu kompor listrik, namun hingga kini di penjuru daerah di Indonesia tak banyak yang menggunakannya, belum mampu menggantikan kompor gas.
Pawonan, Indikator Kemandirian Keluarga Batih Warga Etnik Tengger
Pawonan adalah “indikator keberlangsungan kehidupan”. Konon ketika tungku (pawonan) biasa digunakan, asap yang keluar akibat pembakaran pada tungku (pawonan), yang dimetaforkan dengan “dapur ngebul”, menjadi pertanda masih adanya aktivitas dapur, dan bila masih ada aktifitas di dapur, kehidupan masih akan terus berlanjut. Sebutan yang serupa arti dengan “gethonge mlopong“, yakni pedaringan tempat wadah beras, yang berarti tidak cukup punya bahan untuk dimakannya. Sampai-sampai “kendhine nggoling“, artinya wadah baru minum dari terakota (kendinya) pun lantaran tak terisi.air. Namun kini, pawonan berbahan bakar kayu, pedaringan sebagai tempat beras, dan kendi wadah air minum tak lagi digunakan, dan indikator itu pun mulai tak berlaku.
Selain aktivitas dapur dan ketersediaan bahan makan dan minum menjadi indikator eksistensi kehidupan, ada juga indikator yang berlaku dilingkungan etnik Tengger bahwa kepemilikan tungku (pawonan) menjadi indikator akan “kemandirian” suatu keluarga Batih, utamanya pada keluarga muda. Ada kebiasaan di warga Tengger bahwa anak yang baru menikah tinggal bersama orangtua atau mertuanya. Untuk berapa waktu, pengantin baru—bahkan bisa hingga telah punya anak—itu kebutuhannya dicukupi oleh orang tua, termasuk kebutuhan makannya, yang diistilahkan dengan “isih dicadhing wong tuwo“. Namun seiring dengan tumbuhnya kemampuan untuk dapat memetik kebutuhan hidupnya sendiri, berangsur-angsur orang tuanya mulai melepaskan “cadhingan“nya, untuk ke depan dapat “hidup mandiri (mentas)”. Meski masih tinggal serumah dengan orang tuanya, pada tahap ini orangtua mulai membuatkan pawonan (tungku) untuk anaknya, yang berati mereka telah mulai memenuhi kebutuhan hidup keluarga batihnya secara mandiri.
Demikian pentingnya pawonan bagi sebuah keluarga, maka ketika berlangsung prosesi nikah (walagara), kedua mempelai warga etnik Tengger dikirab mengekuling pawonan hingga 3X. Selain itu, sesani kecil (tampung) diberikan kepada “sing aming-among gemi“, yakni tungku perapian. Bahan bakar utama bagi perkawinannya, yakni kayu bakar, mustilah cukup tersedia. Oleh karena itu, sepulang dari aktivitas di ladang, sedapat mungkin membawa serta (nyaking) kayu bakar ke rumah. Kayu bakarnya diperlakukan istimewa, musti dibuat jadi keung, tak boros dalam pemakaian, serta bila kayu bakar tengah dimasukkan ke dalam tungku, tak boleh (pamali) kaki melangkahi pangkal kayu yang masih terbujur di luar mulut tungku. Walau kini, ketika “gas melon” menjadi bahan bakar utama agi kompor gasnya, penghargaan mereka terhadap kayu bakar tak pernah sirna. Kayu dan arang tetaplah penting untuk “diang“, yakni penghangat tubuh dalam menghadapi hawa dingin lereng Tenget. Dapur baginya adalah “pemberi kehangatan”.
Suasana hangat di dapur menjadi “kehangatan interaksi sosial internal” lingkungan keluarga. Selain itu, tempat kumpul keluarga adalah di dapur. Perencanaan kegiatan dalam berladang (berkebun) dan perbincangan urusan rumah tangga di lakukan di dapur. Itulah sebab muncul ungkapan “rembuk pawon“. Demikian pula, “penerimaan tamu pun dilakukan di dapur, bukan karena tak punya ruang tamu yang layak, namun ada rasa bahwa lingkungan dapat lebih memberi kehangatan dan persaudaraan, yang tak tergantikan oleh ruang lain di dalam rumah tinggalnya, kendati pun nuansa di dapur kehitaman dan beraroma “sangit” asap. Dapur bagi warga Tengger adalah “axis mundi mikro“, yakni “poros dunia kecil ” di lingkungan rumah keluarga.
Sebutan “dapur” kini lebih akrab pada warga etnik Jawa ketimbang sebutan “pawon“. Begitu pula, sebutannya”,kompor” lebih banyak terdengar dari pada “pawonan“. Meski serupa arti, yang menunjuk pada dapur dan perangkat pembakaran (baca “memasak”), namun makna yang terkandung dari masing-masing sebutan itu lain. Pawon dan painan sebagaimana telah dipaparkan di atas tak sekadar memilik makna arsitektur, peralatan (equipment), namun ada makna sosio-kultural dan ekologis yang tidak tergantikan oleh kata”dapur” dan “kompor”.
Demikianlah uraian ringkas mengenai “budaya pawin” menurut “konsepsi eko-sosio-kultural” warga etnik Jawa. Semoga dapat menambah wawasan bagi para bijak. Matur sembah kawin atas perhatiannya.
Griyajar Citralekha, 5 November 2025