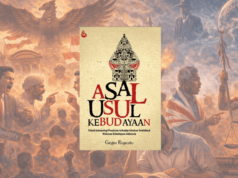Buku #Reset Indonesia: Gagasan tentang Indonesia Baru ditulis oleh empat jurnalis lintas generasi yang menempuh Ekspedisi Indonesia Baru (2022–2023). Masing-masing mewakili zamannya: Farid Gaban (Boomer) sudah empat dekade pengalaman sebagai jurnalistik. Dandhy Laksono (Gen X) 26 tahun berkarya jadi jurnalis, dikenal lewat film dokumenter Sexy Killer dan Dirty Vote. Yusuf Priambodo (Milenial) jurnalis dan fotografer asal Tuban. Benaya Harobu (Gen Z) jurnalis paling muda berasal dari Indonesia timur tepatnya di pulau Sumba.
Buku ini adalah puncak refleksi dari tiga perjalanan panjang: Ekspedisi Zamrud Khatulistiwa (2009–2010), Indonesia Biru (2015–2016), dan Indonesia Baru (2022–2023). Yang membuat buku ini penting adalah keberanian para penulisnya untuk turun langsung ke pelosok negeri dan menyaksikan dari dekat persoalan-persoalan yang kerap luput dari sorotan media arus utama, diperkuat oleh riset mendalam yang tercermin dari kelengkapan referensi di bagian akhir buku.
Melalui perjalanan lintas wilayah, pembaca diajak menelusuri beragam problem Indonesia, mulai dari krisis lingkungan di Sungai Brantas, Bengawan, dan Citarum, hingga konflik agraria dan tambang di Wadas, Dayak, Papua, serta pesisir timur Indonesia, sekaligus melihat Indonesia dari dua sisi: realitas lapangan melalui perjumpaan dengan figur-figur seperti Zamrisyaf di Agam, Sumatra Barat, yang membangun pembangkit listrik tenaga ombak, dan ruang gagasan melalui refleksi para pendiri bangsa, dari koperasi ala Bung Hatta, Mustika Rasa Bung Karno, hingga kritik terhadap mitos ekonomi trickle-down.
Sebagai pembaca, saya merangkum momen dan fakta paling kuat dalam buku ini, bagian-bagian yang bukan hanya menarik, tetapi juga memberi pelajaran penting tentang wajah Indonesia hari ini.
Air Bersih dan Mitos Kemajuan
Prolog Reset Indonesia berjudul “Mencari Ukuran Kemajuan” menjadi momen yang langsung menampar kesadaran saya. Dandhy Laksono menggambarkan betapa sulitnya warga Indonesia menikmati air bersih, bahkan untuk kebutuhan paling dasar. Di Jakarta hampir 80% rumah tangga kini bergantung pada air kemasan. Gambaran ini sangat dekat dengan pengalaman pribadi saya. Pada 2000–2012, keluarga saya masih meminum air keran yang dimasak. Airnya jernih, tidak berbau, dan tidak berkapur. Namun sejak 2013, semuanya berubah. Air keran mulai berbau dan meninggalkan kerak kapur setelah direbus. Sejak saat itu, keluarga saya beralih ke air galon.
Ironisnya, ketika saya kecil, nenek sering memarahi saya jika membeli air kemasan. Itu dianggap pemborosan, karena air sumur sudah cukup untuk diminum. Kini, air sumur justru tidak lagi disarankan. Perubahan ini menunjukkan betapa air bersih yang seharusnya menjadi hak dasar, telah berubah menjadi barang mewah yang harus dibeli. Di titik inilah kita sering dicekoki narasi bahwa “setiap pembangunan pasti membutuhkan pengorbanan.” Kalimat ini terdengar masuk akal, tetapi kerap menjadi pembenaran atas pencemaran sungai, limbah industri, dan ketergantungan masyarakat pada air minum kemasan dari perusahaan seperti Danone dan Nestlé, karena air keran tak lagi layak konsumsi.
Namun contoh dari luar negeri membuktikan bahwa narasi itu keliru. Jerman, dengan industri raksasa seperti Airbus, Mercedes, Audi, BMW, dan VW, tetap memiliki sungai-sungai yang bersih. Regulasi lingkungan yang ketat memaksa investor berinovasi dan mengembangkan teknologi ramah lingkungan. Hasilnya, Sungai Elbe, yang berdampingan langsung dengan pabrik Airbus, dapat digunakan untuk berenang. Hal serupa terjadi di Jepang dan Korea Selatan, industrinya maju, teknologinya melesat, tetapi air keran tetap aman diminum. Contoh-contoh ini menunjukkan bahwa pembangunan tidak harus merusak alam, yang dibutuhkan adalah keberanian negara untuk menegakkan aturan dan menempatkan keselamatan lingkungan di atas kepentingan jangka pendek.
Luka Sosial Akibat Tambang: “Anjing-anjing Perang”
Pertikaian warga pro dan kontra terhadap tambang yang berujung adu parang hingga menewaskan beberapa orang menjadi bagian paling horor mengerikan dalam subbab “Anjing-anjing Perang” pada Bab 1. Tragedi di Desa Pancer, Banyuwangi, ini menunjukkan luka sosial mendalam akibat ekonomi ekstraktif. Gunung Salakan, tak jauh dari Bukit Tumpang Pitu, bekas hutan lindung yang kini terkikis tambang menjadi saksi kerusakan tersebut. Limpasan lumpur merusak ekosistem Teluk Pancer dan mematikan mata pencaharian nelayan, memicu ketegangan baru saat eksplorasi kembali dilakukan.
Dari sini konflik tumbuh. Perbedaan sikap berubah menjadi pertengkaran, lalu pertumpahan darah. Keluarga terbelah, tetangga saling curiga, dan warga biasa menjadi korban, bukan pemilik modal atau pengambil keputusan. Sementara itu, perusahaan tambang berdiri aman di balik penjagaan aparat. Penolakan dipatahkan, protes dianggap ancaman, dan warga yang mempertahankan tanahnya justru dicap penghambat pembangunan.
Kisah Pancer hanyalah satu dari banyak tempat lain, Teluk Buli, Weda, Obi, Morowali, Wawonii, hingga Tumpang Pitu. Bahkan berulang di Kongo, Sierra Leone, dan Liberia. Polanya sama, alam rusak, masyarakat tersingkir, dan generasi muda kehilangan masa depan. Yang paling pahit, rakyat kecil selalu menjadi korban. Mereka tak pernah meminta tambang itu hadir, namun harus menanggung seluruh dampaknya. Tambang bukan hanya merusak alam, tetapi juga manusia, keluarga, dan rasa kebersamaan, demi keuntungan segelintir orang atas sesuatu yang tak pernah benar-benar menjadi milik mereka.
Masyarakat Adat: Pengetahuan yang Diabaikan
Istilah “masyarakat adat” sering dilekatkan dengan citra primitif, bodoh, dan tertinggal. Pandangan inilah yang membuat mereka kerap diabaikan, bahkan disingkirkan atas nama pembangunan. Salah satu contohnya adalah rencana pemindahan Suku Ata Modo, penduduk asli Pulau Komodo, demi melindungi satwa purba tersebut. Padahal, jauh sebelum negara Indonesia berdiri, mereka telah hidup berdampingan dengan komodo selama ratusan, bahkan ribuan tahun. Mereka tidak pernah memburunya, meski ancaman selalu ada, karena bagi masyarakat Ata Modo, komodo adalah sabae saudara kembar yang harus dihormati.
Peran masyarakat adat dalam menjaga alam juga terlihat dalam berbagai tradisi lain. Suku Dayak di Kalimantan memuliakan burung enggang sebagai simbol kesehatan hutan, hilangnya burung ini dipercaya sebagai tanda rusaknya alam. Di Kepulauan Talaud, adat e’ha mengatur waktu dan lokasi penangkapan ikan serta panen tanaman agar ekosistem pulih, sementara praktik serupa dikenal sebagai sasi di Maluku, Nusa Tenggara, dan Papua. Semua pranata adat ini memastikan keberlanjutan alam dan pangan jauh sebelum konsep “pembangunan berkelanjutan” populer. Meski tidak semua praktik adat selalu selaras dengan dunia modern, dari merekalah kita belajar bahwa pembangunan tidak harus menghancurkan alam. Jika diberi ruang, masyarakat adat mampu mengelola wilayahnya secara mandiri, bukan sebagai kelompok terbelakang, melainkan sebagai contoh cara hidup yang justru semakin relevan hari ini.
Dari Buku ke Layar: Catatan dari Ekspedisi Indonesia Baru.
Ketika membaca buku Reset Indonesia, saya terdorong untuk menonton dua film dokumenter dari Ekspedisi Indonesia Baru: Silat Tani dan Dragon For Sale. Keduanya seperti perpanjangan tangan dari buku, membawa saya melihat langsung wajah Indonesia yang selama ini kerap luput dari layar-layar promosi pembangunan.
Dalam Silat Tani, yang paling membekas bagi saya adalah kisah tentang kesejahteraan petani. Sungguh memilukan melihat bagaimana kerja keras petani selama tiga hingga empat bulan nyaris tak menghasilkan apa-apa. Kalaupun ada keuntungan, jumlahnya sangat tipis. Seorang petani bercerita bahwa bertani sering kali hanya berakhir pada angka impas. Gabah dijual seharga Rp4.500–5.500 per kilogram, sementara modal produksi sudah menyentuh Rp4.000. Ketika kualitas padi dianggap kurang baik, harga jualnya bahkan jatuh ke Rp4.000, artinya berbulan-bulan bekerja hanya untuk kembali ke titik nol, tanpa keuntungan sepeser pun.
Sementara itu, Dragon For Sale membuka kenyataan lain yang tak kalah mengejutkan. Labuan Bajo, wilayah yang dipromosikan sebagai “Bali Baru” dengan panorama alam memukau, ternyata mengalami krisis air serius. Krisis ini muncul seiring pembangunan besar-besaran: hotel-hotel mewah berdiri, proyek Parapuar digulirkan, dan pariwisata didorong tanpa jeda. Kontrasnya terasa menyakitkan. Turis-turis kaya berenang di kolam hotel, menikmati air dengan mudah, sementara warga setempat kesulitan memenuhi kebutuhan paling dasar, mandi, mencuci, bahkan minum. Warga terpaksa membeli air tanki berkapasitas 1.200 liter seharga Rp400.000, yang hanya cukup untuk dua pekan, sehingga sekitar Rp800.000 harus dikeluarkan setiap bulan hanya untuk air bersih.
Kekurangan Buku
Satu catatan kritis yang patut disampaikan adalah penggunaan angka statistik yang cukup banyak dan padat, terutama pada pembahasan ekonomi. Bagi pembaca awam seperti saya, deretan angka tersebut membutuhkan waktu dan energi lebih untuk dipahami. Memang, data-data itu sebenarnya penting dan memperkuat argumen buku. Namun ketika disajikan terlalu banyak dalam bentuk teks, ia justru berpotensi menimbulkan kejenuhan.
Apalagi buku Reset Indonesia dikampanyekan sebagai buku yang ingin dibaca oleh semua kalangan, dari masyarakat bawah hingga atas. Akan sangat membantu jika sebagian data statistik tersebut divisualisasikan dalam bentuk diagram atau tabel, sehingga lebih mudah dipahami dan dicerna oleh pembaca lintas latar belakang.
Penutup
Reset bukan berarti menghapus semuanya. Ia bukan tombol delete, melainkan ajakan untuk menata ulang pondasi bangsa, nilai-nilai, cara berpikir, prioritas, pendidikan, lingkungan, ketimpangan ekonomi, kesenjangan sosial, hingga akses kesehatan yang belum merata. Itulah sepotong gambaran yang saya tangkap dari buku Reset Indonesia. Buku ini menghadirkan Indonesia apa adanya indah, rapuh, sekaligus penuh persoalan. Di tengah berbagai masalah yang telah terjadi, reset menjadi upaya untuk kembali menempatkan manusia dan alam sebagai pusat pembangunan, agar keduanya tidak terus-menerus menjadi korban.
Bukankah kita ingin anak-cucu kita kelak tetap dapat menyaksikan keindahan negeri ini? Kita tentu ingin dikenang sebagai generasi penjaga, bukan generasi perusak. Apa yang saya tuliskan di sini hanyalah sebagian kecil dari isi buku ini. Masih banyak cerita lapangan, data, dan refleksi penting yang hanya bisa dipahami sepenuhnya dengan membacanya langsung. Karena itu, membaca buku Reset Indonesia bukan sekadar menambah pengetahuan, melainkan membuka perspektif baru tentang Indonesia hari ini, serta mengajak kita berpikir ulang tentang arah masa depan yang sedang kita pilih bersama.