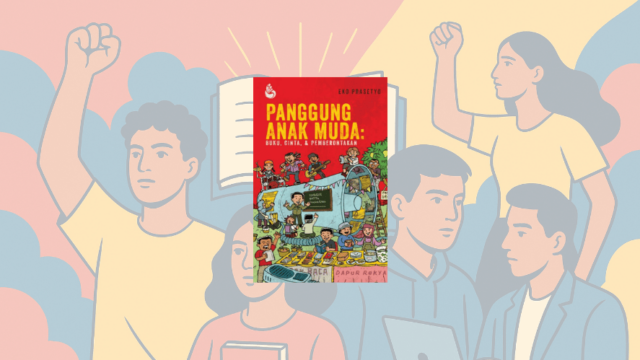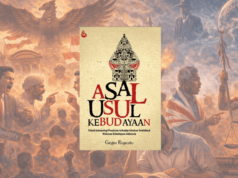Buku Panggung Anak Muda: Buku, Cinta, dan Pemberontakan karya Eko Prasetyo hadir sebagai semacam seruan moral sekaligus refleksi panjang tentang peran anak muda dalam lintasan sejarah sosial-politik Indonesia. Buku ini tidak ditulis sebagai risalah akademik yang kaku, melainkan sebagai buku yang mengajak untuk berpikir, merenung, dan—pada titik tertentu—gelisah. Eko Prasetyo menempatkan anak muda bukan sebagai objek statistik demografi atau sekadar simbol regenerasi, melainkan sebagai subjek sejarah yang terus-menerus dipanggil untuk memilih apakah mesti tunduk pada arus zaman atau melawannya dengan kesadaran.
Dalam buku ini, anak muda digambarkan sebagai entitas yang selalu berada di persimpangan. Di satu sisi, anak muda dibanjiri tawaran gaya hidup yang menjanjikan kesempurnaan semu: popularitas, konsumsi, jabatan, dan status sosial. Di sisi lain, ada panggilan yang lebih sunyi namun mendalam, yakni panggilan untuk terlibat, berpikir, dan mengambil posisi dalam pergulatan sosial. Eko melihat bahwa banyak anak muda akhirnya terseret pada logika materialisme dan karierisme, termasuk hasrat menjadi pejabat, tanpa sempat bertanya lebih jauh: untuk apa kekuasaan itu, dan siapa yang dilayani olehnya.
Namun buku ini tidak menghakimi. Alih-alih mencela, Eko berusaha memahami mengapa anak muda kerap memilih jalan aman. Ada sejarah panjang represi, ketakutan, dan pemutusan ingatan kolektif yang membuat keberanian kini terasa mahal. Masa lalu, dengan segala romantisme dan kegagalannya, tetap menjadi medan penting untuk dipelajari. Bukan untuk disalin mentah-mentah, tetapi untuk menjaga kesinambungan gerakan dan nilai. Di sini, Eko menekankan pentingnya mempertahankan jalan perjuangan, meskipun zaman terus berubah dan godaan kompromi semakin halus.
Buku ini juga memberi perhatian besar pada peran buku dan gagasan. Eko menulis dengan keprihatinan terhadap zaman yang bergerak cepat namun miskin permenungan. Aktivisme yang tercerabut dari bacaan dan pemikiran, baginya, akan mudah tergelincir menjadi slogan kosong. Ia mengingatkan bahwa sejarah pergerakan di Indonesia lahir dari perjumpaan intens dengan teks, gagasan, dan perdebatan. Tokoh-tokoh besar tidak hanya turun ke jalan, tetapi juga bergulat dengan ide-ide besar tentang keadilan, demokrasi, dan kemanusiaan.
Dalam konteks ini, buku jadi tenaga pembebasan. Membaca menjadi tindakan politik, karena melalui bacaan seseorang belajar melihat dunia secara lebih luas dan kritis. Bahkan karya sastra—termasuk novel—dipahami sebagai medium yang mampu membuka imajinasi, empati, dan keberanian moral. Sebaliknya, politik yang dijalankan tanpa basis bacaan hanya akan melahirkan kekuasaan yang dangkal dan mudah dimanipulasi. Eko dengan tegas mengkritik praktik politik yang meminggirkan pengetahuan dan menggantinya dengan pragmatisme jangka pendek.
Salah satu kekuatan paling menonjol dari buku ini adalah pembahasannya tentang cinta. Cinta, dalam pengertian Eko, jauh dari makna romantis yang sempit. Ia adalah energi etis yang menggerakkan keberpihakan. Anak muda, menurut Eko, tengah mengalami krisis cinta: cinta pada sesama, pada keadilan, dan pada masa depan bersama. Sejarah rezim otoriter digambarkan sebagai sejarah pemusnahan cinta—bagaimana keberanian diubah menjadi kepatuhan, dan solidaritas diganti dengan kecurigaan.
Bagi Eko, seorang aktivis sejati digerakkan oleh cinta. Cinta menjadi dasar solidaritas, kepekaan sosial, dan kemampuan merasakan penderitaan orang lain. Dari cinta pula lahir harapan—sesuatu yang sering kali tampak rapuh namun justru paling menentukan. Tanpa cinta, perjuangan mudah berubah menjadi ambisi personal atau sekadar pencarian pengakuan. Buku ini mengajak anak muda untuk berpaling dari kepentingan diri sendiri dan kembali pada dimensi etis dari perjuangan sosial.
Puncak refleksi Eko bermuara pada tema pemberontakan. Pemberontakan di sini tidak selalu berarti kekerasan atau penolakan total, melainkan sikap batin dan intelektual yang menolak ketidakadilan sebagai sesuatu yang wajar. Eko menempatkan pemberontakan sebagai bagian tak terpisahkan dari sejarah manusia. Setiap kemajuan sosial lahir dari keberanian sekelompok orang untuk mengatakan “tidak” pada tatanan yang menindas.
Namun, buku ini juga jujur mengakui bahwa banyak pemberontakan berakhir dengan kekalahan. Kekuasaan memiliki berbagai cara untuk mematahkan perlawanan: kooptasi, kriminalisasi, hingga pembusukan nilai dari dalam. Meski demikian, kekalahan tidak selalu berarti sia-sia. Ada jejak moral dan ingatan kolektif yang tetap hidup, menjadi benih bagi perlawanan berikutnya. Eko menekankan pentingnya membentuk jiwa pemberontak—jiwa yang tidak mudah menyerah, tetapi juga tidak kehilangan kemanusiaannya.
Pada akhirnya, Panggung Anak Muda adalah buku yang mengajak pembacanya bercermin. Ia tidak menawarkan resep instan atau jalan pintas menuju perubahan. Yang ditawarkan adalah kesadaran: bahwa menjadi anak muda adalah tanggung jawab historis. Buku, cinta, dan pemberontakan dipertautkan sebagai tiga pilar yang saling menopang. Tanpa buku, pemberontakan kehilangan arah. Tanpa cinta, perjuangan kehilangan jiwa. Dan tanpa keberanian memberontak, semua gagasan akan berhenti sebagai wacana.
Buku ini layak dibaca oleh siapa pun yang masih percaya bahwa anak muda bukan sekadar penonton sejarah. Dengan bahasa yang lugas namun reflektif, Eko Prasetyo menegaskan bahwa panggung itu masih ada—dan pilihan untuk naik ke atasnya, atau turun dari sana, selalu berada di tangan anak muda sendiri.
Identitas Buku

Judul : Panggung Anak Muda: Buku, Cinta, dan Pemberontakan
Penulis : Eko Prasetyo
Jumlah halaman: x230 hlm
Ukuran : 16,8 x 24,5 cm
Penerbit : Intrans Publishing
ISBN : 9786236529263