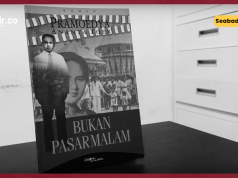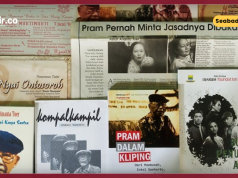“Sudah terumuskan atau belum pengalaman itu, proses kreatif tetap pengalaman pribadi yang sangat pribadi sifatnya,” begitu tulis Pram mengenai proses kreatifnya dalam menulis Perburuan (1950), sebagaimana dikutip dari buku Proses Kreatif Jilid I: Mengapa dan Bagaimana Saya Mengarang (Jakarta: KPG, 2009). Bagi Pram, proses kreatif adalah perjalanan yang betul-betul pribadi dan “tidak butuh pembenaran orang lain”. Namun, tidak seperti Chairil Anwar, misalnya, yang membentuk id dalam reiterasi ke-“aku”-an dalam setiap karyanya sedemikian hingga dicap terlalu menyombongkan diri sendiri (walau belum tentu Chairil begitu), Pram justru menghasilkan suatu otentisitas yang agaknya tidak dijumpai di karya sastrawan lain. Ada sentimentalitas dan rasionalitas yang bergumul jadi satu prosa sederhana: berakar dari pengalaman riil, tetapi tetap mengandung estetika yang nisbi. Pengalaman bersifat objektif, tetapi penafsirannya subjektif. Memang, nama Pram sudah terlampau sering dilontarkan, tetapi untuk betul-betul menghayati alam pikirannya, diperlukan suatu interpretivisme holistik mengenai konteks sosio historis serta psikologisnya.
Ada anekdot bahwa rata-rata penulis, penyair khususnya, bergantung pada kesedihan untuk menghasilkan karya. Alhasil, bagi para sastrawan, kebahagiaan menjadi musuh terbesar. Namun, Pram meramu kebahagiaan itu sendiri dari kepiluannya: tanpa muse, dan justru berbekal rasa benci terhadap sepak terjang militerisme Jepang yang diserapnya ke dalam pori-pori jiwa. Kalaupun Pram mengarang Perburuan demi kepentingannya sendiri – memuaskan hasrat ingin melampiaskan amarah guna menenangkan kemelut yang diakibatkan trauma akibat pendudukan Jepang di Jawa (1942—1945) – pada akhirnya ego itu membawa “syafaat”: Perburuan diakui sebagai salah satu karya sastra monumental dalam sejarah seni Indonesia. Terlebih lagi, novel ini juga digadang sebagai teladan spirit perlawanan terhadap imperialisme dan fasisme Jepang di Asia Tenggara, merangkap objek tinjauan pascakolonialisme dalam kesusastraan.
Pram bercerita, alkisah, kampungnya, Blora langsung terdampak penjajahan Jepang tak lama setelah Tentara Kekaisaran Dai Nippon mendarat di Banten, Kragen, dan Eretan Wetan pada awal 1942. “Tak lebih dari tiga hari di bawah kekuasaan Jepang,” begitu ia mulai berkisah pada buku suntingan Pamusuk Eneste tersebut, “aku berpapasan dengan dua serdadu Jepang yang sedang berpatroli mengendarai sepeda kayu. Mereka hentikan aku, dan aku turun dari sepeda baruku. Langsung milik kebanggaan itu dirampas,”