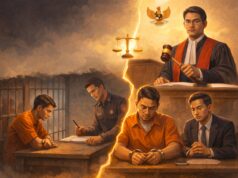Indonesia, sebagai negara dengan jumlah penduduk terbanyak keempat di dunia, realitasnya masih gagal merawat sebuah prinsip demokrasi yang paling mendasar: kesetaraan. Salah satu kelompok yang secara repetitif termarjinalkan adalah penyandang disabilitas. Merujuk data dari Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2020, terdapat setidaknya 22 juta penyandang disabilitas di Indonesia. Data tersebut terus mengalami peningkatan secara signifikan dari 16,5 juta pada tahun 2021.
Dari sekitar 17 juta penyandang disabilitas yang berusia produktif, hanya sekitar 7,6 juta yang bekerja. Sebuah fakta yang memantik kita untuk bertanya: benarkah ruang-ruang sosial kita telah inklusif? Atau sebenarnya ruang itu hanya dihiasi oleh euforia slogan, sementara praktiknya tetap dengan corak yang sama dan diskriminatif?
Dalam narasi resmi, atensi terhadap penyandang disabilitas sering disebutkan sudah “diperhatikan”. Namun dalam realitas sosial, mereka masih tetap dihadapkan pada tembok-tembok tak nampak: stigma, prasangka, dan paradigma usang bahwa disabilitas berarti ketidakmampuan. Lebih tragis, cara pandang ini justru semakin menyusup dalam transformasi digital—sebuah ekosistem yang semestinya membuka akses yang luas, justru tak dapat dijangkau oleh sebagian pihak.
Menyikapi kondisi demikian, timbul pertanyaan, apakah ruang digital sudah menjadi milik bersama, atau sebatas replikasi dari kesenjangan akses sosial dalam medium yang lebih canggih? Oleh karena itu, pemberdayaan menjadi kata kunci. Tapi mari kita bersikap skeptis: pemberdayaan sejenis apa? Jika merujuk pada definisi umum, pemberdayaan merupakan proses memampukan sejumlah kelompok lemah untuk memperoleh akses sumberdaya produktif. Hematnya, bukan sebatas memberi bantuan, melainkan membangun otonomi: kemampuan, keterampilan, dan kemandirian.
Di tengah gelombang globalisasi, pemberdayaan digital menjadi jalan masuk yang logis. Media sosial, serupa Instagram, dapat menjadi medium alternatif. Merujuk hasil riset Voykinska dan kawan-kawan (2016), media sosial bagi penyandang disabilitas netra bukan sebatas instrumen komunikasi, tapi juga alat perjuangan. Untuk menjaga relasi, untuk mendukung karier dan membangun identitas di tengah dunia yang terlalu sibuk merayakan normalitas.
Merebut Ekosistem Digital yang Inklusif
Sebuah riset hasil kerja sama antara Australia dan Indonesia mengungkapkan bahwa penyandang disabilitas di Indonesia masih menghadapi kondisi yang tidak layak dalam pendidikan serta keterbatasan akses terhadap fasilitas publik, khususnya di tengah transformasi digital saat ini.
Mengimplementasikan ruang digital yang inklusif menjadi salah satu agenda krusial dalam upaya transformasi digital di Indonesia, terutama untuk memastikan bahwa penyandang disabilitas memperoleh akses dan hak yang setara. Namun, sampai saat ini, partisipasi penuh disabilitas dalam proses penciptaan ekosistem digital yang inklusif masih sangat terbatas. Padahal, mandat undang-undang maupun konvensi internasional dengan tegas menekankan bahwa inklusivitas hanya dapat terlaksana apabila penyandang disabilitas diberi kesempatan dan ruang untuk terlibat secara aktif dan seimbang.
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas sebenarnya telah mengakomodasi hak-hak akses informasi bagi kelompok disabilitas. Namun, pemenuhan seperangkat hak tersebut masih jauh dari kata optimal akibat disparitas akses digital yang masih dihadapi.
Merujuk data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 2018 yang dipublikasi oleh kementerian Sosial memperlihatkan bahwa tingkat akses kelompok disabilitas terhadap penggunaan telepon seluler maupun laptop baru mencapai 34,89% bahkan jauh tertinggal jika dikomparasikan dengan kelompok non-disabilitas yang mencapai 81,61%.
Sementara itu, sejumlah riset mengungkapkan bahwa faktor utama yang menyebabkan disparitas digital ini adalah lemahnya daya motivasi serta ketertarikan penyandang disabilitas untuk mengakses teknologi digital. Sejumlah faktor lain juga berkontribusi memperkeruh kondisi ini, antara lain keterbatasan fisik, kendala ekonomi dan tingginya biaya, keterbatasan kapasitas penguasaan teknologi, kurangnya ketersediaan sarana komunikasi dan informasi yang sesuai dengan kebutuhan penyandang disabilitas, serta minimnya dukungan sosial.
Namun, sebelum membahas faktor teknis mengenai aksesibilitas digital, penting juga untuk terlebih dahulu mewujudkan inklusi sosial. Tingginya tingkat disability awareness atau kesadaran masyarakat isu disabilitas menjadi pondasi penting agar pedoman aksesibilitas digital dapat diperkenalkan dan diterima secara luas.
Realitas di Indonesia memperlihatkan bahwa inklusivitas sosial bagi kelompok disabilitas masih jauh dari kata ideal. Keterlibatan penyandang disabilitas dari berbagai lini kehidupan masih sangat terbatas. Masyarakat Indonesia umumnya belum secara total terbuka terhadap kebutuhan khusus penyandang disabilitas, dan banyak yang masih belum memahami kompleksitas kebutuhan mereka.
Dari sisi kelompok disabilitas sendiri, penting juga untuk meningkatkan literasi terkait penggunaan teknologi bantu serta pemahaman tentang aksesibilitas digital, supaya mereka dapat memperoleh saluran berbagai aplikasi dan situs web secara mandiri.
Akibat keterbatasan inklusi sosial ini, tak sedikit layanan publik yang dikembangkan tanpa mempertimbangkan kebutuhan nyata para penyandang disabilitas. Tak jarang, layanan tersebut dibangun berdasarkan asumsi semata, tanpa dibarengi dengan melibatkan mereka dalam proses pengambilan kebijakan.
Pada akhirnya, inklusi sosial harus terlebih dahulu diwujudkan agar kebijakan dan layanan yang ditujukan bagi penyandang disabilitas benar-benar tepat sasaran dan efektif. Para pengambil kebijakan perlu menyikapi aksesibilitas digital sebagai hak dasar penyandang disabilitas, bukan sebatas opsi tambahan.
Strategi Kebijakan Kolaborasi yang Partisipatif
Penting bagi kelompok disabilitas untuk mempunyai ruang untuk menyampaikan gagasan, aspirasi, serta memperjuangkan hak-hak mereka. Selain itu, akses yang lebih demokratis terhadap teknologi juga dapat menjadi motor penggerak peningkatan pendapatan, memperbaiki kesehatan mental, serta memperkuat modal sosial.
Untuk mengatasi kompleksitas masalah yang terjadi, setidaknya terdapat sejumlah langkah strategis yang dapat dilakukan pemerintah guna menjembatani disparitas tersebut dan mendukung penyandang disabilitas dalam mengejar ketertinggalan akses teknologi serta kontribusi mereka dalam aktivisme digital.
Pertama, pemerintah perlu merumuskan seperangkat kebijakan yang mendukung transformasi digital yang inklusif bagi penyandang disabilitas. Wacana transformasi digital yang digembar-gemborkan pemerintah harus benar-memperhatikan prinsip-prinsip demokrasi dan pemenuhan terhadap hak asasi manusia.
Kebijakan ini harus memfasilitasi peningkatan kapasitas penyandang disabilitas dalam penggunaan teknologi informasi dan komunikasi, baik melalui lembaga pendidikan formal dan non-formal, maupun melalui kebijakan kolaborasi dengan lembaga swadaya masyarakat (LSM).
Kedua, pemerintah tak hanya perlu memperluas daya jangkau akses digital melalui penyediaan infrastruktur dan platform pelayanan publik, tetapi juga memastikan akses tersebut dapat dijangkau. Strategi konkret yang dapat diambil antara lain dengan menerapkan skema insentif hingga menjalin kemitraan dengan perusahaan penyedia layanan teknologi untuk meningkatkan ketersediaan sarana yang adaptif dan relevan dengan kebutuhan kelompok mereka.
Ketiga, cara lain untuk mewujudkan inklusivitas dalam ranah aksesibilitas digital adalah dengan melibatkan penyandang disabilitas secara langsung dalam proses pengujian produk digital atau sering disebut sebagai disability user testing. Melalui cara ini, para pengembang dapat memperoleh umpan balik dari pengalaman pengguna disabilitas, sehingga produk digital yang diperoleh lebih responsif terhadap kebutuhan semua kalangan.
Dengan menjembatani disparitas yang terjadi, pemerintah harus bergerak satu langkah lebih depan dalam mewujudkan transformasi digital yang inklusif sekaligus mendukung penguatan aktivisme digital di kalangan kelompok disabilitas. Pada akhirnya, upaya ini akan berkontribusi terhadap terwujudnya iklim demokrasi yang lebih inklusif dan partisipatif.