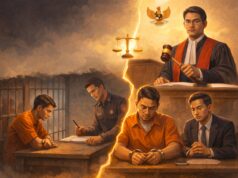“Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan.”
Kutipan yang termaktub dalam Piagam Jakarta tersebut menandai kalau apa yang dilakukan Israel dewasa ini harus dihentikan, dan kita selaku bekas korban tanah jajahan yang mengetahui penderitaan kolonialisme musti berjuang dan menyokong kemerdekaan bagi bangsa Palestina. Selain itu, dalam perjalanan kemerdekaan kita sebagai bangsa Indonesia tidak mampu menampikkan jejak sejarah atas jasa Palestina sebagai negara yang pertama kali mengakui kemerdekan Indonesia secara de facto, melalui pernyataan Syekh Muhammad Amin Al-Husaini di tahun 1944. Secara moril, melalui tulisan ini, saya sebagai bagian dari bangsa yang berhutang kepada Palestina, atas nama perdamaian dan kemanusiaan mendesak kemerdekaan total untuk bangsa Palestina.
Ekspansi yang terus-menerus dan menyebabkan penderitaan bagi warga Palestina di Gaza merupakan kekejaman luar biasa. Mengutip dari AlJazeera.com, efek akumulatif jumlah korban tewas dapat mencapai lebih dari 186.000 jiwa dan jumlah tersebut mewakili hampir 8 persen dari populasi warga Gaza sebelum perang yang mencapai 2,3 jiwa. Jumlah tersebut bukanlah kalkulasi final, dan kemungkinan besar akan terus bertambah seiring eskalasi militer yang terus dilakukan Israel. Peristiwa yang terjadi bukan hanya sekadar konflik agama, tragedi ini menyangkut kejahatan kemanusiaan dan praktik genosida yang dilakukan Zionis. Hal yang terjadi pada masa Jerman dibawah tangkup kepemimpinan sang Führer, Adolf Hitler, yang menempatkan kaum Yahudi dan kelompok Zionis sebagai target operasi pemusnahan, kini berkebalikan. Mencuat pertanyaan dasar soal mengapa kelompok ras yang pada mulanya menjadi korban, kini menjelma pelaku?
Jejak Sejarah Zionis dan Ambisi Suatu Kaum
Bila ditilik dalam sejarahnya, kehadiran bangsa Israel erat kaitannya dengan Zionisme yang merupakan suatu gerakan yang didasari oleh semangat kelompok Yahudi untuk Kembali ke tanah Zion, tanah yang dijanjinkan. Menurut Satrianingsih dan Abidin (2016: 174) Istilah Zionisme berasal dari akar kata zion atau sion yang pada masa awal sejarah Yahudi merupakan sinonim dari perkataan Jerusalem. Dalam bahasa Ibrani adalah tsyon, memiliki arti bukit yang merujuk kepada bukit suci Jerusalem sebagai simbol dari konsep teokrasi Yahudi. Melalui perjalanan sejarah yang panjang membawa Zion yang pada mulanya sebatas narasi religi semata, bermanuver menuju gerakan politik. Nathan Bernbaum (pada tahun 1776) merupakan penggagas istilah Zionisme dalam makna politik, dan Yahuda Al-Kalai sebagai tokoh Yahudi pertama yang menggagas pembentukan negara Yahudi di tanah Palestina (Maulani, 2002: 7-8). Secara tidak langsung, berdasarkan jejak historis-ideologisnya, Zionisme sudah menargetkan Palestina menjadi tanah jajahan yang musti ditaklukan, dan bangsa barat turut serta dalam memuluskan langkah Zionis mewujudkan proyek ambisiusnya.
Menurut Al-Saqqa (dalam Satrianingsih & Abidin, 2016: 178), spirit pergerakan politik masyarakat Yahudi untuk menduduki Palestina sudah dapat diprediksi melalui gerakan Makkabiy yang terjadi 586-538 SM silam yang bertujuan untuk membangun Kembali Haikal Sulaiman di tanah Zion, gerakan Bar Kokhba (118-138 M) untuk membangun peradaban khusus kaum Yahudi, dan gerakan David Robin yang terjadi di tahun 1501-1532 Masehi yang mendesak orang-orang Yahudi untuk mendirikan Kerajaan Israel di Palestina.
Dari masa ke masa niatan kelompok Yahudi dalam gerakan Zionisme semakin menguat, bukan hanya karena diskriminasi rasial yang mereka dapatkan dari bangsa Eropa namun juga diakibatkan karena doktrin agama dan sokongan dari imperialis di zamannya. Bukan hanya di masa sekarang. Awal abad 18, Napoleon Bonaparte berusaha merebut hati para kaum Yahudi dengan tujuan memperoleh bantuan keuangan (Satrianingsih & Abidin, 2016: 178). Napoleon berkenan terlibat dalam pengembalian kejayaan Jerusalem lama, di era Raja David dan Solomon. Kemudian, pada tahun 1916, kemenangan Perang Dunia I menghasilkan perjanjian Sykes Picot menyoal pembagian kekuasaan jazirah Arab untuk Inggris dan Perancis sebagai pemenang perang. Selang setahun kemudian Inggris mengeluarkan deklarasi Balfour yang berisi dukungan pembentukan negara Yahudi di Palestina (Maulani, 2002: 30).
Peristiwa deklarasi Balfour di tahun 1917 menjadi akar muasal terbentuknya sistem kenegaraan yang dicita-citakan kaum Yahudi, sekaligus menguatkan kedudukan Israel secara de jure. Imperium barat adalah sosok yang terlibat dan bertanggung jawab atas terbentuknya mentalitas nasionalisme fanatik dalam kelompok Zionis, juga konflik dehumanisasi yang terus dilestarikan sampai kini. Keterlibatan Amerika dalam konflik yang menjalar antara Iran dan Israel pada Juni 2025 kemarin, menandai hubungan Istimewa negara adidaya itu dengan Israel. Kesan paradoks dan kontradiksi tampak nyata diperlihatkan oleh anggota Istimewa Perserikatan Bangsa-bangsa, organisasi penjaga perdamaian dunia, lewat keberpihakannya kepada satu sisi. Entah kepentingan apa yang mereka bawa, yang jelas peristiwa yang tak habis-habisnya ini mencerminkan ketegangan antara nasionalisme, kolonialisme, dan hak asasi manusia.
Kekejaman Kolonialisme, Totalitarianisme, dan Perenggutan Hak-hak Dasar Manusia
Pengalaman hidup Hannah Arendt sepatutnya dihayati oleh para Zionis dan para praktikus penjajahan untuk merefleksikan perbuatannya. Arendt sebagai seorang Yahudi Ashkenazi-Jerman yang lahir di Jerman pada 1906, hidup sebagai Yahudi di tengah kebangkitan antisemitisme menempatkan dirinya sebagai korban Perang Dunia ke-II yang harus hidup dalam pelarian, mengungsi untuk menghindari kejaran Nazi. Hal tersebut menyebabkan Arendt banyak menuangkan penderitaannya lewat pikiran kritis, misalnya dalam karyanya The Origin Of Totalitarianism dan The Human Condition. Meski jadi bagian kaum Yahudi, kala itu, Arendt tidak mendukung Zionisme politik dalam bentuk yang dominan. Ia mendukung gagasan Yahudi untuk memiliki rumah sendiri, tetapi tidak dalam bentuk negara-bangsa eksklusif yang menyingkirkan penduduk asli Palestina.
Dalam esai yang Hannah Arendt tulis, To Save the Jewish Homeland (1948: 475-482), Arendt memperingatkan bahwa pendekatan Zionisme yang berbasis kolonialisme Eropa dan nasionalisme sempit akan membawa bencana bagi Yahudi dan Arab Palestina. Arendt menulis bahwa “suatu bangsa kecil yang memproklamasikan nasionalisme yang eksklusif di tengah Timur Tengah yang penuh permusuhan akan menghadapi perlawanan tanpa akhir”. Ia melihat bahwa pengadaptasian logika kolonialisme Eropa ke Palestina berarti mengabaikan keberadaan rakyat Arab yang telah mendiami tanah itu selama berabad-abad. Lebih lanjut, ia menyarankan bentuk negara bi-nation, di mana Yahudi dan Arab dapat hidup bersama sebagai warga setara dalam satu komunitas politik (Arendt, 1948: 343). Namun, usulan ini termarginalkan, kalah oleh arus utama Zionisme politik yang lebih populer memilih mendirikan negara-bangsa Yahudi sendiri.
Menurut Arendt, eksklusifitas nasionalisme semacam Ultra-Nasionalis ini tidak hanya berbahaya bagi Palestina, tetapi juga bagi Yahudi itu sendiri karena memperkuat permusuhan, mengasingkan diri dari tetangga, dan membawa mereka pada logika kekerasan yang sama dengan yang pernah mereka derita di masa Jerman ketika mengemban ideologi totaliter fasisme. Arendt (1973: 459) berpendapat dari keyakinan modern yang memandang segala hal itu mungkin menyebabkan tindakan manusia mengandung dimensi ketakterdugaan dan ketakpengharapan, dan totalitarianisme hadir mengubah “iman” modernisme yang pada mulanya “segala sesuatu adalah mungkin” menjadi “segala sesuatu dapat dihancurkan”. Totalitarianisme menciptakan keseragaman paham dalam kepala manusia yang beragam, menjadikan mereka tertutup dan menolak kehadiran manusia lain yang berbeda. Tampak nyata, apa yang dilakukan Israel dewasa ini tak jauh berbeda dengan keadaan Jerman di tahun 1930-an saat dominasi, supremasi, dan superioritas Nazi berada di puncaknya.
Pengalaman para pengungsi Yahudi di Eropa dalam Perang Dunia ke-II dan para pengungsi Palestina setelah 1948 sampai saat ini, mencerminkan satu konsep penting dari Arendt: statelessness atau kondisi tanpa negara. Dalam bukunya, The Origins of Totalitarianism (Arendt, 1973: 292), ia menggambarkan bagaimana jutaan orang yang kehilangan kewarganegaraan di Eropa abad ke-20 juga kehilangan “hak untuk memiliki hak”. Bagi Arendt, hak-hak asasi manusia hanya dapat dijamin jika seseorang diakui sebagai warga negara dalam suatu komunitas politik. Ketika status kewarganegaraan hilang, seseorang kehilangan bukan hanya tempat tinggal, tetapi juga status sebagai subjek hukum dan politik.
Kerugian pertama yang dialami oleh orang-orang yang tidak memiliki hak adalah hilangnya rumah mereka, ini berarti hilangnya tatanan sosial dan tempat mereka membangun tempat sendiri di dunia (Arendt, 1973: 293). Kondisi tersebut sangat relevan bagi jutaan pengungsi Palestina yang hingga kini banyak hidup di kamp-kamp pengungsi tanpa kewarganegaraan yang diakui, hak kembali yang nyata, atau hak-hak politik secara penuh. Dalam pandangan Arendt, situasi ini adalah tragedi ganda: orang-orang ini tidak hanya terusir secara fisik dari tanahnya, tetapi juga secara politis dari dunia.
Politik Sebagai Ruang Hidup Bersama
Di balik kritiknya terhadap nasionalisme eksklusif, dalam bukunya, The Human Condition, Arendt juga menawarkan visi politik yang lebih positif: politik sebagai public realm, ruang bersama, di mana individu dapat tampil, berbicara, dan bertindak sebagai setara. Bagi Arendt, politik ideal bukanlah dominasi satu kelompok atas yang lain, melainkan pembentukan komunitas yang mampu mengakui perbedaan namun tetap bersatu melalui percakapan dan tindakan Bersama (Arendt, 2019: 22-27). Ia memandang politik sebagai hal yang mencirikan kemanusiaan, maka dari itu keterikatan antara ruang publik dan politik tidak dapat dipisahkan.
Hannah Arendt (2019: 50-55) mendefinisikan ruang publik dalam dua pengertian yaitu, ruang penampakan dan dunia bersama. Ia mengatakan kalau ruang penampakan adalah sesuatu yang bisa dilihat dan didengar oleh orang lain layaknya oleh diri kita sendiri yang menentukan dan meyakinkan kehadiran kita dalam realitas dunia. Sedangkan, ruang publik sebagai ruang bersama (common world) dalam pengertiannya ialah dunia tempat hidup bersama, yang dipahami bersama, ruang yang sama yang didalamnya menyimpan perbedaan pandangan pribadi.
Ruang publik sebagai ruang penampakan berfungsi mengurasi dan menyeleksi suatu kepentingan bersama yang menjadi prioritas di antara kepentingan privat. Ruang penampakan akan memisahkan hal yang tidak relevan dengan kehidupan bersama, dan “cahaya kepublikan” akan menyinari apa yang privat, bukan sebaliknya (Arendt, 2019: 51). Maka, yang terjadi dalam tatanan masyarakat Israel, para aktivis Zionis, dan negara-negara penyokongnya telah menampakkan praktik kepentingan privat yang diberlakukan dalam ruang publik. Hal tersebut tidak hanya menyangkut Masyarakat Palestina yang tereksodus dari tanahnya, namun juga mengancam kita sebagai sesama penghuni ruang publik.
Perspektif politik Arendt menitik beratkan kepada tindakan, yang menjadi dasar manusia hidup aktif (vita activa). Tindakan memiliki kaitan erat dengan pluralitas manusia, sebab tindakan adalah aktivitas politik Par Excellence (Arendt, 2019: 7). Dalam kata lain, pluralitas merupakan kunci dari berlangsungnya tindakan politik. Pluralitas menjadi prasyarat dasar dari tindakan dan wicara, tempat berlangsungnya dialektika antara kesamaan/kesetaraan dan perbedaan (Arendt, 2019: 175). Berdasarkan kaitannya dengan ruang publik, manusia hadir diantara manusia yang lainnya merupakan bentuk pluralitas yang menjadi prasyarat terjalinnya tindakan dalam kehidupan politik. Saat ruang publik menjadi ruang privat maka ruang penerimaan terhadap keragaman tidak lagi ada, tindakan (termasuk wicara) tidak lagi terjalin, dan politik pun menjadi lenyap ketika yang publik menjadi privat.
Gambaran yang dapat diamati bersama ketika Konferensi PBB yang membahas konflik antara Israel-Palestina sejak tahun 1970-an tak juga menemukan solusi penyelesaiannya. Dalam konteks pandangan ini, berarti bahwa solusi sejati tidak mungkin dicapai selama logika pengusiran, eksklusi, dan supremasi satu pihak atas pihak lain tetap dipertahankan. Hanya dengan mengakui keberadaan, hak, dan martabat pihak lain sebagai setara, sebuah ruang publik dengan kehidupan politik yang adil dapat dibangun.
Gugatan Hannah Arendt
Semakin jelas, gejolak konflik Israel–Palestina merupakan tragedi kemanusiaan yang melibatkan praktik kolonialisme, nasionalisme eksklusif, dan pengabaian hak-hak asasi manusia. Dalam perspektif Hannah Arendt, situasi ini tidak hanya mencerminkan kegagalan politik modern, tetapi juga reproduksi pola-pola penindasan yang pernah dialami kaum Yahudi sendiri di bawah rezim totalitarian Jerman.
Lewat buah pikir Arendt, terproyeksi bahwa nasionalisme Zionis yang mengambil bentuk negara-bangsa eksklusif di tanah Palestina tidak hanya mengabaikan keberadaan masyarakat Arab yang telah lama mendiami wilayah tersebut, tetapi juga memperkuat konflik yang tak berkesudahan. Gerakan Zionis yang semula merupakan narasi religius bergeser menjadi ambisi politik kolonialis dengan dukungan kekuatan imperialis Barat.
Lebih lanjut, Arendt mengingatkan lewat kondisi statelessness yang dialami para pengungsi Palestina sejak 1948 adalah salah satu bentuk perampasan hak paling mendasar, yaitu hak untuk memiliki hak. Bukan hanya hak-hak yang Nampak secara fisik, namun juga hak bertindak dan berkehendak bebas (free will). Tanpa pengakuan sebagai warga dalam komunitas politik, mereka kehilangan tempat tinggal, status hukum, dan martabat kemanusiaan.
Sebagai solusi, Arendt mengusulkan pemulihan ruang publik (public realm) sebagai tempat politik yang inklusif, di mana pluralitas manusia diakui dan semua pihak dapat tampil serta bertindak sebagai warga yang setara. Ia menekankan bahwa hanya dengan mengembalikan politik pada esensinya (sebagai ruang bersama untuk berbicara dan bertindak secara kolektif) maka perdamaian yang adil dapat dituai di muka dunia sebagai ruang hidup bersama.
Dengan demikian, untuk mewujudkan keadilan bagi rakyat Palestina dan Israel, dunia internasional perlu mengedepankan prinsip-prinsip kemanusiaan, pengakuan terhadap hak yang setara, serta keberanian untuk meninggalkan logika kolonialisme dan dominasi. Visi Hannah Arendt mengajarkan bahwa kemerdekaan, martabat, dan pengakuan adalah hak setiap bangsa dan individu yang tidak dapat ditawar atas dalih apapun.
Referensi
Arendt, H. (1948). To Save the Jewish Homeland. Commentary, 6, 398.
Arendt, H. (1973). The origins of totalitarianism [1951]. New York.
Arendt, H. (2019). The human condition. University of Chicago press.
Maulani, Z. A. (2002). Zionisme: Gerakan Menaklukkan Dunia. Daseta.
Satrianingsih, A., & Abidin, Z. (2016). Sejarah zionisme dan berdirinya negara Israel. Jurnal Adabiyah, 16(2), 172–184.