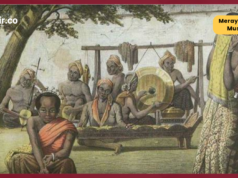“Dan beberapa hari setelah itu sang gadis harus tinggalkan dapurnya, suasana kampungnya, kampungnya sendiri dengan bau amis abadinya.”
Seorang perempuan berusia empat belas tahun, sehari-hari menghabiskan waktunya di pantai–berbakti membantu orang tuanya yang nelayan. Seperti itulah penggambaran Gadis Pantai sebagai sosok yang terbiasa bekerja kasar di usianya yang masih belia. Di zaman saat Gadis Pantai dibesarkan, merupakan hal yang wajar apabila anak di bawah umur menghabiskan hari-hari sebagai pekerja kasar. Fakta ini juga memiliki kaitan erat dengan kelas ekonomi. Gadis Pantai hanyalah perempuan pesisir dan anak nelayan yang tak mampu baca tulis.
Latar waktu dalam novel Gadis Pantai tidak secara gamblang dijelaskan. Akan tetapi pada perjalanannya, dapat disimpulkan kejadian-kejadian dalam novel Gadis Pantai terjadi pada awal abad dua puluh. Di awal abad ini, penjajahan kolonial Belanda berjalan beriringan dengan feodalisme, khususnya di pulau Jawa.
Kentalnya feodalisme yang digambarkan dalam novel ini telah diperlihatkan sejak awal babak. Tanpa aba-aba, Gadis Pantai diambil dari orang tuanya untuk dinikahkan dengan seorang Bendoro. Bendoro pada masa itu dapat diposisikan sebagai seorang priyayi, berasal dari kelompok elit dalam struktur masyarakat Jawa.
Prosesi pernikahan yang dialami Gadis Pantai terjadi begitu cepat. Kehadiran Bendoro diwakilkan hanya dengan sebilah keris. Bahkan sejak awal terjadinya pernikahan, kedudukan Gadis Pantai sebagai perempuan sangatlah timpang. Fakta ini menunjukkan bahwa laki-laki dalam masayarakat patriarkal memiliki privilege atau hak istimewa dalam prosesi pernikahan. Ketidakhadiran Bendoro sebagai suaminya bukan menjadi masalah, justru dengan perwakilan sebilah keris, masyarakat pada saat itu menilai Gadis Pantai beruntung karena menikah dengan seseorang yang terpandang.
Dalam latar masyarakat patriarki, menikah merupakan tahapan hidup yang dianggap menguntungkan untuk perempuan–sekalipun ia berstatus sebagai selir. Terlebih, Gadis Pantai berasal dari keluarga nelayan dengan kemampuan ekonomi yang rendah dan rentan. Orang tua Gadis Pantai secara sukarela membiarkan anak perempuannya diambil jadi kepunyaan seorang Bendoro. Justru rasa bangga menyelimuti hati mereka walaupun keseharian dan status ekonomi tetap tidak berubah. Menjadi wanita utama dari Bendoro tak lantas menjadikan orang tua Gadis Pantai makmur, keseharian sebagai nelayan–dengan hasil tangkapan yang tak pasti–tetap harus dihadapi mereka setiap hari.
Kehidupan Baru Si Perempuan Pesisir
Gadis Pantai yang masih belia, yang bahkan belum mengerti menstruasi, harus mengalami perubahan hidup yang sama sekali asing baginya. Kepindahannya dari pesisir ke istana megah milik Bendoro membuatnya meraba-raba bagaimana harus bertingkah laku.
Kedatangan Gadis Pantai ke tempat baru tak serta merta disambut Bendoro. Pelayan perempuan terlebih dahulu ditugaskan untuk merawat Gadis Pantai sebelum mendapatkan izin untuk bertemu Bendoro. Tergambar dengan jelas Gadis Pantai berposisi sebagai pihak yang rentan dan tak berdaya. Dalam waktu yang sangat singkat dirinya bersuamikan laki-laki yang belum dilihatnya secara langsung, bahkan setelah resmi menjadi seorang istri.
Bendoro diceritakan sebagai laki-laki yang jarang berada di rumah. Lebih sering bekerja dan berada di luar untuk urusan perang. Walaupun belum mengenal lebih mendalam, Gadis Pantai secara otomatis tunduk pada Bendoro tiap kali mereka berkesempatan bertemu.
Ketidaksetaraan relasi antara istri dan suami merupakan hal yang kerap terjadi dalam masyarakat patriarki. Kentalnya budaya patriarki membuat Gadis Pantai tak pernah mempertanyakan nasibnya yang menjadi manusia kelas dua dalam struktur rumah tangga. Tak lain penyebabnya karena budaya ini telah mengakar cukup kuat dan dinormalisasi dalam laku hidup, ditambah nilai-nilai feodalisme yang beriring bersamaan dengan budaya ini.
Inferiority Complex pada Tokoh Mbok
Beberapa dialog dalam Gadis Pantai menunjukkan beban berlapis yang dialami perempuan akibat patriarki sekaligus feodalisme. Beban berlapis tersebut tak hanya dialami Gadis Pantai sendiri, tetapi juga Mbok (sebutan untuk perempuan tua pesuruh) yang berperan sebagai pelayannya. Beban ganda tersebut terdiri dari pertama, fakta bahwa identitasnya sebagai perempuan dan kedua, sebagai sahaya (budak atau proletar). Dialog yang menunjukkan fakta tersebut adalah sebagai berikut.
“Ah, Mas Nganten, di kota, barangkali di semua kota–dunia kepunyaan lelaki…”
“Lantas apa yang dipunyai perempuan kota?”
“Tak punya apa-apa, Mas Nganten kecuali…”
“Ya?”
“Kewajiban menjaga setiap milik lelaki”
“Lantas milik perempuan itu sendiri apa?”
“Tidak ada, Mas Nganten. Dia sendiri hak-milik lelaki.”
Dialog tersebut berlangsung antara Gadis Pantai (disebut sebagai Mas Nganten) dan Mbok (pelayan pribadi Gadis Pantai). Dialog ini juga memperjelas kedudukan Gadis Pantai yang menjadi kepunyaan laki-laki–kepunyaan priyayi. Dalam situasi tersebut, Gadis Pantai mulai bertanya-tanya mengapa nilai dirinya sama dengan meja, kursi, lemari, dan kasur. Fenomena ini juga termasuk objektifikasi yang dialami perempuan dalam latar masyarakat patriarki sekaligus feodalisme, karena tak lebih dari sekadar kepunyaan laki-laki priyayi.
Selain dialog di atas, terdapat pula pernyataan dari Mbok yang seolah mengamini ketidakadilan yang dialaminya sebagai perempuan dalam masyarakat patriarki dan feodal.
“Perempuan ini diciptakan ke bumi, Mas Nganten, barangkali memang buat dipukul lelaki. Karena itu jangan bicarakan itu, Mas Nganten. Pukulan itu apakah artinya kalau dibandingkan dengan segala usahanya buat bininya, buat anak-anaknya. Kalau saja Tuhan dulu mengurniakan sahaya anak, barangkali seorang, barangkali juga selusin? Apakah artinya pukulan pada emak?”
Pernyataan Mbok menunjukkan adanya inferiority complex pada diri perempuan dalam masyarakat patriarki sekaligus feodal. Inferiority complex merupkan kondisi psikologis saat seseorang merasa tidak memiliki nilai atau kemampuan sebanding dengan orang lain. Tak hanya itu, dialog di atas juga menunjukkan pesimisme perempuan terhadap kekerasan yang dialami akibat kedudukannya sebagai kelas kedua dalam masyarakat. Seolah perempuan layak mendapatkan kekerasan sebagai bayaran atas jasa laki-laki. Bahkan, Mbok sebagai perempuan juga rela jika diposisikan sebagai pabrik anak.
Mendengar ucapan dari Mbok, Gadis Pantai mulai mempertanyakan posisinya sebagai istri dari seorang priyayi. Terdapat kebingungan dalam dirinya akan status tersebut. Setelah menjadi istri seorang Bendoro, apakah Gadis Pantai sudah pasti menjadi priyayi juga? Pertanyaan pun kemudian dilontarkan Gadis Pantai kepada Mbok.
“Lantas aku ini, bagaimanakah aku ini?”
“Mas Nganten ampunilah sahaya. Sahaya bukan bermaksud jelek. Boleh sahaya bicara?”
“Ah, Mbok apa yang salah pada diriku?”
“Tidak Mas Nganten Cuma saja ….”
“Apa salahku?”
“Salah Mas Nganten seperti salah sahaya, salah kita, berasal dari orang kebanyakan.”
“Lantas Mbok, lantas?”
“Kita sudah ditakdirkan oleh yang kita puji dan yang kita sembah buat jadi pasangan orang atasan. Kalau tidak ada orang-orang rendahan, tentu tidak ada orang atasan.”
“Aku ini, mbok, aku ini orang apa? Rendahan? Atasan?”
“Rendahan Mas Nganten, maafkanlah sahaya, tapi menumpang di tempat atasan.”
“Jadi apa mesti aku perbuat, Mbok?”
“Ah, beberapa kali sudah sahaya katakan. Mengabdi, Mas Nganten. Sujud, takluk sampai ke tanah pada Bendoro…”
Dari dialog di atas, secara jelas tergambarkan logika berpikir yang diyakini perempuan terkhusus dari kelas proletar pada masa itu. Mbok begitu menerima kedudukannya dalam belenggu feodalisme. Nasib sebagai pesuruh yang tidak dapat diubah dianggap sebagai suatu kepastian dalam hidup yang harus dihadapi. Selain itu, Gadis Pantai pun tetap berstatuskan kelas rendahan dan hanya anak nelayan sekalipun dirinya bersuamikan seorang Bendoro priyayi. Kedudukan perempuan yang tetap menjadi kelas kedua dan berada di bawah laki-laki tidak akan berubah selama ia bukan berasal dari kelas priyayi.
Sekalipun Gadis Pantai disebut sebagai wanita utama dan memiliki pelayan pribadi, tetap saja terdapat jarak antara dirinya dengan suaminya. Menjadi seorang istri dari priyayi hanyalah status yang tak mengubah kedudukan Gadis Pantai yang seorang anak nelayan. Justru, status sebagai istri berarti harus melaksakan penghambaan terhadap suami–terlebih jika ia seorang priyayi. Relasi ini semakin memperjelas objektifikasi terhadap perempuan dan perbedaan kelas. Berikut dialog yang menunjukkan ketidaksetaraan relasi antara Gadis Pantai dan Bendoro. Dialog ini juga memperlihatkan bahwasanya perempuan hanya memahami dirinya sebagai kepunyaan dan hak milik laki-laki.
“Kau tak ingin lihat orang tuamu?”
“Tidak Bendoro, sahaya lebih suka melayani Bendoro.”
“Tapi kau anaknya, kau bukan hanya istriku.”
“Sekarang ini kewajiban sahaya adalah mengabdikan diri pada Bendoro. Orang tua sahaya dapat menolong diri sendiri tanpa sahaya, Bendoro.”
“Tak pernah kau kirim utusan ke sana?”
“Tidak Bendoro.”
“Tentu aku percaya. Tak pernah kirim uang atau pakaian ke sana?”
“Tidak Bendoro.”
“Aku percaya, tapi mengapa?”
“Saya tak berani Bendoro. Sahaya hanyalah sahaya.”
Dalam masyarakat feodal, seorang perempuan kelas rendah yang menikah dengan priyayi tidak dianggap sebagai seorang Nyonya. Statusnya sebagai wanita utama sebenarnya tak lebih dari sekadar selir. Sikap dari Bendoro sendiri sebagai laki-laki dari kelas priyayi dapat dinilai manipulatif, karena sikap dan ucapannya tidak sejalan. Saat berkomunikasi dengan Gadis Pantai, Bendoro terkesan lemah lembut. Di belakang itu, dirinya sama sekali tidak menghargai dan menganggap Gadis Pantai sebagai pendampingnya. Berikut terdapat dialog yang menunjukkan betapa Bendoro tidak mau menganggap Gadis Pantai sebagai istri karena perbedaan latar belakang dan statusnya.
“Bendoro sahaya dengar ada bajak menyerbu kampung nelayan ….”
“Kampung nelayan mana?”
“Kampung … beribu ampun. Bendoro … kampung nyonya Bendoro.”
“Nyonyaku?” Bendoro menjawab setengah berteriak. “Aku belum punya nyonya!”
“Beribu ampun, Bendoro. Beribu ampun. Sahaya diutus surat kabar sahaya dari Semarang buat datang ke mari, menghadap Bendoro dan menanyakan soal ini. Kantor Pusat sahaya yang kasih keterangan.”
“Pergi, sebelum aku marah.”
Kejahatan Feodalisme pada Perempuan
Pada bagian keempat, dikisahkan Gadis Pantai mengandung anak dari Bendoro. Setelah bayi perempuan itu lahir, Bendoro buru-buru menceraikan si Gadis Pantai. Dalam konteks ini, terlihat bahwa perempuan hanya dianggap sebagai pabrik anak. Pasalnya, setelah melahirkan, Gadis Pantai diusir dari rumah dan harus kembali ke pantai. Tak hanya sekadar objektifikasi, Feodalisme lagi-lagi menormalisasi ketidakadilan antar manusia, khususnya perempuan– dengan status dan latar belakang yang bukan dari kalangan priyayi.
“Seribu ampun Bendoro. Sahaya dengar tuanku telah ceraikan sahaya.”
“Apa kau tak suka?”
“Sahaya cuma seorang budak yang harus jalani perintah Bendoro.”
“Apalagi?”
“Sahaya belum lagi mempersembahkan anak ini kepada Bendoro. Inilah putri tuanku Bendoro. Putri tuanku sendiri, bukan anak orang lain.”
“Kau tinggalkan rumah ini! Bawa seluruh perhiasan dan pakaian. Semua yang telah kuberikan padamu. Bapakmu sudah kuberikan uang kerugian, cukup buat membeli dua perahu sekaligus dengan segala perlengkapannya. Kau sendiri, ini …,”
Bendoro mengulurkan kantong berat berisikan mata uang …. pesangon.
“Carilah suami yang baik, dan lupakan segala dari gedung ini. Lupakan aku, ngerti?”
“Sahaya, Bendoro.”
“Dan ingat. Pergunakan pesangon itu baik-baik. Dan … tak boleh sekali-kali kau menginjakkan kaki di kota ini. Terkutuklah kau bila melanggarnya.. Kau dengar?”
Gadis Pantai dalam bagian keempat (bagian terakhir) ini seolah hanya diposisikan sebagai istri dalam masa kontrak tertentu. Setelah melahirkan, ia pun dipaksa dipisahkan dengan bayinya. Tak hanya itu, Bendoro juga memperlihatkan ketidakpuasannya pada jenis kelamin si bayi. Kedudukan perempuan pada era Feodalisme tidak dipandang sebagai subjek. Pertama kalinya seorang bayi perempuan menghirup udara di dunia pun keberadaannya dianggap tidak berharga.
“Jadi sudah lahir dia. Aku dengar perempuan bayimu, benar?”
“Sahaya, Bendoro.”
“Jadi cuma perempuan?”
“Seribu ampun, Bendoro.”
Kritik Pram pada Patriarki dan Feodalisme
Dalam novel ini, Pram menggambarkan sangat jelas ketimpangan demi ketimpangan relasi antar gender. Setiap peristiwa dan dialog menunjukkan narasi patriarkis yang telah mengakar menjadi konstruksi berpikir masyarakat dalam era tersebut. Pram juga memperlihatkan sikap-sikap manipulatif yang dilakukan laki-laki dalam budaya patriarki dan feodalisme terhadap perempuan. Melalui tokoh Bendoro, kita dapat menilai betapa ketimpangan gender dan kelas tetap direproduksi oleh kalangan feodal.
Selain itu, sikap inferiority complex yang ditunjukkan melalui tokoh Mbok dan Gadis Pantai juga memperlihatkan patriarki dan feodalisme begitu merusak. Internalisasi sikap-sikap yang kerap merendahkan diri sepanjang cerita dapat kita temukan secara jelas. Sikap-sikap tersebut diinternalisasi oleh tokoh-tokoh dengan latar belakang yang bukan priyayi, akibat adanya ketimpangan relasi kuasa dalam era feodalisme.
Penulis melihat bahwa Pram dalam setiap karyanya selalu berhasil mengajak para pembaca untuk kembali merenungi dan sadar pada ketimpangan-ketimpangan yang sering dianggap normal. Kritik Pram pada timpangnya relasi kuasa dan gender mengajak pembaca untuk marah dan sadar pada fenomena tersebut. Tidak hanya terjadi pada masa kolonial, patriarki dan feodalisme masih menjadi PR yang perlu dan harus kita selesaikan bersama sampai detik ini.