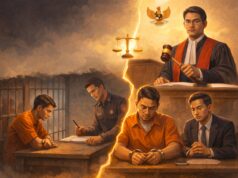Dalam setiap diskusi tentang kebebasan pers, kita sering membayangkan media besar dengan wartawan yang bekerja penuh waktu, dilindungi oleh institusi redaksi, serta memiliki jaringan organisasi profesi yang kuat. Gambarannya jelas, ada ruang redaksi, ada perusahaan pers, ada biro hukum yang bisa turun tangan ketika terjadi sengketa. Namun, ada kelompok lain yang tak kalah penting perannya tetapi justru berada di pinggiran perlindungan hukum, yakni kolumnis dan kontributor lepas. Mereka menulis opini, esai, laporan analitis, atau feature yang kadang justru lebih tajam dan berani untuk komprontatif. Ironisnya, peran itu dijalankan tanpa jaminan hukum yang tegas ketika ancaman datang.
Jika kita kembali pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, regulasi ini memang dirancang untuk menegakkan kemerdekaan pers. Di dalamnya, wartawan didefinisikan sebagai orang yang secara teratur melakukan kegiatan jurnalistik. Frasa “secara teratur” ini tampak sederhana, tetapi implikasinya besar. Kolumnis yang hanya menulis seminggu sekali atau kontributor lepas yang mengirimkan tulisan berdasarkan panggilan kebutuhan tidak selalu bisa dianggap bekerja secara teratur. Akibatnya, posisi mereka dalam struktur hukum menjadi kabur. Mereka menulis di media, tetapi tidak jelas apakah karya mereka berhak mendapat perlindungan yang sama dengan wartawan yang setiap hari turun ke lapangan.
Kekosongan itu makin nyata ketika kita membaca Pasal 8 Undang-Undang Pers. Pasal tersebut menyatakan bahwa wartawan dalam melaksanakan profesinya mendapat perlindungan hukum. Subjek yang dilindungi disebut secara eksplisit yaitu wartawan. Tidak ada penyebutan kolumnis, penulis opini, atau kontributor lepas. Dengan demikian, secara tekstual perlindungan Pasal 8 tidak otomatis berlaku bagi mereka. Padahal, banyak di antara kontributor lepas yang menjalankan kerja jurnalistik, bahkan menyumbang fungsi kontrol sosial yang sama pentingnya dengan wartawan tetap. Maka celah ini membuat posisi kolumnis dan kontributor lepas menjadi lebih rapuh karena tidak punya dasar normatif yang sekuat wartawan.
Diambang Ketidakpastian Perlindungan
Contoh-contoh kasus di lapangan memperlihatkan betapa rapuhnya posisi mereka. Pada Mei 2025 seorang penulis opini di Detik.com diduga mengalami intimidasi. Alih-alih dilindungi sebagai bagian dari kerja jurnalistik, penulis itu justru menerima ancaman serius baik di ranah digital maupun dalam kehidupan pribadi. Kasus serupa terjadi pada penulis opini di AJNN.Net yang dipolisikan karena tulisannya dianggap mencemarkan nama baik. Situasi ini menunjukkan bahwa kolumnis yang bekerja independen tidak memiliki perisai hukum yang kuat ketika menghadapi tekanan.
Praktik intimidasi hingga upaya kriminalisasi seperti ini memperlihatkan bahwa ketika statusnya bukan wartawan tetap, maka perlindungan yang diberikan undang-undang tidak secara otomatis menjangkau mereka. Konsekuensinya, penulis harus menghadapi risiko hukum sendirian, tanpa dukungan mekanisme perlindungan yang semestinya disediakan negara.
Kekosongan hukum ini bukan sekadar persoalan teknis, tetapi persoalan fundamental dalam demokrasi. Data dari Aliansi Jurnalis Independen (AJI) menunjukkan bahwa kekerasan terhadap jurnalis masih terjadi dalam skala yang mengkhawatirkan.
Memang benar, Dewan Pers berusaha menambal celah ini dengan berbagai kebijakan. Tetapi, regulasi yang tersedia tidak punya kekuatan setara undang-undang ketika berhadapan dengan proses pidana. Apalagi, kriminalisasi terhadap karya jurnalistik sering kali menggunakan pasal pidana pencemaran nama baik atau pasal karet dalam undang-undang lain. Tanpa dasar hukum yang eksplisit, posisi kolumnis dan kontributor lepas dalam menghadapi aparat penegak hukum tetap rapuh.
Kita memang patut mengapresiasi langkah-langkah koordinasi antara Dewan Pers dan Kepolisian melalui nota kesepahaman yang ditandatangani pada 2022. Intinya, polisi diharapkan merujuk setiap sengketa karya jurnalistik kepada mekanisme Dewan Pers, bukan langsung ke ranah pidana. Tetapi efektivitas kesepahaman ini sangat bergantung pada komitmen aparat di lapangan. Tidak jarang, dalam praktiknya, laporan polisi tetap diterima dan proses hukum tetap berjalan meski karya itu jelas-jelas memenuhi syarat sebagai karya jurnalistik. Di titik inilah terlihat jelas bahwa perlindungan hukum berbasis perjanjian kelembagaan saja tidak cukup.
Menata Regulasi yang Inklusif
Lalu apa yang harus dilakukan. Pertama, kita perlu memperluas definisi wartawan dalam undang-undang agar mencakup individu yang menjalankan kerja jurnalistik meskipun tidak dalam struktur perusahaan pers. Perlindungan tidak boleh dibatasi hanya pada mereka yang bekerja penuh waktu. Yang lebih esensial adalah apakah tulisan atau karya itu menjalankan fungsi pers, yakni memberi informasi, melakukan kontrol sosial, dan membuka ruang publik bagi perdebatan.
Kedua, negara harus menjamin akses kontributor lepas terhadap bantuan hukum ketika mereka menghadapi gugatan atau tuntutan pidana akibat karyanya. Selama ini, banyak kontributor yang menghadapi masalah sendirian, tanpa kuasa hukum, tanpa perlindungan organisasi. Padahal, mereka sedang menjalankan fungsi yang sesungguhnya menjadi bagian dari kepentingan publik. Mekanisme bantuan hukum publik atau skema kolaborasi antara Dewan Pers, organisasi profesi, dan lembaga bantuan hukum bisa menjadi jawaban.
Ketiga, perlu ada pembatasan yang lebih ketat terhadap penggunaan pasal pidana dalam kasus sengketa karya jurnalistik. Prinsipnya, karya jurnalistik yang dipersoalkan seharusnya diselesaikan melalui mekanisme etik, bukan pidana. Banyak negara demokrasi telah mengambil langkah ini untuk menghindari efek mengerikan dari kriminalisasi, yaitu self censorship atau pembungkaman sebelum menulis.
Keempat, perlindungan digital juga penting. Di era media sosial, ancaman tidak hanya datang dari aparat, tetapi juga dari serangan digital, doxxing, dan intimidasi daring. Kolumnis yang menulis isu sensitif sering kali menjadi sasaran serangan semacam ini tanpa ada sistem keamanan redaksi yang bisa membantu. Negara, media, dan platform teknologi seharusnya memikul tanggung jawab bersama untuk melindungi para penulis independen dari risiko serangan digital.
Dan yang terakhir, legitimasi kontributor lepas dapat diperkuat melalui pendidikan dan standar etik yang diakui. Kolumnis atau penulis lepas bukan berarti boleh menulis seenaknya. Mereka pun harus tunduk pada kode etik jurnalistik agar publik mendapatkan kepastian bahwa yang ditulis adalah informasi dan opini yang bertanggung jawab. Dengan cara ini, mereka tidak hanya mendapat perlindungan, tetapi juga diakui sebagai bagian integral dari ekosistem pers.
Jika melihat semua uraian di atas, tampak jelas bahwa persoalan perlindungan hukum bagi kolumnis dan kontributor lepas bukan perkara kecil. Ini adalah soal menjaga kebebasan berekspresi, memastikan hak publik atas informasi, dan menegakkan demokrasi. Membiarkan celah hukum ini sama saja dengan membiarkan satu kelompok penting dalam ekosistem pers hidup dalam kerentanan permanen.
Pers bukan hanya redaksi besar atau wartawan penuh waktu. Pers juga hidup dari kolumnis yang setiap pekan menulis, dari kontributor lepas yang melaporkan fenomena lokal, dari penulis independen yang berani membuka suara minoritas. Jika negara tidak mengakui dan melindungi mereka, maka yang dirugikan bukan hanya penulis itu sendiri, tapi juga masyarakat luas yang kehilangan keragaman informasi dan suara kritis yang seharusnya hadir dalam ruang publik.
Karena itu, sudah waktunya negara, legislatif, Dewan Pers, serta organisasi profesi duduk bersama untuk merumuskan revisi atau kebijakan baru yang secara tegas memberikan perlindungan hukum kepada kolumnis maupun kontributor lepas. Demokrasi tidak bisa bertahan hanya dengan melindungi kelompok yang berada di pusat. Demokrasi justru diuji ketika ia mampu melindungi yang tersisihkan.