Sebelum Indonesia merdeka, para intelektualnya lebih dulu bertempur lewat gagasan. Buku Polemik Kebudayaan mencatat pergulatan penting tentang arah kebudayaan dan identitas keindonesiaan.
Bayangkan terdapat suatu wilayah yang berada dalam kondisi terjajah dan belum merdeka. Di dalam wilayah tersebut, terdapat perdebatan atau polemik mengenai kebudayaan. Polemiknya adalah tentang: “apakah kebudayaan pada wilayah yang dimaksud pada masa modern awal abad ke-20 adalah kelanjutan dari zaman sebelumnya ataukah justru sama sekali baru?”.
Polemik itulah yang pernah terjadi di Indonesia—saat itu bernama Hindia Belanda—pada tahun 1930-an. Achdiat K. Mihardja berjasa dalam mengumpulkan tulisan-tulisan yang berisi polemik kebudayaan tersebut. Kumpulan tulisan-tulisan polemik tersebut kemudian dibukukan dengan judul Polemik Kebudayaan: Pergulatan Pemikiran Terbesar dalam Sejarah Kebangsaan Indonesia dan diterbitkan pertama kali pada tahun 1948.
Buku yang pertama kali diterbitkan pada tahun 1948 ini memuat kumpulan 19 artikel dari 8 tokoh yang terlibat dalam polemik kebudayaan. 8 tokoh tersebut antara lain Sutan Takdir Alisjahbana (STA), Sanusi Pane, Purbatjaraka, Sutomo, Tjindarbumi, Adinegoro, M. Amir, dan Ki Hadjar Dewantara. Tulisan-tulisan tersebut awalnya tersebar di sejumlah publikasi pada masa itu, misalnya seperti majalah Poedjangga Baroe, majalah Wasita, surat kabar Soeara Oemoem, dan surat kabar Pewarta Deli.
Sebelum memasuki pembahasan utama dari buku Polemik Kebudayaan, pembaca akan disuguhkan tulisan Sekapur Sirih dari Pengumpul (hlm. ix) yang ditulis oleh Achdiat K. Mihardja. Dalam tulisan tersebut, Achdiat K. Mihardja menyampaikan bahwa: “Polemik antara Sutan Takdir Alisjahbana dengan lawan-lawannya adalah salah satu pernyataan tentang adanya unsur-unsur reaksi di dalam kebudayaan feodal yang sudah beku itu. Namun, sekalipun para polemis itu berhadap-hadapan sebagai pihak berselisih, dalam satu hal mereka itu adalah sependapat bahwa kebudayaan kita yang telah beku itu harus dibikin cair supaya mungkin bergerak lagi, mengalir terus ke arah muara kesempatan” (hlm. xii).
Dalam buku Polemik Kebudayaan, polemik dibagi menjadi tiga bab, yakni Polemik 1, Polemik 2, dan Polemik 3. Polemik 1 berisi 5 artikel, Polemik 2 berisi 11 artikel, dan Polemik 3 berisi 3 artikel. Pembagian bab-bab ini menunjukkan bahwa polemik berkembang menjadi diskursus panjang yang saling menanggapi dan menajamkan argumen.
Polemik Dimulai
Polemik kebudayaan dimulai oleh tulisan Sutan Takdir Alisjahbana (STA) berjudul Menuju Masyarakat dan Kebudayaan Baru: Indonesia–Prae-Indonesia (hlm. 3), yang menyatakan bahwa zaman Indonesia itu adalah hal yang sama sekali baru. Karena semangat keindonesiaan yaitu kemauan untuk bersatu yang didesak oleh kesadaran akan kepentingan dan cita-cita bersama belum ada sebelum abad ke-20, sehingga tokoh-tokoh seperti Diponegoro, Tuanku Imam Bonjol, dan Teuku Umar kurang tepat disebut sebagai pahlawan Indonesia karena perjuangan mereka masih bersifat kedaerahan. Karena zaman Indonesia itu adalah hal yang sama sekali baru, maka STA menyatakan bahwa sudah saatnya kebudayaan Indonesia yang baru harus tumbuh mengarah ke Barat.
Artikel tersebut membuat gempar tokoh-tokoh seperti Sanusi Pane, Purbatjaraka, Sutomo, Tjindarbumi, Adinegoro, M. Amir, dan Ki Hadjar Dewantara (KHD). Sanusi Pane kemudian membuat artikel tanggapan dengan judul Persatuan Indonesia (hlm. 18), yang menyatakan bahwa sejarah adalah rangkaian waktu yang timbul dari waktu sebelumnya. Zaman sekarang adalah kelanjutan zaman sebelumnya. Manusia tidak mampu menciptakan hal yang baru sama sekali, hal seperti itu sama seperti mengadakan barang dari yang tidak ada. Contohnya adalah Pujangga Baru yang tidak akan pernah ada jika tidak ada Pujangga Lama. Walaupun Pujangga Baru bertentangan dalam banyak hal, tetapi pertentangan itu membuahkan kelanjutan. Selain itu, Sanusi Pane juga menyatakan bahwa Barat yang lekat dengan materialisme, intelektualisme, serta individualisme dan Timur yang lekat dengan spritualisme, perasaan, serta kolektivisme bisa disatukan agar menjadi haluan yang sempurna untuk kebudayaan Indonesia yang baru.
STA kemudian membuat artikel tanggapan untuk artikel Sanusi Pane dengan judul yang masih sama, yakni Menuju Masyarakat dan Kebudayaan Baru (hlm. 26). Pada artikel tersebut, STA menyatakan bahwa Sanusi Pane keliru memahami pembagian antara kebudayaan “Indonesia” dan “pra-Indonesia” serta keliru memahami arti semangat keindonesiaan. Menurut STA, semangat keindonesiaan yang hidup di rakyat Indonesia sekarang akan melahirkan kebudayaan sendiri yang itu berbeda dengan kebudayaan pra-Indonesia. STA juga menyatakan bahwa semangat keindonesiaan sejatinya memiliki kedekatan atau kesamaan arah dengan semangat progresif yang dimiliki oleh Barat.
Kemudian muncullah artikel tanggapan dari Purbatjaraka dengan judul Sambungan Zaman (hlm. 33). Menurut Purbatjaraka, penting untuk memahami sejarah sebagai dasar merancang masa depan. Ia mengkritik pandangan STA yang kadang memutus hubungan antara masa lalu dan masa kini, meskipun STA juga sesekali mengakui adanya kesinambungan. Bagi Purbatjaraka, menengok ke belakang bukan berarti terjebak romantisme masa lalu, melainkan untuk mengenali jalannya sejarah agar bisa memilah mana yang bermanfaat bagi bangsa. Ia menekankan agar tidak terjebak pada kekunoan maupun kebaratan, tetapi memilih yang terbaik dari keduanya demi masa depan Indonesia.
Memaknai Polemik Kebudayaan
Tulisan-tulisan dalam buku Polemik Kebudayaan tidak berhenti sebagai ajang saling serang antar tokoh. Justru bisa dibilang, polemik ini memperlihatkan kesungguhan para intelektual pada masa itu dalam mencari dasar yang kokoh bagi arah kebudayaan nasional. Mereka memperdebatkan, bukan demi menang, melainkan demi memperkaya gagasan dan membuka kemungkinan baru bagi Indonesia yang sedang bertumbuh menuju kemerdekaan.
Kita bisa lihat Sanusi Pane yang tidak sekadar menolak pandangan STA, tetapi menawarkan landasan filosofis lain. Dalam artikelnya, Sanusi Pane mencoba menyatukan konsep Timur–Barat yang saling melengkapi. Baginya, Indonesia tidak harus memilih salah satu, tetapi bisa menjadi sintesis yang lebih utuh dari keduanya. Gagasan ini menunjukkan bahwa polemik tidak hanya berisi pertentangan, tetapi juga tawaran jalan tengah.
Ki Hadjar Dewantara dalam artikelnya yang berjudul Pembaruan Adab (hlm. 169), juga tidak serta-merta menolak semangat pembaruan STA. Ki Hadjar Dewantara menekankan bahwa perubahan dalam kebudayaan harus tetap mempertimbangkan nilai-nilai luhur bangsa. Baginya, pembaruan memang diperlukan, bahkan kadang harus bersifat radikal atau revolusioner, tetapi tetap harus dilakukan secara sadar dan bijaksana.
Tokoh-tokoh yang berpolemik dalam Polemik Kebudayaan menyadari bahwa masa depan bangsa tidak bisa dibangun hanya dengan semangat merdeka secara politik, tetapi juga harus merdeka secara kebudayaan. Mereka memperdebatkan dasar nilai, arah pembangunan manusia, serta posisi kebudayaan lokal dalam konstelasi dunia yang terus berubah.
Melalui 19 artikel yang ada dalam buku ini, kita diajak memahami bahwa identitas kebangsaan bukanlah sesuatu yang statis. Ia adalah hasil dari benturan gagasan, percampuran pandangan, dan pergulatan wacana. Polemik Kebudayaan tidak hanya menggambarkan pertikaian intelektual, tetapi juga mencerminkan bagaimana semangat keindonesiaan harus dimaknai serta dijalankan—semangat untuk mencari arah kebudayaan Indonesia, semangat untuk menolak stagnasi, dan semangat untuk menjawab pertanyaan besar tentang “siapa kita sebagai bangsa.”
Identitas Buku
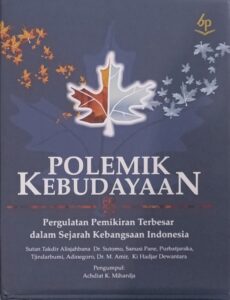
Judul: Polemik Kebudayaan: Pergulatan Pemikiran Terbesar dalam Sejarah Kebangsaan Indonesia
Penulis: Sutan Takdir Alisjahbana (STA), Sanusi Pane, Purbatjaraka, Sutomo, Tjindarbumi, Adinegoro, M. Amir, Ki Hadjar Dewantara
Pengumpul: Ki Hadjar Dewantara
Penerbit: Balai Pustaka
Tanggal terbit: 2008 (cetakan keempat)
Tebal halaman: 223 halaman





















