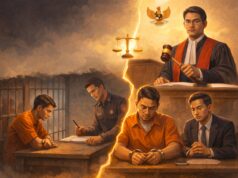Ucapan terima kasih yang mengalir setiap kali seseorang sukses sering kali berhenti di satu nama: guru. Sosok yang disebut-sebut sebagai fondasi segala keberhasilan, inspirasi tanpa henti, dan penggerak perubahan bangsa. Tapi di balik kalimat penuh hormat itu, ada sesuatu yang mengganjal. Pujian demi pujian tumbuh jadi tembok tinggi yang justru menghalangi suara mereka sendiri—suara tentang gaji yang tak cukup, beban kerja yang terus bertambah, dan kebijakan yang datang tanpa pernah melibatkan mereka.
Heroisme guru telah menjadi mitos nasional yang terus direproduksi. Frasa “tanpa tanda jasa” menyimpan ironi yang dalam. Guru diagungkan setinggi langit, sementara kesejahteraan mereka justru nyaris tak terdengar. Narasi ini bukan sekadar penghormatan, melainkan telah berubah menjadi alat pelipur lara bagi kegagalan sistemik yang enggan menyentuh akar persoalan.
Mari sejenak berhenti dari euforia pujian. Lihat bagaimana guru-guru honorer hidup dalam kecemasan tentang gaji yang tak seberapa, status yang tak jelas, dan masa depan yang menggantung. Mereka tidak digaji layak, tidak dilindungi sistem, dan sering kali tak dihargai murid atau orang tua murid. Tapi setiap Hari Guru, suara mereka ditenggelamkan oleh jargon lama yang gemanya terdengar merdu di telinga kekuasaan.
Pahlawan adalah sosok luar biasa yang dianggap melampaui batas manusia biasa. Ketika guru terus ditempatkan di takhta ini, mereka tak diberi ruang untuk salah, kecewa, apalagi marah. Padahal, guru juga manusia. Mereka punya keluarga yang menunggu makan malam. Mereka menabung cemas demi biaya sekolah anak. Mereka membawa tumpukan kertas ujian ke rumah dan melawan kantuk demi menuntaskan koreksi.
Kita jarang bertanya: bagaimana kabar guru hari ini? Bukan sebagai simbol, tapi sebagai manusia. Yang harus memikirkan ongkos ke sekolah, cicilan motor, harga sembako yang melonjak, hingga ancaman burnout karena beban administrasi yang berlebihan. Kita lebih suka menulis puisi tentang pengabdian mereka daripada mendesak sistem untuk berubah.
Desakralisasi frasa “pahlawan tanpa tanda jasa” bukan bentuk penghinaan. Ini adalah upaya menyadarkan publik bahwa guru tidak seharusnya dipuja tanpa diberi perlindungan. Guru tidak butuh puisi jika hak-haknya dicabut perlahan. Mereka tak perlu karangan bunga bila rumahnya digadaikan demi biaya hidup. Mereka layak mendapatkan kompensasi setara dengan beban kerja dan dampak sosial dari profesinya.
Sayangnya, glorifikasi itu menciptakan kebijakan yang abai. Pemerintah merasa cukup memberi panggung dan ucapan selamat setiap tahun. Padahal, yang dibutuhkan guru bukan seremoni. Mereka ingin jaminan kesejahteraan. Mereka ingin pelatihan berkala yang benar-benar relevan. Mereka ingin ruang untuk bersuara tanpa takut dibungkam. Dan mereka ingin jaminan bahwa jerih payah mereka di kelas tidak akan sia-sia di mata kebijakan yang terus berubah-ubah.
Kita juga perlu mengubah cara kita, sebagai masyarakat, memandang profesi guru. Tak sedikit orang tua yang memperlakukan guru anaknya seperti pelayan sekolah, bukan mitra pendidikan. Ada pula siswa yang mengolok-olok guru karena menganggap pekerjaan itu tidak keren. Semua ini tumbuh subur dalam budaya yang menjadikan guru semacam patung suci—harus dihormati, tetapi tidak diselami.
Faktanya, banyak guru yang merasa kesepian dalam sistem yang katanya menjunjung pendidikan. Mereka menulis RPP, mengejar sertifikasi, mengikuti pelatihan daring yang melelahkan, sambil tetap harus hadir penuh energi di kelas setiap pagi. Di sisi lain, sekolah swasta banyak mempekerjakan guru bergaji minim tanpa jaminan, sementara guru negeri tak lepas dari tuntutan administratif yang kadang tidak relevan.
Lebih ironis lagi, ketika guru mencoba bersuara, mereka dianggap tidak bersyukur. Suara-suara kritis kerap dibungkam, dengan dalih menjaga nama baik institusi atau loyalitas pada negara. Padahal, justru dari suara merekalah seharusnya perubahan bermula. Guru tahu persis masalah di lapangan. Tapi suara mereka nyaris tak pernah dijadikan dasar dalam merumuskan kebijakan.
Di tengah tuntutan digitalisasi dan perubahan kurikulum yang cepat, guru sering kali dibiarkan beradaptasi sendiri. Bekerja dari pagi hingga sore, dilanjutkan dengan pelaporan daring, pertemuan wali murid, hingga aktivitas di luar jam kerja. Mereka tidak punya waktu untuk jeda, apalagi untuk bertumbuh secara personal dan profesional. Dan di antara itu semua, mereka tetap dituntut untuk “ikhlas”.
Namun sampai kapan guru harus terus diminta ikhlas, sementara negara dan masyarakat tak kunjung berubah cara memandang dan memperlakukan mereka?
Jika kita terus bertahan pada narasi lama, maka kita sedang memiskinkan makna profesi guru. Mereka tidak butuh didewakan. Mereka butuh didengarkan. Mereka tidak mencari tepuk tangan, mereka mendamba keadilan. Maka, desakralisasi ini justru bentuk penghormatan sejati: memandang guru sebagai manusia utuh yang layak hidup dengan martabat.
Sudah saatnya kita berhenti memberi label mulia tapi tanpa fasilitas. Guru bukan aktor dalam panggung seremoni. Mereka adalah penentu masa depan generasi. Kita bisa mulai dari hal yang konkret: memperjuangkan skema gaji yang adil, memberikan jaminan sosial dan kesehatan, menciptakan ruang aman bagi aspirasi mereka, dan memastikan pelatihan yang benar-benar menjawab kebutuhan lapangan.
Kita tak perlu menunggu Hari Guru untuk mendengar suara mereka. Kita tak perlu menunggu viralnya kisah sedih untuk sadar bahwa sistem pendidikan kita sedang pincang. Dan kita tak boleh menunggu guru menyerah, baru mengulurkan tangan.
Pendidikan tak mungkin maju jika para pengajarnya terus ditinggalkan. Maka, mari kita rawat profesi ini dengan adil, bukan dengan slogan.
Karena sejatinya, guru bukan “pahlawan tanpa tanda jasa”. Mereka adalah pekerja pendidikan yang layak dihargai, dihormati, dan diberdayakan dengan nyata. Bukan hanya oleh kata-kata manis, tapi oleh keberpihakan sistem dan masyarakat yang benar-benar mau mendengar, melihat, dan bergerak—hari ini, bukan nanti.