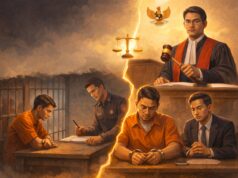Serupa sarana rekreasi, musik kerap dianggap sebagai ruang pelarian atau bahkan penyembuhan. Ia hadir untuk memeluk kesedihan, menumpahkan airmata, memantik tawa, atau sekadar menjadi latar dari kehidupan yang melelahkan. Dalam gambaran umum, panggung musik berdiri sebagai ruang netral, bebas dari beban politik dan moral yang saban hari menyesaki isi kepala dan headline berita online di ponsel mereka.
Tetapi sejarah, sekali lagi, memperlihatkan hal yang sebaliknya. Musik tidak pernah sepenuhnya bersikap netral. Ia bisa menjadi instrumen kekuasaan untuk melanggengkan dominasi, dan bisa pula menjadi medium perlawanan rakyat yang melawan arus atas kondisi sosial yang memprihatinkan. Dan saat ini, pagelaran musik Pestapora 2025 memberi bukti paling mutakhir bahwa panggung hiburan tidak bisa dilepaskan dari tarik-menarik nilai.
Festival musik terbesar di Indonesia itu semestinya menjadi ruang euforia ribuan penonton. Orang-orang datang dengan harapan yang sederhana: menari, bernyanyi, dan sejenak melupakan kerasnya rutinitas. Tetapi suasana berbalik 180 derajat ketika nama PT Freeport Indonesia tiba-tiba muncul sebagai sponsor di antara lalu lalang penonton.
Sebuah spanduk besar dengan tulisan “Tembaga Ikutan Berpestapora” terbentang, lengkap dengan iring-iringan marching band yang berparade seolah tambang emas terbesar itu hanya sekadar bagian dari pesta. Sejak saat itu, suasana terasa hening, hilang kata, dan panggung Pestapora kehilangan klaim netralitasnya. Musik tiba-tiba harus berhadapan dengan kenyataan yang jauh lebih rumit dari yang dibayangkan.
Bagi sebagian penonton, logo sponsor mungkin hanya dekorasi dan identitas usaha. Tetapi bagi musisi, kehadiran korporasi ekstraktif di balik panggung adalah soal legitimasi. Dengan tetap tampil, sebagian dari mereka sadar telah menjadi bagian dari
“pencucian” dosa ekologis dan sosial sebuah korporasi.
Freeport tidak datang tanpa rekam sejarah. Di Papua, perusahaan ini meninggalkan perjalanan panjang soal perampasan tanah adat, pencemaran lingkungan, hingga konflik horizontal yang menelan banyak korban. Membiarkan korporasi itu bersolek di pagelaran musik berarti ikut serta dalam mengaburkan kenyataan pahit masyarakat di tanah yang jauh dari sorak sorai festival yang terselenggara.
Maka tak heran apabila sejumlah musisi memutuskan untuk bersikap mundur. Seperti halnya band Hindia dan Feast menyebut diri mereka “patah hati dan marah” ketika mengumumkan pembatalan. Banda Neira, Leipzig, Sukatani, Rebellion Rose, dan beberapa nama besar lain ikut menyusul.
Keputusan dan sikap berani itu tentu tidak hadir tanpa resiko. Kehilangan honorarium, meruntuhkan jadwal yang telah disusun, bahkan kekecewaan dari penggemar yang telah menunggu berbulan-bulan. Tetapi dalam pandangan mereka, mundur adalah cara paling jujur menjaga integritas.
Kita mungkin bertanya, mengapa musisi harus menanggung beban sebesar itu? Bukankah tugas mereka hanya menghibur? Pertanyaan ini tampak masuk akal tetapi sesungguhnya naif. Musik sejak lama punya sejarah keberpihakan. Dari Woodstock yang menolak perang Vietnam, konser Rock Against Apartheid yang menentang diskriminasi rasial di Afrika Selatan, hingga gerakan global dengan slogan “No Music on a Dead Planet” yang menyatukan musisi untuk isu lingkungan.
Semua contoh ini memperlihatkan bahwa musik adalah bagian dari politik kebudayaan. Seni, dalam hal ini musik, tidak pernah lahir di ruang hampa. Ia selalu membawa jejak realitas sosial yang membentuknya.
Pihak Pestapora akhirnya memutus kontrak kerja sama dengan Freeport sehari setelah gelombang protes mencuat. Mereka bahkan mengakui kelalaian dalam membuka ruang bagi sponsor tanpa mempertimbangkan kajian, sebuah sikap yang patut dihormati. Mengakui kesalahan di ruang publik memang tidak mudah, terlebih dalam skala festival sebesar Pestapora.
Tetapi pengakuan itu bisa menjadi titik balik yang penting dan sebuah pengingat bahwa dunia hiburan harus lebih hati-hati dalam memilih siapa yang hendak dilibatkan. Semoga kesalahan serupa tidak lagi terulang dalam event-event mendatang, agar panggung musik tetap bisa berdiri tanpa bayang-bayang legitimasi korporasi yang merusak lingkungan.
Namun keputusan itu tidak cukup untuk mengembalikan sejumlah musisi kembali ke depan panggung acara. Sikap perlawanan muncul dalam berbagai bentuk. Rapper Yacko tetap tampil tetapi mendonasikan seluruh honornya ke WALHI. The Panturas menyalurkan hasil penjualan merchandise untuk gerakan lingkungan. Rebellion Rose bahkan memilih menggelar gigs akustik di luar arena resmi festival.
Fenomena ini mengajarkan dua hal penting. Pertama, bahwa sikap dan keberpihakan adalah identitas yang tidak bisa ditukar-tambahkan. Musisi seperti Navicula dan Efek Rumah Kaca sudah lama membuktikan bahwa konsistensi sikap bisa menjadi fondasi yang lebih kokoh daripada sekadar popularitas. Kini, semakin banyak musisi arus utama yang berani menapaki jalan serupa. Ada kesadaran baru bahwa popularitas tanpa integritas hanya akan melahirkan kekosongan.
Kedua, bahwa publik kini lebih kritis. Penonton tidak lagi hanya memikirkan line up band, tetapi juga mempertanyakan siapa sponsor di balik festival. Etika dan transparansi kini menjadi bagian tak terpisahkan dari ekosistem musik.
Pendanaan sponsor mungkin bisa membiayai panggung megah, tetapi tidak lagi bisa menyembunyikan jejak buruk yang sudah terlanjur diketahui publik. Dengan kata lain, penyelenggara festival harus beradaptasi dengan kenyataan baru bahwa hiburan tidak bisa lagi dipisahkan dari isu keberlanjutan.
Isu ini menjadi semakin relevan ketika kita bicara soal krisis iklim. Indonesia bukan sekadar menghadapi ancaman, tetapi sudah hidup di dalamnya. Banjir bandang, kekeringan, kebakaran hutan, hingga kenaikan permukaan laut menjadi bagian dari keseharian di banyak daerah.
Aktivitas korporasi ekstraktif adalah bagian dari struktur besar yang mempercepat krisis tersebut. Dalam situasi ini, panggung musik bukan lagi sekadar ruang hiburan. Ia bisa menjadi corong perlawanan, ruang artikulasi yang lebih nyaring dari dentuman speaker mana pun.
Pestapora 2025 memperlihatkan bagaimana sebuah festival musik berubah menjadi arena tarik menarik nilai. Ada musisi yang memilih diam dan tetap tampil, ada yang berteriak dengan mundur. Ada yang mencari jalan tengah dengan mengalihkan honorarium.
Keputusan mundur dari panggung Pestapora juga membuka ruang dialog yang lebih luas. Musik tidak bisa hanya dilihat sebagai komoditas hiburan. Ia adalah bahasa emosional yang mampu menggerakkan massa, menumbuhkan solidaritas, atau melahirkan kemarahan kolektif. Ketika musisi menolak tampil, mereka sedang mengingatkan bahwa ada hal yang lebih besar dari sekadar sorak penonton yakni tanggung jawab moral untuk berpihak pada kehidupan.
Keberanian itu akan berdiri sejajar dengan sejarah panjang musik sebagai medium perlawanan. Dari panggung kecil hingga festival raksasa, dari gigs sederhana hingga konser internasional, selalu ada jejak bahwa musik bisa menjadi bagian dari perjuangan sosial. Musik memang tidak pernah ada di ruang netral. Ia adalah bagian dari pertarungan nilai. Pestapora 2025 menjadi pengingat bahwa panggung musik tidak bisa dilepaskan dari realitas sosial-politik yang melingkupinya.