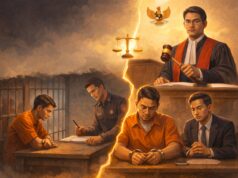Nasionalisme bukanlah sesuatu yang asing bagi bangsa ini, terutama di bulan Agustus ketika rakyat Indonesia merayakan kemerdekaan. Semangat yang melahirkan Republik Indonesia berakar pada nasionalisme yang menyala di dada rakyat saat menghadapi penjajahan. Nasionalisme menjadi pemersatu perjuangan untuk meruntuhkan belenggu kolonialisme dan menegakkan harga diri bangsa.
Namun, di era disrupsi saat ini, nasionalisme kerap direduksi menjadi sekadar seremoni: pengibaran bendera, lomba tujuh belasan, atau jargon cinta tanah air yang berhenti di permukaan. Padahal, Sukarno pernah mengingatkan bahwa nasionalisme sejati bukanlah chauvinisme sempit, melainkan kesadaran kolektif untuk membebaskan manusia dari penindasan, serta mengelola alam demi kesejahteraan rakyat.
Gagasan itu ia tuangkan dengan tegas dalam buku Di Bawah Bendera Revolusi melalui konsep Sosio-Nasionalisme. Bagi Sukarno, “sosio” berarti masyarakat; maka sosio-nasionalisme adalah nasionalisme-masyarakat. Nasionalisme ini tidak lahir dari sekadar romantika kosong, melainkan dari kenyataan pahit dalam kehidupan rakyat. Sosio-nasionalisme, kata Sukarno, bukanlah nasionalisme “ngalamun” atau “melayang”, melainkan nasionalisme yang menjejak kuat di bumi masyarakat, dengan tujuan memperbaiki keadaan agar tidak ada kaum yang tertindas dan sengsara.
Gagasan nasionalisme Sukarno tidak lahir dalam ruang hampa. Ia banyak dipengaruhi oleh pemikiran Ernest Renan dan Otto Bauer. Renan melihat bangsa sebagai sebuah jiwa, sebuah asas yang berdiri di atas dua hal: pertama, rakyat memiliki sejarah bersama; kedua, rakyat memiliki kehendak untuk hidup sebagai satu kesatuan. Otto Bauer menambahkan, bangsa terbentuk dari persatuan perangai yang lahir dari pengalaman hidup bersama suatu rakyat. Namun, bagi Sukarno, kedua pandangan itu masih kurang lengkap. Dalam pidato 1 Juni 1945 ia menegaskan: Renan dan Bauer hanya menekankan sisi manusia—jiwa, perasaan, dan pengalaman bersama—tanpa mengingat tanah tempat manusia berpijak. Padahal, menurut Sukarno, tanah air adalah bagian tak terpisahkan dari bangsa. Manusia dan tanah air adalah satu kesatuan.
Namun, gagasan Sukarno tentang nasionalisme tidak bisa berhenti sebagai romantisisme sejarah. Ia perlu diuji di hadapan tantangan zaman sekarang. Dunia pasca kolonial ternyata tidak bebas dari bentuk penjajahan baru. Kapitalisme global menjerat ekonomi Indonesia melalui ketergantungan investasi dan dominasi modal asing di sektor-sektor strategis; digitalisasi menjadikan nasionalisme sekadar slogan yang diproduksi algoritma dan diperdagangkan lewat politik pencitraan; sementara tanah air yang dahulu menjadi inti pemikiran Sukarno justru kian terkoyak oleh deforestasi, pertambangan, dan krisis iklim. Pernyataan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia, yang menyebut bahwa membabat hutan demi pembangunan nasional “tidak masalah”, menunjukkan dengan gamblang bagaimana alam dikorbankan atas nama pembangunan. Dalam situasi seperti ini, nasionalisme sejati bukanlah upacara simbolis, melainkan keberanian melawan kapitalisme lokal dan global, serta membela bumi Indonesia dari kehancuran ekologis. Dalam kerangka pemikiran Sukarno, merusak lingkungan berarti menghancurkan manusianya; dan bila manusianya hancur, maka nasionalisme pun akan runtuh. Bagaimana mungkin membicarakan masyarakat tanpa membicarakan alamnya?
Maka itu, nasionalisme hari ini harus dibaca ulang bukan sekadar sebagai ingatan pada masa lalu sehingga hanya sebatas romantisir, melainkan sebagai orientasi praksis menghadapi tantangan baru. Nasionalisme tidak cukup diwujudkan dalam seremoni kenegaraan, melainkan dalam keberpihakan konkret pada rakyat, kedaulatan ekonomi, dan kelestarian lingkungan. Sukarno menekankan bahwa nasionalisme sejati lahir dari rahim rakyat dan berpijak pada tanah air. Di era digital yang sarat manipulasi algoritma serta di tengah krisis iklim yang kian nyata, tugas kita adalah menghidupkan kembali roh nasionalisme itu: menjadikannya daya kritis yang membebaskan, bukan sekadar retorika yang meninabobokan—seperti jargon “kita ini bangsa besar“.
Menghidupkan nasionalisme seperti gagasan Sukarno saat ini bisa kita lakukan dengan cara paling sederhana, yaitu dengan mulai peduli terhadap orang-orang terdekat terutama dengan mereka yang sangat membutuhkan serta menjaga lingkungan dengan tidak membuang sampah sembarangan. Tindakan kecil ini mungkin tampak sepele, bahkan tidak bersifat makro, tetapi di tengah zaman yang serba individualistik, keterasingan dari alam, dan ilusi seremoni buatan penguasa, ia menjadi sebuah antitesis. Dari hal-hal kecil itulah empati terhadap sesama dan kepedulian terhadap lingkungan dapat tumbuh, dan perlahan menghidupkan kembali nasionalisme sebagai praksis sehari-hari, bukan sekadar slogan.
Ketika rasa empati tumbuh maka kesadaran kolektif tentang nasionalisme yang berjiwa kemanusiaan akan tumbuh karena nasionalisme sejati tidak berhenti hanya pada individu. Kesadaran kolektif akan mampu mengubah sistem politik, ekonomi dan sosial. Di politik tak lagi basisnya individualistik dan elektoral semata namun politik yang berlandaskan kepentingan kaum tertindas agar menghapuskan ketertindasan. Dibidang ekonomi tak lagi mengedepankan kapital diatas segalanya namun manusianya merupakan segalanya. Semangat ekonomi koperasi sebagai soko guru tak lagi menjadi jargon namun menjadi dasar perekonomian negara. Dibidang sosial, semangat gotong royong kian tumbuh kembali, baik di masyarakat kota maupun desa.
Namun sayangnya, nasionalisme hari ini lebih sering dimaknai secara seremonial dan simbolik. Ia dipertontonkan melalui pesta-pesta kekuasaan, jargon kosong, serta panggung politik elektoral yang justru menjauhkan rakyat dari esensi kebangsaan. Padahal, seperti yang pernah ditegaskan Sukarno, nasionalisme tanpa keberpihakan pada kaum tertindas hanyalah ilusi. Nasionalisme sejati menuntut keberanian untuk melawan ketidakadilan, menegakkan kedaulatan rakyat di atas modal, dan menumbuhkan solidaritas yang hidup di tengah masyarakat. Pertanyaannya kini, apakah kita rela membiarkan nasionalisme dikebiri menjadi sekadar tontonan penguasa, atau berani menjadikannya praksis sehari-hari yang berpihak pada kemanusiaan?