Pernahkah kita menyadari, betapa sistem pendidikan di Indonesia kerap menuntut keseragaman dan memaknai kedisiplinan kaku? Totto-chan: Gadis Cilik di Jendela hadir sebagai cermin yang memantulkan ironi tersebut.
Novel yang terbit pertama kali pada 1981 ini merupakan memoar masa kecil sang penulis, Tetsuko Kuroyanagi. Dengan sentuhan jenaka, Kuroyanagi mengajak pembaca menyusuri dunia dari mata seorang anak kecil yang polos, lugu, dan penuh rasa ingin tahu.
Ada tiga unsur yang menjadikan cerita dalam novel ini begitu memikat: tingkah lugu Totto-chan, dedikasi Sosaku Kobayashi, dan atmosfer pembelajaran di Tomoe Gakuen. Ketiganya tidak hanya berkelindan, tapi juga saling melengkapi, mengantarkan kita pada permenungan untuk melihat pendidikan dari perspektif yang lebih inklusif.
Kisahnya dimulai ketika gadis kecil bernama Totto-chan dikeluarkan dari sekolah lamanya karena alasan sederhana: rasa ingin tahunya yang berlebih dianggap mengganggu orang-orang sekitarnya. Musabab itulah, Totto dipindahkan ke sekolah baru, yang membuka babak penuh kejutan.
Kepindahan itu membawa Totto-chan pada sebuah sekolah unik bernama Tomoe Gakuen. Berbeda dari sekolah pada umumnya, alih-alih dibangun dengan desain megah dan dilengkapi pilar kokoh, Tomoe Gakuen berdiri di atas gerbong-gerbong kereta bekas yang disulap menjadi ruang kelas dan perpustakaan.
Adalah Sosaku Kobayashi, sosok visioner yang mengepalai sekolah gerbong kereta tersebut. Dengan pendekatan yang hangat sekaligus berani menentang pakem konvensional, ia berhasil menciptakan ruang belajar yang menaruh hormat pada keunikan setiap anak. Sekolah bukan lagi soal menghafal dan menuruti aturan yang kaku, melainkan tentang ketulusan untuk membentuk pribadi yang percaya diri, berempati, dan mampu merayakan kebebasan berpikir.
Karena itulah, Totto-chan yang pernah dianggap “nakal” dan dikeluarkan dari sekolah lamanya justru merasa diterima sepenuhnya di Tomoe Gakuen. Di sana ia bisa belajar secara leluasa dan tumbuh dengan rasa ingin tahu yang terjaga.
Pembelajaran Ala Kobayashi
Selain gaya arsitekturnya yang eksentrik, ekosistem pembelajaran di Tomoe Gakuen tak kalah unik. Ketika kelas dimulai, para siswa dibiarkan melakukan kegiatan yang mereka sukai. Ada yang menggambar, ada yang menjetikkan jemarinya di atas papan piano, ada yang bermain-main dengan krayon dan kanvas, bahkan ada pula yang melakukan eksperimen sains. Semuanya dilakukan dengan bebas sesuai minat masing-masing.
Suasana kelas dibangun begitu menyenangkan. Tak ada kursi tetap, siswa dibebaskan duduk di mana saja. Mereka juga diajak berkenalan dengan literasi melalui gerbong khusus yang difungsikan sebagai perpustakaan. Lalu ketika jam makan siang, para siswa diminta membawa bekal berisi “sesuatu dari laut dan sesuatu dari pegunungan”. Aturan sederhana ini menanamkan kesadaran anak-anak akan pentingnya menjaga keseimbangan gizi, sekaligus mengingatkan bahwa kedua ekosistem itu memiliki peran krusial dalam menyokong kehidupan manusia.
Pembelajaran pun tidak hanya berlangsung di dalam kelas. Siswa diajak berenang bersama, berjalan-jalan ke alam, hingga belajar berkebun dengan petaninya langsung. Ini memberikan mereka pengalaman langsung dengan dunia sekitar, memungkinkan ilmu pengetahuan terhubung dengan realitas sehari-hari.
Kobayashi juga menekankan betapa pentingnya membangkitkan kepekaan anak-anak, salah satunya melalui musik. Ada berbagai macam pelajaran musik di Tomoe Gakuen, termasuk pelajaran euritmik setiap hari. Menurut Kobayashi, euritmik akan membantu anak mengembangkan kepribadian mereka secara alamiah, kepribadian yang indah, selaras dengan alam, dan mematuhi hukum-hukumnya.
Tampaknya, Kobayashi memang sengaja merancang sedemikian rupa sistem semacam ini untuk menjaga keriangan anak. Ia percaya, bahwa keriangan itu muncul sebagai fondasi dalam membentuk kreativitas dan fleksibilitas kognitif individu.
Tak heran jika Kepala Sekolah Tomoe itu pernah berpesan, “serahkan mereka pada alam. Jangan patahkan ambisi mereka. Cita-cita mereka lebih tinggi daripada cita-cita kalian.” Sebab baginya, yang terpenting dari pendidikan dasar adalah menjaga keingintahuan anak tetap menyala. Karena tanpa itu, Kobayashi khawatir akan lahir generasi yang punya mata, tapi tidak melihat keindahan; punya telinga, tapi tidak mendengar musik; punya pikiran, tapi tidak memahami kebenaran; punya hati, tapi tidak tergerak.
Sebuah Resonansi
Jika dicermati, praktik pendidikan yang diterapkan Sosaku Kobayashi, kendati berbeda secara teritori, memiliki frekuensi yang seirama dengan konsep pendidikan yang digaungkan oleh Bapak Pendidikan kita, Ki Hajar Dewantara.
Misalnya, keyakinan Kobayashi bahwa setiap anak lahir dengan watak baik yang harus dipelihara, selaras dengan pandangan Ki Hajar Dewantara: anak sebagai ciptaan kodrati dengan keunikannya masing-masing. Keduanya menolak homogenisasi, sekaligus menegaskan bahwa manusia merupakan makhluk yang secara fundamental kreatif, terus mencari, dan menyempurnakan diri.
Dalam hal pembelajaran, Kobayashi membiarkan siswa untuk mempelajari apa pun yang menarik minat mereka. Guru hadir sebagai pendamping, bukan penguasa kelas, memastikan siswa memahami apa yang dipelajari. Prinsip ini beresonansi dengan sistem among ala Ki Hajar Dewantara. Sistem among memberikan kebebasan kepada siswa, sementara guru hanya bertugas mengawasi dan menuntun. Guru tidak boleh menjadi mesin pengajar, melainkan fasilitator yang membuka ruang eksplorasi siswa.
Tamsil lainnya juga terlihat dalam cara keduanya memaknai sekolah. Kobayashi menjadikan lingkungan sekitar sebagai sumber belajar (sekolah). Susana belajar dibangun begitu alamiah, sehingga memungkinkan siswa untuk menggali informasi sesuai dengan rasa ingin tahunya.
Ki Hajar pun menekankan hal serupa. Baginya, sekolah adalah ruang di mana anak dapat tumbuh secara alami, bebas dari penyeragaman yang membunuh kreativitas. Karena itu, Ki Hajar mendefinisikan sekolah sebagai “taman”, sebab sifatnya bebas, alami, dan menggembirakan. Ia memiliki batas, tapi tidak membatasi. Memiliki ruang, tapi tidak mengurung.
Dalam jalinan ini, baik Kobayashi maupun Ki Hajar, keduanya sama-sama mementingkan kebebasan belajar dan menjadikan sekolah sebagai ruang pertumbuhan yang alami. Kesamaan ini mengantarkan pada sebuah resonansi, bahwa pendidikan sesungguhnya yakni yang membebaskan, bersedia mewadahi multipotensi setiap siswa, serta memungkinkan individu tumbuh sesuai dengan distingtifikasinya masing-masing.
Refleksi terhadap Pendidikan Kita
Pendidikan, seperti yang ditegaskan Paulo Freire, semestinya menjadi arena pembebasan manusia. Ada dua fungsi pendidikan secara umum. Pertama, memosisikan manusia sebagai subjek bukan objek, sehingga mengantarkan kepada penemuan dirinya sendiri. Kedua, membebaskan manusia dari kungkungan penindasan sosial, kultural, dan politik.
Namun pertanyaannya, sejauh mana pendidikan kita benar-benar mengimplementasikan cita-cita itu? Bila kita melongok ke praktik pendidikan dasar di Indonesia hari ini, ironinya amat dalam. Kultur pendidikan kita lebih menghargai keseragaman ketimbang keragaman.
Amsal, bila ada seorang siswa yang lebih menekuni seni ketimbang matematika, secara konstan akan mendapat stempel “kurang berprestasi” karena nilai eksaknya rendah. Begitu pun sebaliknya. Atau kalau ada siswa yang kritis, berani menyanggah, dan suka menentang argumen guru, segera dilabeli sebagai pembangkang karena dianggap tidak sopan.
Kurikulum Merdeka yang belakangan dielu-elukan pun hanya berhenti pada prototipe administratif belaka. Pada konsepnya, ia menjanjikan fleksibilitas dan kebebasan belajar. Tapi pada implementasinya, siswa tetap terikat pada asesmen seragam, ujian standar, dan target pencapaian numerik. Guru pun masih sering terjebak dalam tumpukan administrasi. Substansi pembelajaran kerap dikesampingkan, selama berkas terjilid dan terlapor dengan baik, maka semuanya aman.
Padahal, sekolah idealnya menjadi ruang eksplorasi, bukan ladang penyeragaman. Siswa perlu diberi spasi untuk mengenali dirinya sendiri, tanpa harus terbebani oleh kurikulum yang mengekang. Tugas guru hanyalah mengamati ke mana kecenderungan itu mengarah, lalu membimbingnya menjadi lebih terarah.
Dengan begitu, barulah spirit “ing ngarsa sung tuladha, ing madya mangun karsa, tut wuri handayani” yang digelorakan Ki Hajar Dewantara bisa hidup nyata dalam praktik, bukan berhenti sebagai slogan dekoratif di dinding sekolah. Seperti yang ditegaskan Kobayashi, “tujuan pendidikan adalah untuk menemukan ‘watak baik’ dalam diri setiap anak dan mengembangkannya, agar mereka tumbuh menjadi orang dewasa dengan kepribadian yang khas.”*
Identitas Buku
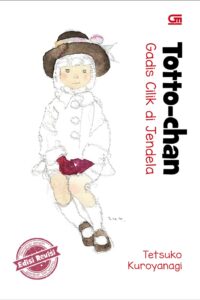
Judul : Totto-chan, Gadis Cilik di Jendela
Penulis : Tetsuko Kuroyanagi
Penerbit : Gramedia Pustaka Utama
Tahun terbit : 2019
Jumlah halaman : 269 halaman
ISBN : 978-602-06-3601-6





















