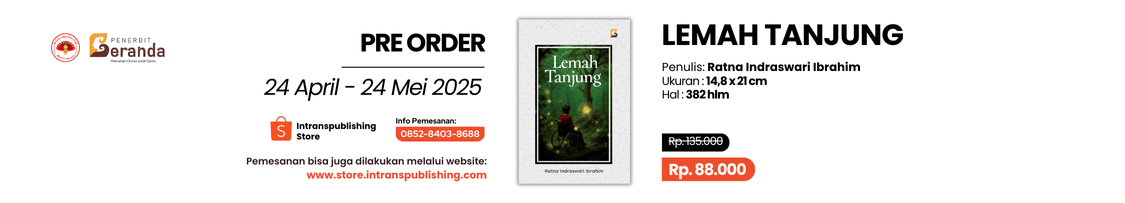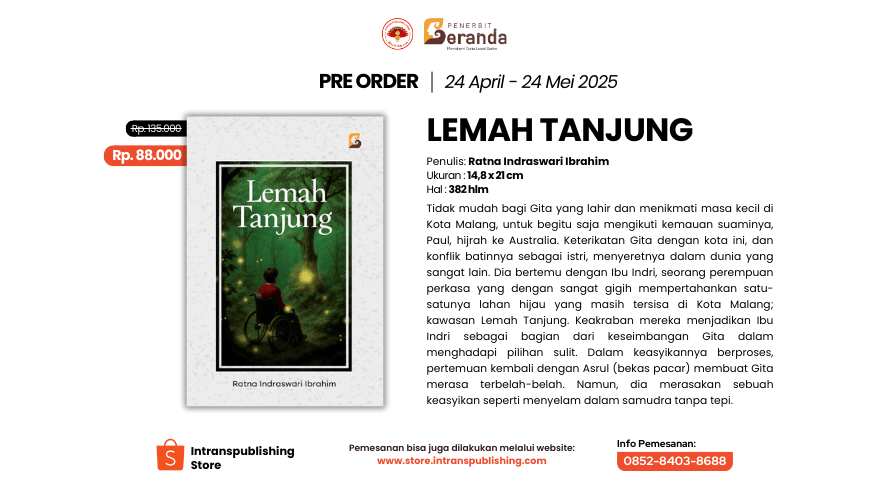Utuh Merdeka!
Bung Hatta pernah berucap, “Indonesia merdeka bukan tujuan akhir kita. Indonesia merdeka hanya syarat untuk bisa mencapai kebahagiaan dan kemakmuran rakyat.”
Ungkapan penting yang relevan sampai hari ini di saat bangsa kita masih tertatih mewujudkan kebahagiaan dan kemakmuran rakyat “yang berkeadilan”, kendati sudah merengkuh kemerdekaan 80 tahun lamanya. Penanda bahwa kemerdekaan sejati −dalam konsepsi Bung Karno: merdeka politik, ekonomi, dan budaya− tidak pernah paripurna, tapi perlu terus diusahakan untuk mendekatinya. Bagai “jembatan emas,” kata Bung Karno, merdeka politik hanya sebagai pintu penghubung memasuki medan perjuangan sesungguhnya. Sebab itu, kata “merdeka” selalu relevan dibahas, digugat, lalu dikerjakan.
Jauh setelah merdeka secara politik pada 17 Agustus 1945, di era kini pun refleksi sekaligus gugatan terhadap kemederkaan, diperlukan sangat. Demi menguji, apakah jalan kita selaras cita-cita bangsa atau justru melenceng dari “tangga harapan”. Dengan begitu kita terus memurnikan nawaitu perjuangan. Mengingat perjuangan meraih merdeka bukanlah suatu yang gampang; banyak kelihangan yang diderita dan dikorbankan. Harga yang harus dibayar demi sebuah kemerdekaan bahkan lebih hebat dari narasi-narasi mainstream dalam buku-buku dan film-film sejarah.
Tentu kita tidak meragukan kadar perjuangan para pelopor republik: Tirtho Adhi Soerjo, Kartini, Tan Malaka, Agus Salim, Ki Hadjar Dewantara, Bung Karno, Bung Hatta, M. Yamin, Sjahrir, dan rekan-rekan sezamannya. Mereka ialah orang-orang terpelajar yang punya kesempatan sekolah khusus bagi kalangan priyayi. Intelektualitas itulah yang membuat mereka percaya diri melawan penjajah dan kemudian dikenang karena gagasan-gagasan dan jalan perjuangan mereka dicatat dan tercatat dalam buku. Literatur itu yang kita konsumsi hingga saat ini. Tak ada yang salah dengan jalan itu selagi ilmu yang diperoleh digunakan sebaik-baiknya demi meraih kemedekaan.
Hanya, ingat! Banyak perlawanan dari masyarakat biasa yang tidak tercatat dalam sejarah. Perjuangan menentang penjajahan secara kolektif demi satu tujuan: merdeka! Narasi perlawanan dari keluarga biasa, dari kampung, sama berharganya dikemukakan untuk menegaskan bahwa terbentuknya bangsa kita ini adalah impian utuh dari semua kalangan dari setiap penjuru; bukan sebatas kehendak elite politik yang diisi priyayi dan militer saja.
Penghapusan dan Pencarian
Kita perlu melacak kembali arsip-arsip sejarah yang tersisa, walau tidak banyak, yang menceritakan sejarah secara adil.
Film Turang bisa jadi satu contoh. Film karya sutradara Bachtiar Siagian ini menawarkan perspektif berbeda dalam sejarah revolusi Indonesia: merekam perjuangan warga dan sekelompok tantara di Tahah Karo, di bawah kaki gunung Sinabung, Sumatera Utara, pada masa Agresi Militer Belanda.
Film Turang diproduksi pada 1957 dan diputar pertama kali di Istana Negara bersama Presiden Sukarno pada 1960, film Turang naik daun. Film ini mendapat predikat film terbaik dalam Pekan Apreasiasi Film Nasional, sebelum menjadi Festival Film Indonesia (FFI), dan sebelumnya juga menjadi primadona dalam Festival Film Asia Afrika pertama pada 1958 yang digelar di Tashkent, Uzbekistan. “The most celebrated picture at Tashkent,” begitu akademisi dari Concordia University Montreal, Elena Razlogova, menulis dalam papernya menggambarkan film Turang.
Kendati memenangkan film terbaik dan diakui di dunia internasional, namun film Turang sempat hilang bersama dengan film-film karya sutradara ‘kiri’, termasuk karya-karya Bachtiar Siagian. Ini tidak terlpas dari peristiwa 1965, di bawah rezim militer Soharto, upaya penghilangan jejak sejarah yang berkaitan dengan gerakan ‘kiri’, jelasnya Partai Komunis Indonesia dan afiliasinya, masif terjadi.
Mereka yang dianggap terlibat atau bersinggungan dengan PKI, dibunuh dan ditangkap, termasuk anggota lembaga seni yang dinilai dekat dan menjadi bagian dari PKI yakni Lembaga Kebudayaan Rakyat (Lekra). Karena dianggap bagian dari Lekra, Bachtiar Siagian ditangkap dan mendekap di pengasingan Pulau Buru selama 12 tahun. Tak hanya para pencipta seni yang bernaung di Lekra, karyanya pun turut dihabisi. Itulah mengapa banyak arsip film tanah air menghilang, di samping karena buruknya sistem pendokumentasian film.
Setelah lama hilang, pada 2025 film Turang kembali ditemukan. Ialah putri sang sutradara film Turang, Bunga Siagian, yang giat melacak arsip film-film ayahnya. Di tanah air sendiri, jejak film Turang sudah hilang. Untungnya, film Turang pernah ikut dalam Festival Film Asia Afrika, ada kemungkinan arsipnya masih tersimpan.
Kesempatan itu menghampiri saat Bunga Siagian menghadiri pameran seni kontemporer internasional Documenta di Kota Kassel, Jerman. Bunga bertemu dengan seniman video dari Tashkent dan meminta bantuannya untuk mencari film Turang. Setelah ditelusuri, ada satu arsip film berjudul Turang yang ditemukan di arsip film Rusia Gosfilmofond, Moskow. Benar saja, itu film Turang yang masih utuh. Tepat pada Februari 2025, Turang bisa kembali meraung.
Raungan Turang
Di antara reruntuhan arsip perfilman Indonesia, Turang muncul kembali, menegaskan sejarah yang nyaris dilupakan.
Karya sineas kiri Bachtiar Siagian ini menampilkan perjuangan kolektif melawan Belanda, memotret secara otentik: republik yang dibangun tidak semata dari peluru militer dan diplomasi kaum terpelajar, tetapi juga oleh tangan-tangan warga biasa, yang punya semangat membara demi merengkuh kemerdekaan.
Turang, dengan latar komunitas adat Karo dan gaya neorealisnya yang kuat, tidak menyuguhkan pahlawan dalam wujud militer atau priyayi terpelajar, tetapi memilih menunjukkan Tipi—gadis desa yang merawat Rusli, pemimpin laskar yang terluka parah. Tipi dan ayahnya, kepala desa yang hidup di bawah bayang-bayang pendudukan Belanda, menjadi simbol dari bentuk keberanian yang sering kali luput dari ingatan nasional: keberanian rakyat kecil.
Tak ada glorifikasi dalam Turang. Tak ada sorak sorai kemenangan tentara, karena justru mereka gugur di penghujung cerita. Desa dihujani bom dan peluru, ayah Tipi ditangkap karena menolong, dan Rusli serta Tipi tak luput dari takdir tragis. Namun di balik kekalahan itu, Turang memekikkan pesan bahwa perjuangan tidak hanya hidup di medan tempur, tapi juga di ladang-ladang kecil, di pelipir dapur, dan di hati warga yang rindu merdeka.
Film ini, sebagaimana diulas oleh pengamat film Hafiz dan Bunga Siagian, tidak memusuhi pemerintah, namun juga tidak menempatkan tentara sebagai pusat segalanya. Alih-alih membangun mitologi militeristik, Turang justru membongkar ilusi heroisme tunggal, dan menghadirkan kehidupan sehari-hari sebagai medan juang yang setara pentingnya. Dari kebun yang digarap bersama, nyanyian yang bergema di sela malam mencekam, hingga gestur-gestur kecil antara Tipi dan Rusli, film ini memperlihatkan bahwa cinta, kerja, dan solidaritas adalah bentuk lain dari perjuangan.
Dalam dunia yang kerap melupakan suara rakyat biasa, Turang menjadi arsip penting, semacam saksi bisu bahwa republik ini dibangun dari keringat mereka yang tak tercatat dalam buku sejarah. Sebagaimana diingatkan oleh Bung Hatta, “Janganlah pemimpin itu terlalu didewa-dewakan dab janganlah kita menggantungkan nasib pergerakan kepada salah seorang pemimpin.
Tidak puas kita memperingatkan, pergerakan tidak boleh tinggal pergerakan pemimpin saja, yang hilang timbul adanya pemipin itu, melainkan haruslah pergerakan rakyat.” Turang meneguhkan peringatan itu. Ia mengingatkan bahwa kemerdekaan bukan hadiah dari elite nasionalis atau hasil strategi jenderal belaka, tapi buah dari kerja kolektif rakyat yang mengangkat cangkul dan berani menyembunyikan pejuang dengan nyawa sebagai taruhannya.
Sejarah memang cenderung menulis tentang yang besar dan berseragam, tapi Turang menyisipkan kisah sehari-hari. Seperti halnya kisah yang tercatat dalam buku Pemberontakan Petani Banten 1888, yang secara adil menampilkan sejarah perjuangan, di mana petani, pemuka agama, saudagar, secara bersama melawan ketidakadilan.
Kini, ketika Turang kembali disuarakan, selain menawarkan nostalgia sinematik, juga mengajak kita meninjau ulang siapa yang layak disebut pahlawan. Menuntut agar sejarah tidak hanya memuliakan kaum priyayi, tetapi juga rakyat yang senasib sepenanggungan. Turang kembali meraung, bukan sebagai ratapan, melainkan pekik dari rakyat yang tak pernah berhenti memperjuangkan makna sejati dari kemerdekaan.
Saya meyakini bahwa ada banyak kisah perlawanan dari masyarakat biasa di berbagai penjuru tanah air. Narasi itu perlu dikampanyekan lewat berbagai instrumen seperti film dan tulisan. Dengan begitu sejarah bangsa tidak sebatas sejarah kaum priyayi dan militer saja, tetapi utuh memuat peristiwa sejarah yang juga hadir dari warga biasa. Keduanya satu kesatuan yang berlandaskan rasa senasib sepenanggungan sebagai bangsa yang lama terjajah.
Tujuannya satu: Merdeka. Sebagaimana dituliskan oleh Sartono Kartodirjo dalam buku Pemberontakan Petani Banten 1888, yang menceritakan kronologi pemberontakan petani di Banten. Perjuangan kolektif oleh petani, pemuka agama, dan saudagar ditampilkan setara dan mempunyai peran masing-masing.
Dengan melihat sejarah secara jernih, kita dapat memaknai kehidupan berbangsa secara utuh. Laksana ungkapan Multatuli, “demi kebenaran dan akal sehat”. Pondasi itu menjadi sumber spirit untuk terus mengusaha cita-cita bersama: merdeka sejati.