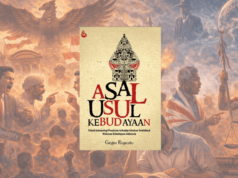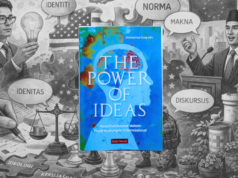Bagaimana sebaiknya kita membaca sejarah sebuah lembaga kebudayaan yang telah dibubarkan, dicap berbahaya, dan dikubur dalam narasi hitam-putih selama puluhan tahun? Dalam buku Komitmen Sosial dalam Sastra dan Seni: Sejarah Lekra 1950–1965, Keith Foulcher mengajak kita menengok ulang Lembaga Kebudayaan Rakyat (Lekra)—organisasi seni yang pernah begitu berpengaruh, begitu dibenci, dan begitu rumit untuk dibicarakan tanpa emosi.
Berbicara mengenai sejarah kebudayaan di Indonesia—terutama di era sebelum ’65—maka nama Lembaga Kebudayaan Rakyat (Lekra) tidak bisa dilepaskan. Lekra adalah sebuah organisasi kebudayaan sayap kiri yang bergerak sekitar tahun 1950-1965. Keith Foulcher dalam karyanya yang berjudul Komitmen Sosial dalam Sastra dan Seni: Sejarah Lekra 1950–1965, mendedahkan sejarah Lekra secara detail dengan terdiri dari tujuh bab. Buku yang diterjemahkan oleh Rima Febriani dan diterbitkan oleh Pustaka Pias pada 2020 ini membahas mulai dari pembentukan sejarah sastra Indonesia, antologi sastra Lekra, hingga interpretasi mengenai Lekra.
Dalam kata pengantar yang berjudul Lekra, Menurut Pihak Ketiga oleh Ariel Heryanto (hlm. xii), besarnya pengaruh Lekra pada masanya tidak hanya diakui oleh tokoh-tokoh Lekra, tetapi juga—secara tidak langsung—diakui oleh mereka yang berseberangan dengan Lekra, bahkan ketika Lekra bubar pasca peristiwa G30S. Hal itu karena pembahasan mengenai Lekra pasca peristiwa G30S diwarnai oleh (sisa-sisa) perasaan dendam dan kebencian oleh mereka yang dulunya berseberangan dengan Lekra. Karena itulah, buku karya Keith Foulcher—sebagai seorang pengamat sastra Indonesia modern—ini menjadi sangat penting karena menyajikan ulasan mengenai Lekra secara lebih objektif dan terbuka.
Lekra dan PKI
Lekra didirikan pada 17 Agustus 1950 melalui Manifesto Lekra 1950. Karena Lekra merupakan sebuah organisasi kebudayaan sayap kiri dengan berpaham realisme sosialis, maka tidak mengherankan jika Lekra dekat dengan Partai Komunis Indonesia (PKI). Kedekatan Lekra dengan PKI terlihat jelas pada komentar ini (hlm. 13):
“Pada tanggal 17 Agustus 1950, Lekra … organisasi budaya PKI … dibentuk, kurang dari dua tahun setelah revolusi komunis kedua dipadamkan di tengah perjuangan kemerdekaan Indonesia (Peristiwa Madiun, 18 September 1948). Mukadimah Lekra tentu saja berdasarkan realisme sosial.”
Selain itu, pada peresmian berdirinya Lekra dengan jarak 10 hari setelah konferensi pada 17 Agustus 1950, ada dua pemimpin PKI—yang baru direformasi pasca Peristiwa Madiun—yaitu D.N. Aidit dan Njoto. Peristiwa tersebutlah yang menjadi awal dari hubungan antara Lekra dan PKI. Pada peresmian berdirinya Lekra itu pula, pemikiran Marxis secara terang-terangan digunakan sebagai kerangka untuk menjelaskan pandangan nasionalis dan antiimperialis (hlm. 25).
Kedekatan Lekra dan PKI semakin terlihat pada konferensi pertama Lembaga Sastra (Lestra) yang berlangsung di Medan pada Maret 1963. Pada konferensi tersebut, D.N. Aidit tampil dan berpidato dengan judul “Sastrawan-sastrawan kita harus bersatu-hati dan bersatu-tekad dengan massa Rakyat”. Pada pidato itu, D.N. Aidit menekankan implementasi penuh prinsip “Turun ke Bawah” serta integrasi para penulis dengan kelas-kelas revolusioner yang menjadi tujuan karya mereka (hlm. 125).
D.N. Aidit juga berpendapat bahwa karya sastra harus diarahkan kepada kader partai, siapa target pembacanya, serta bagaimana penulis belajar tentang kehidupan dan perjuangan rakyat biasa. Pada tingkat nasional, karya sastra harus berperan dalam “mengisolasi kekuatan reaksioner, memperkuat kesatuan nasional, dan mengkonsolidasi kekuatan progresif”. Untuk itu, penulis harus bisa menentukan dengan jelas mana musuh dan sekutu Rakyat dalam tulisan-tulisannya, dan tentunya mengetahui serta memahami Rakyat itu sendiri (hlm. 126).
Mereka yang Berseberangan dengan Lekra
Pada awal tahun 1960-an, terdapat majalah Sastra—yang dieditori oleh H.B. Jassin dan M. Balfas—yang merupakan salah satu majalah utama bagi penulis non-Lekra dan anti-Lekra. Majalah Sastra ini sempat terlibat perdebatan dengan koran Bintang Timur—koran sayap kiri yang pro-PKI. Pada awal tahun 1963, majalah Sastra mengumumkan sejumlah penghargaan bagi cerita, puisi, dan esai yang diterbitkan pada tahun sebelumnya. Tidak lama kemudian, serangkaian penolakan atas penghargaan tersebut muncul di koran BIntang Timur dan menuduhnya sebagai sikap “kontra-revolusioner” (hlm. 119).
Salah satu upaya yang mungkin terbesar untuk mengimbangi kekuatan Lekra adalah deklarasi Manifes Kebudayaan (Manikebu) yang antikomunis. Selain untuk mengimbangi kekuatan Lekra, Manifes Kebudayaan juga memiliki tujuan menentang pengadopsian Manifesto Politik (Manipol) sebagai landasan kehidupan berbudaya nasional oleh Presiden Soekarno. Manifes Kebudayaan disiarkan pada Oktober 1963 dengan ditandatangani oleh perwakilan penulis, seniman, dan intelektual dari generasi 1945 serta penerusnya yang lebih muda.
Manifes Kebudayaan adalah kelompok seniman yang mengusung humanisme universal dan paling keras berseberangan dengan Lekra. Nama-nama seperti H.B. Jassin, Goenawan Mohamad, dan Arief Budiman (Soe Hok Djin) tercatat sebagai pengusung utama semangat Manifes Kebudayaan yang menekankan otonomi kebudayaan dan kebebasan berekspresi di luar garis ideologis partai. Selain itu, ada juga Wiratmo Soekito yang kemudian menjadi juru bicara utama bagi kekuatan budaya anti-Lekra.
Sejak deklarasi berdirinya Manikebu, Lekra langsung memberikan tanggapan yang keras dan mengambil posisi yang berlawanan dengan Manikebu. Bagi Lekra, Manikebu dianggap sebagai simbol ancaman yang ditampilkan oleh kekuatan imperialis terhadap kecenderungan progresif dalam kebudayaan Indonesia. Lekra menggolongkan bahaya Manikebu sama dengan bahaya hadirnya lembaga-lembaga milik Amerika Serikat seperti United States Information Service (USIS) dan Peace Corps.
Arsip Karya-karya Para Seniman Lekra
Pada buku ini, kumpulan karya-karya seniman Lekra dibagi menjadi dua bab. Yaitu pada bab IV dengan judul Antologi Sastra Lekra (I): Puisi dan Prosa hingga 1959‘ (hlm. 76) dan bab VI dengan judul Antologi Sastra Lekra (II): Puisi dan Prosa 1960—1965 (hlm. 151). Pemisahan ini didasarkan pada perubahan bentuk dan arah Lekra. Perubahan yang dialami oleh Lekra banyak dipengaruhi oleh kondisi politik di Indonesia yang memang berubah-ubah, misalnya seperti diberlakukannya Demokrasi Liberal (1950–1959) dan Demokrasi Terpimpin (1959–1965) oleh Presiden Soekarno.
Tidak hanya puisi dan prosa, pada hlm. 192—197, terdapat juga karya seni dua dimensi yang beberapa di antarnya terbit di koran Bintang Timur. Selain itu, pada hlm. 198—206, terdapat juga foto-foto yang berkaitan dengan Lekra, mulai dari foto Konferensi Lekra Jawa Tengah pada Januari 1958, kehadiran Presiden Soekarno dalam acara penutupan Kongres Lekra I pada Januari 1959, hingga foto Sidang Eksekutif Konferensi Pengarang Asia—Afrika (KPAA).
Pembaca juga diberi teks asli Manifesto Lekra 1950 dan Mukadimah Lekra 1959 di bagian Lampiran (hlm. 218—227). Itu terletak setelah bab VII dengan judul Epilog: Menginterpretasi Lekra (hlm. 207—217) yang merupakan bab terakhir. Lampiran ini penting karena membuat pembaca menjadi terpapar oleh “sumber primer” yang berasal dari Lekra itu sendiri. Selain itu, dengan adanya bagian lampiran Manifesto Lekra 1950 dan Mukadimah Lekra 1959, pembaca juga seperti diberi kebebasan untuk menafsirkan Lekra secara mandiri.
Kesimpulan
Buku Komitmen Sosial dalam Sastra dan Seni: Sejarah Lekra 1950–1965 ini penting karena menawarkan pandangan yang bisa dibilang lebih objektif soal Lekra. Hal itu karena selama pasca ’65, pembahasan mengenai Lekra didominasi oleh mereka yang sebelumnya pernah berseberangan dengan Lekra.
Keith Foulcher menunjukkan secara detail bagaimana perjalanan Lekra dan konflik-konflik kebudayaan yang dialami oleh Lekra demi mempertahankan keyakinan estetik dan politiknya. Lewat dokumentasi arsip, antologi karya, dan konteks sejarah yang rinci, pembaca bisa melihat bahwa konflik kebudayaan saat itu bukan soal baik dan buruk, tetapi soal pilihan jalan.
Pada akhirnya, buku ini tidak bermaksud memulihkan citra Lekra, apalagi mengampanyekan ideologi tertentu. Namun, ia mengajak pembaca untuk mempelajari sejarah kebudayaan Indonesia dengan objektif alias dengan kepala dingin dan tanpa prasangka ideologis yang kaku.
Identitas Buku
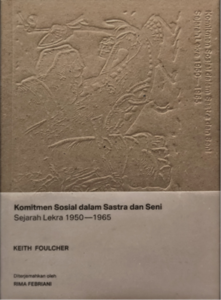
Judul buku: Komitmen Sosial dalam Sastra dan Seni: Sejarah Lekra 1950—1965
Penulis: Keith Foulcher
Penerjemah: Rima Febriani
Penerbit: Pustaka Pias
Tanggal terbit: September 2020
Tebal halaman: 238 halaman